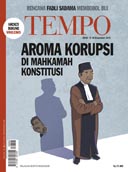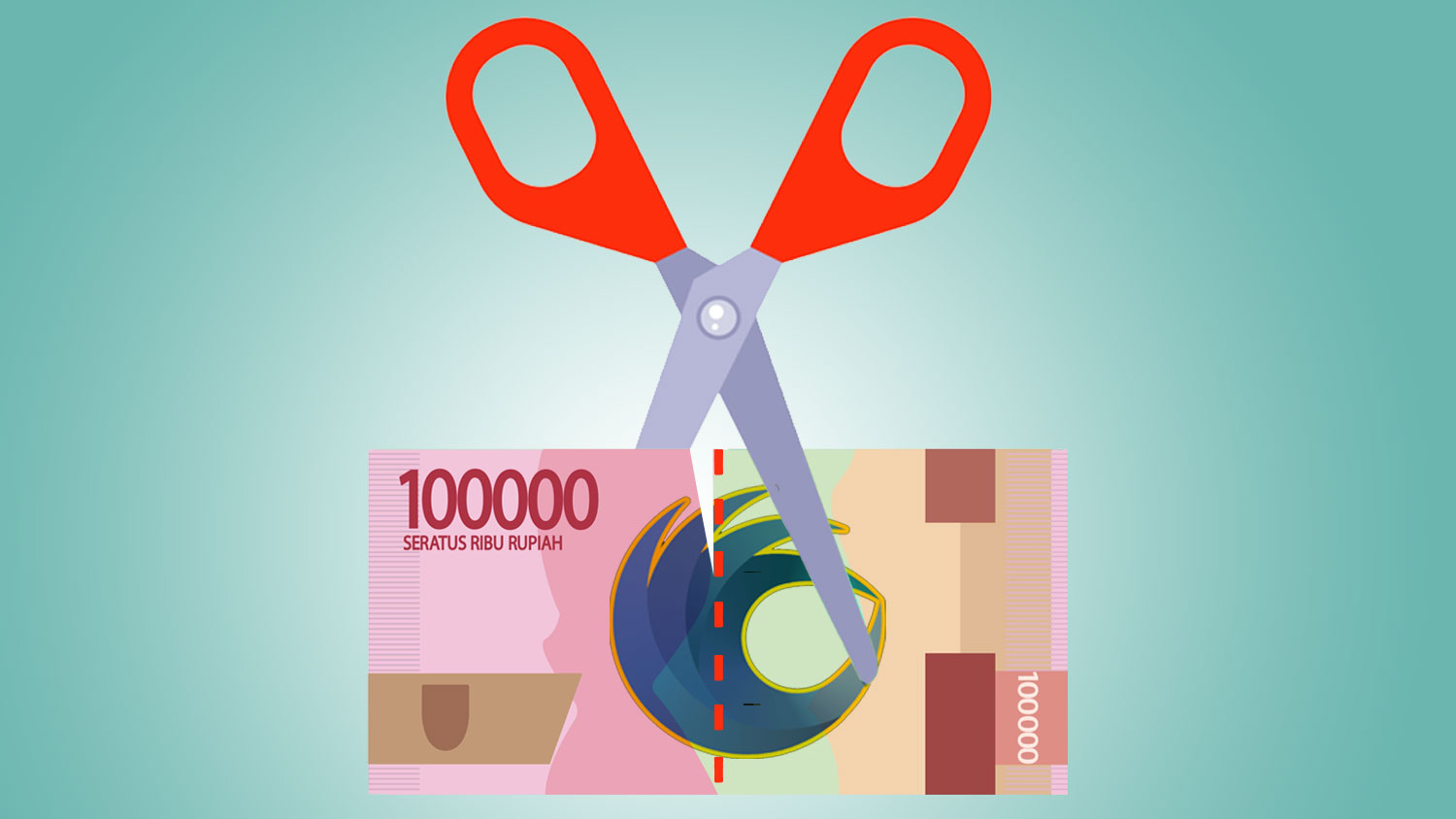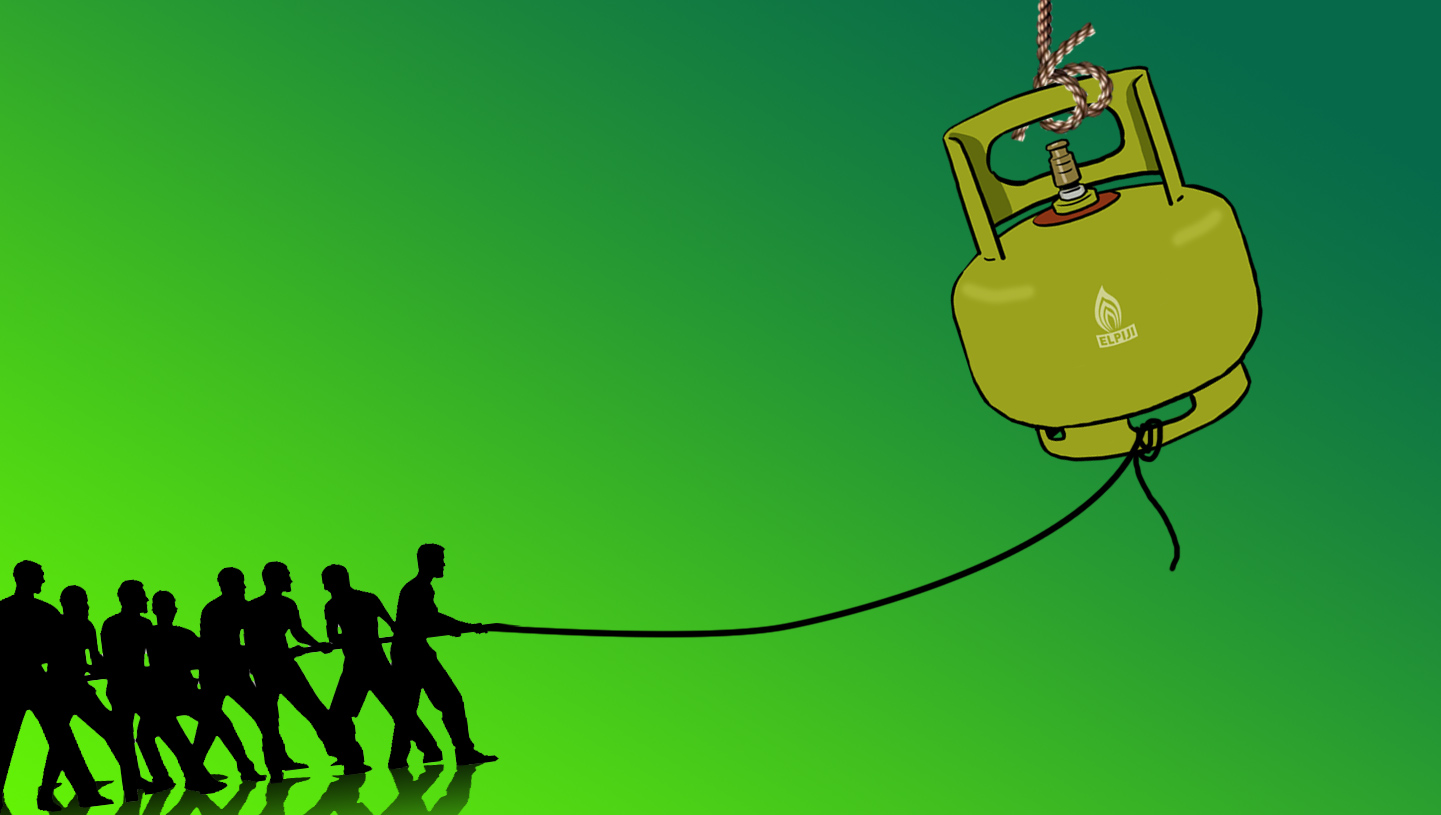Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Teman itu berkata dengan tersenyum mengasihani: ”Kamu orang pesisir. Kamu tak mengerti Jawa.”
Waktu itu, sekitar 20 tahun yang lalu, saya baru menonton sebuah tarian dari Keraton X. Saya tak menyukainya.
Saya tak tahu benarkah itu karena saya ”tak mengerti Jawa”, dan apakah ”tak mengerti Jawa” itu ada hubung annya dengan fakta bahwa saya ”orang pesisir”.
Saya memang dilahirkan di sebuah kota di pantai utara Jawa. Bagi para literati yang hidup di lingkungan Keraton Yogya dan Surakarta, pesisir adalah wilayah (atau lebih tepat: perilaku, pilihan-pilihan artistik, dan bahasa) yang berbeda dari yang didapatkan di sekitar keraton. ”Berbeda” dalam arti lebih ”kasar”, lebih ”tak pantas”, dan ”kurang Jawa”.
Maka mungkin teman itu benar: saya ”tak mengerti Jawa”.
Tapi siapa yang mengerti Jawa? Apa itu ”Jawa”?
Kata itu, ”Jawa”, tentu saja sebuah nama, untuk menyebut sesuatu yang dikemukakan sebagai sebuah ”kesatuan”. Tapi apa yang dianggap sebagai satu itu, sebuah himpunan, sebenar nya tak satu. Sebab itu tiap nama mengukuh kan sesuatu yang sebenarnya genting.
Jauh sebelum unsur-unsur yang kemudian jadi himpunan itu terbentuk, yang ada adalah kemajemukan atau multiplisitas murni, yang tak berpola, tak konsisten. Kemajemukan yang seperti itu ibarat chaos yang tak akan terjangkau pikiran. Tapi manusia berpikiran. Dan berpikir selamanya berangkat bersama proses mengidentifikasi. Syahdan, yang tak konsisten itu pun ter-satu-kan, compter-pour-un, kata Badiou.
Demikianlah ”Jawa” disebut. ”Jawa” sebuah Gestalt, sebuah sosok keseluruhan yang lebih dari sekadar pelbagai ”anggota”-nya. Ia bukan sekadar himpunan yang menyatukan Yogya, Sala, keraton, priayi, luar keraton, abdi dalem, petani.
Tapi ia tak selesai hanya di situ. Banyak sekali hal bisa dimasukkan di dalam ”Jawa”: Sala utara, selatan, keraton tahun 1930, keraton sekarang, petani tebu, petani tebu yang tak punya ladang, demikian seterusnya sampai tak tepermanai, tak terhitung. ”Jawa” adalah kata se bagai perekat, dan juga indeks, untuk pelbagai hal yang di-satu-kan itu.
Telah kita lihat, begitu banyak yang bisa ia cakup. Seperti saya katakan tadi, nama sebenarnya mengukuhkan sesuatu yang genting, yang labil. Maka dalam tiap nama ada jejak kekuasaan agar yang labil tak cepat kacau. Nama adalah hasil kesepakatan sosial. Kesepakatan ini berlangsung dalam proses panjang dan tiap kali ada pemegang hegemoni yang menentukan.
”Jawa” pada akhirnya merupakan konsep yang dibentuk oleh yang berkuasa atau berwibawa, bagian dari ”metastruktur”: Mangkunegara IV yang mengambil teladan moral cerita wayang untuk merumuskan ”jati diri” di depan kekuasaan asing, atau pemerintahan Hindia Belanda yang ingin mengontrol keragaman yang rumit itu, atau juga pemerintahan setelah kemerdekaan, untuk alas an yang mirip atau beda. ”Orde Baru”, misalnya, selain menyajikan citra Jawa dengan bangunan rumah joglo di Taman Mini Indonesia Indah, mendukung studi ”Javanologi” yang berpusat di Sala. ”Jawa” pun jadi bagian dari pengetahuan, dan dengan segera pula jadi bagian dari informasi yang mandek di dalam ensiklopedia.
Sementara itu, nama juga bukan cuma deskriptif. Ia mengandung tuntutan, atau harapan, bahwa sesuatu yang membawa nama itu seharusnya seperti yang selama ini dibayangkan. Nama ”Jawa” mengandung syarat-syarat. Sifat ”halus”, misalnya, sering disebut sebagai salah satunya. Sebab itu ada ucapan ”durung Jawa” (belum Jawa) atau ”njawani” (berperilaku seperti seharusnya orang Jawa).
Dengan demikian, ”Jawa” merupakan, untuk memakai istilah matematika, sebuah ”himpunan”, khususnya ”himpunan intensional”, sesuatu yang diniatkan dari atas.
Persoalannya ialah bahwa selalu ada yang tak tercakup dalam niat itu. Di dalam wilayah ”Jawa” ternyata ada orang-orang yang tak bisa atau tak peduli dengan ha rapan ala Mangkunegara dan Taman Mini. Ada juga orang-orang yang disisihkan. Penyebutan ”pesisir” adalah akibat dari itu semua. Pesisir adalah nama untuk ”mereka” yang bagian dari ”kita” tapi jauh di luar sana. ”Metastruktur” tak mencakupnya. Sebab itu tak menjinakkannya.
Maka dari mereka yang tak tercakup itulah, yang tak jelas antara di luar dan di dalam itu, sebuah definisi dan identitas akan guyah. Kitab ensiklopedia yang telah baku akan terterobos. Tapi dengan itu sebenarnya sebuah komunitas akan terselamatkan: ia tak akan mengeras tertutup dalam primordialisme dalam semangat untuk menegaskan diri dengan mengibarkan apa yang dianggap melekat sejak dulu dalam identitas diri. Primordialisme hanya mengejar bayangan: apa yang ”melekat sejak dulu” itu justru sesuatu yang sebenarnya tak pernah utuh. Primordialisme adalah hasil ingatan yang tebang pilih.
Memang, primordialisme kadang-kadang dinyatakan sebagai pernyataan agar perbedaan dihormati; agar keanekaragaman (”kearifan lokal”) dirawat, dengan atau tanpa nostalgia. Tapi keanekaragaman tak sama dengan primordialisme. Bhinneka tak hanya terdiri atas ”himpunan intensional”. Ia dinamika dari bawah, yang tak diatur oleh desain yang dikehendaki para pendiri Taman Mini, sang pemegang hegemoni.
Dengan kata lain, keanekaragaman adalah bayang-bayang chaos yang mencari bentuk. Bila primordialisme bersifat defensif, keanekaragaman bersifat dinamis dan itulah yang selama ini membuat Indonesia merupakan tanah air dari semua pesisir yang selalu bergerak.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo