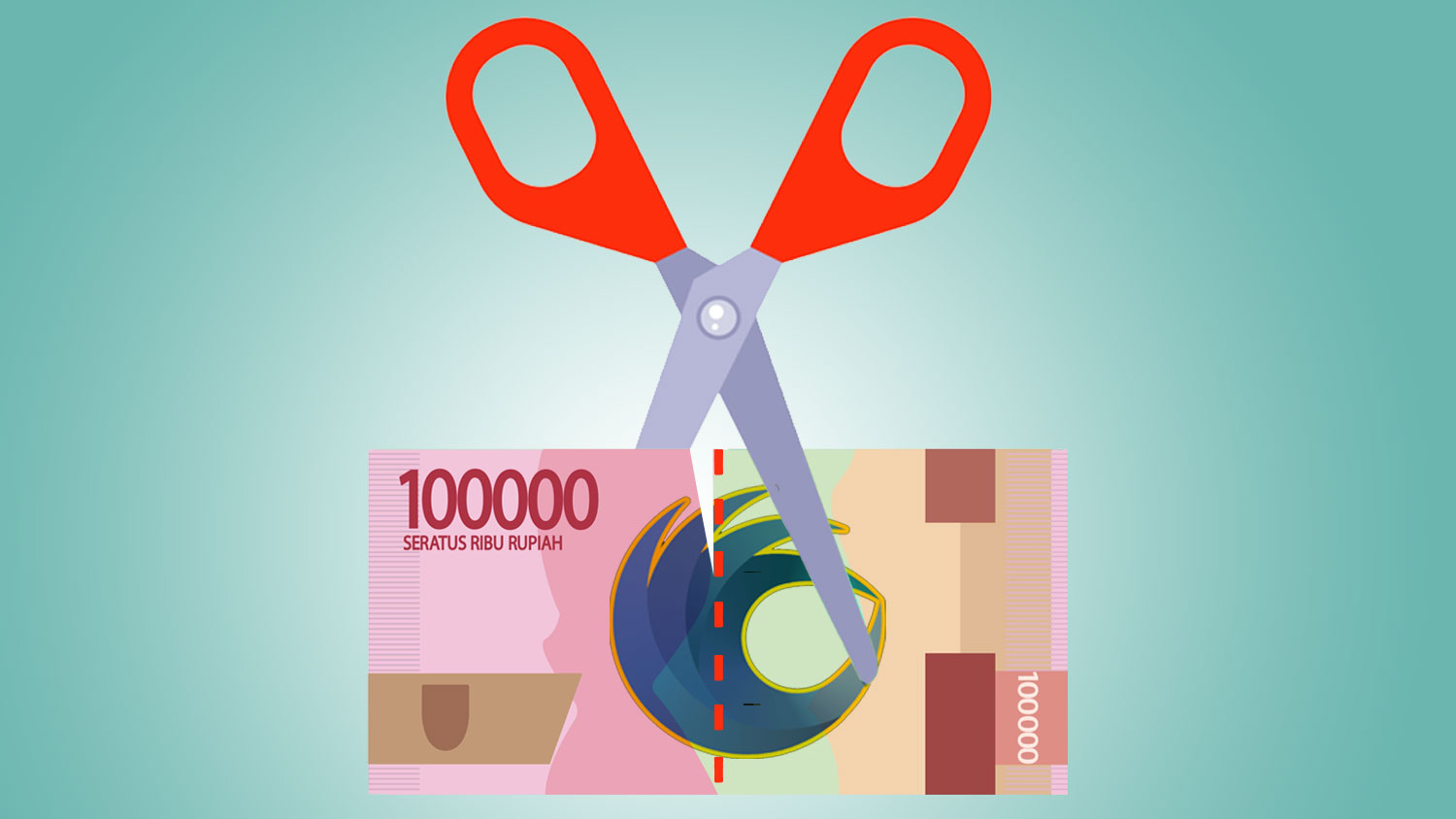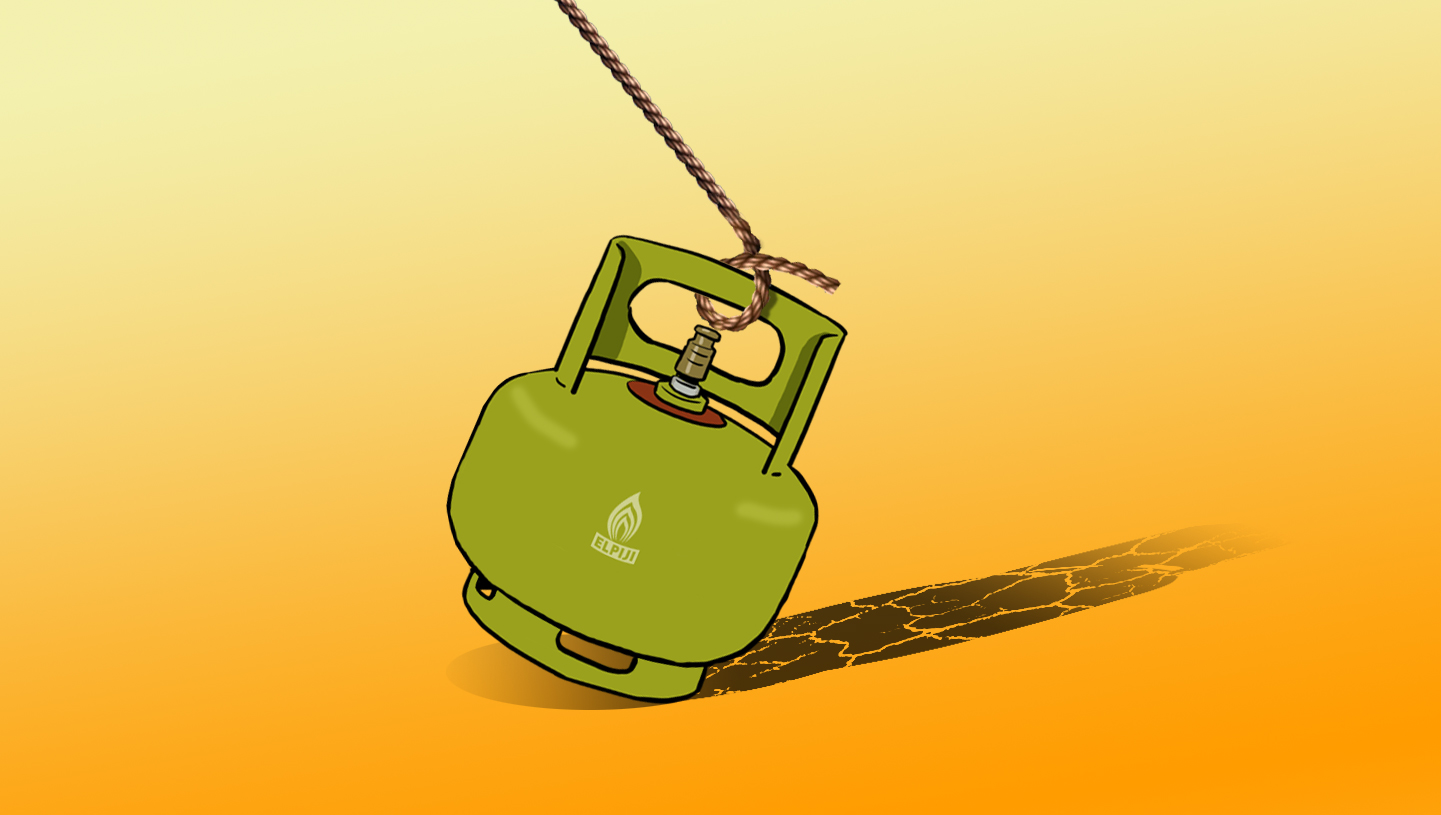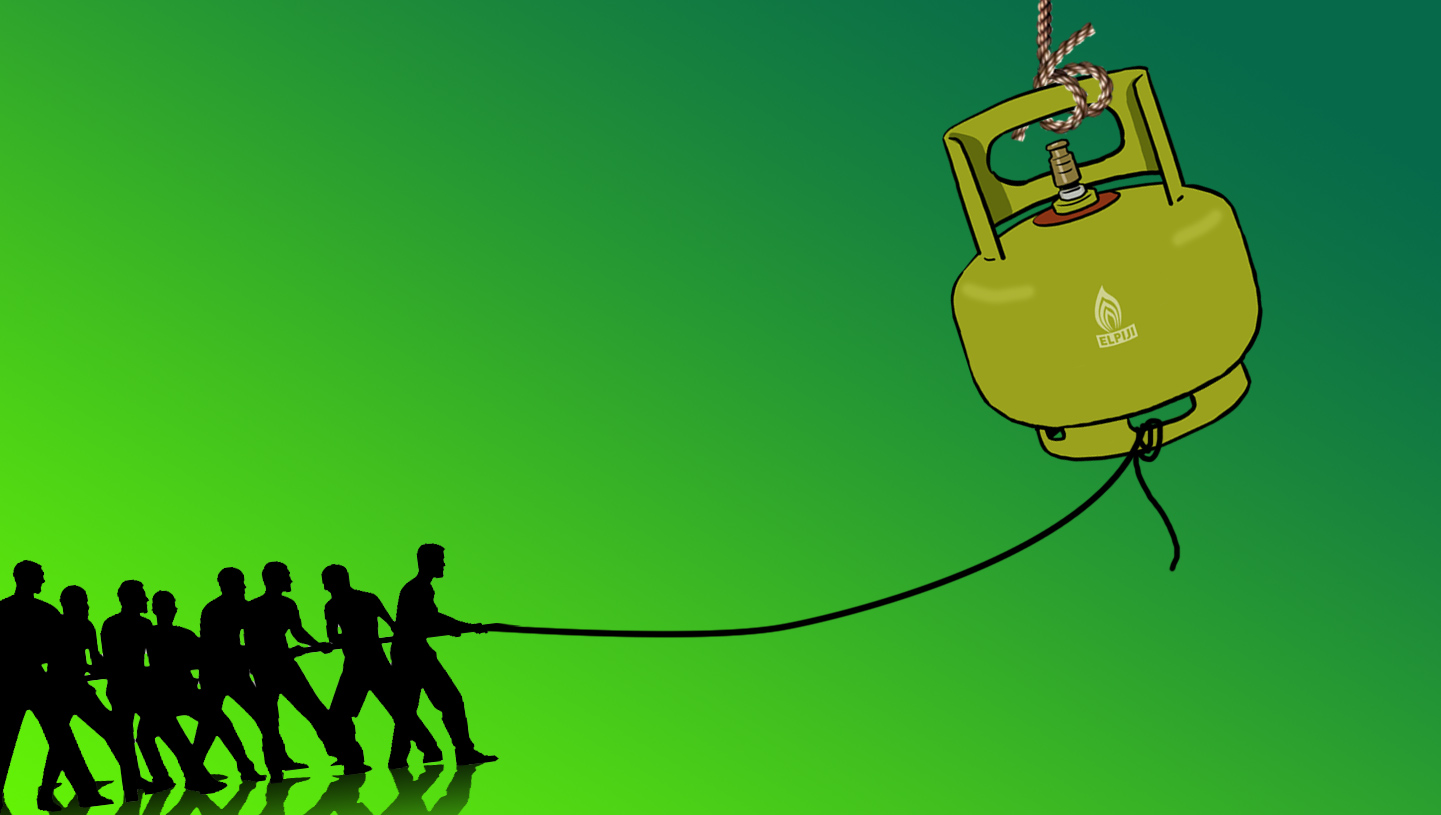Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kontroversi rencana pemerintah DKI Jaya menerapkan pajak atas penjualan makanan berskala kecil, bahkan setelah ditunda, tidaklah mengherankan. Penundaan—bukan pembatalan—itu sebetulnya mirip api dalam sekam: para pedagang sadar, sewaktu-waktu rencana pemerintah memungut bea atas usaha mereka bisa muncul kembali.
Pajak pertambahan nilai ini sedianya dikenakan pada semua kedai, termasuk warung Tegal alias warteg, beromzet Rp 60 juta per tahun—atau sekitar Rp 165 ribu per hari. Tadinya pemerintah DKI berniat memulainya per 1 Januari 2011. Rencana ini kemudian ditunda dengan alasan ”berefek pada penjualan pedagang”.
Dari segi legalitas, Gubernur DKI Jaya dan aparat ekonominya memang punya fondasi hukum. Itulah Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 37-41. Di situ tertera, antara lain, tarif pajak restoran paling tinggi sepuluh persen, ditetapkan melalui peraturan daerah. Pertanyaannya, perlukah penerapan ini digegaskan hanya karena produk hukumnya sudah disetujui DPRD.
Mari kita lihat beberapa fakta. Jakarta memiliki sekitar 20 ribu warteg yang boleh jadi memenuhi kriteria ”beromzet Rp 60 juta”. Karena masuk kategori pajak konsumsi, 10 persen pajak akan ditanggung pembeli. Efeknya mudah ditebak, tapi tak mudah diatasi.
Pedagang terpaksa menaikkan harga. Pembeli mulai tak sanggup makan di warung kecil, yang tadinya menjadi ”buffer ekonomi”: selain murah, bisa ngutang pula. Pedagang kehilangan pelanggan; bisa ratusan ribu orang bila kita ancar-ancarkan satu warteg punya 30 pelanggan. Mereka yang bergantung pada menu murah warteg, kita tahu, kebanyakan berkocek pas-pasan.
Inti perdebatan memang ihwal keadilan. Restoran-restoran menengah menjerit bahwa ada sejumlah warung berpenghasilan hingga Rp 5 juta per hari bebas menikmati subsidi dengan ”label” warteg, padahal sepatutnya mereka membayar pajak. Di sinilah pentingnya Gubernur Fauzi Bowo dan anak buahnya memetakan dengan jelas kelompok warung yang akan disasar. Sekadar perbandingan, jika usaha warung boleh dikategorikan usaha kecil, kriteria usaha kecil seturut Undang-Undang Nomor 9/1995 adalah pelaku usaha dengan kekayaan bersih Rp 200 juta dan omzet usaha Rp 1 miliar.
Poin majalah ini adalah jangan mengejar pajak ke warteg berskala Rp 165 ribu per hari semata-mata karena alasan legal. Toh, hukum dibuat untuk melayani masyarakat. Timbanglah omzet yang lebih masuk akal. Pengurus Asosiasi Warteg mengusulkan batas omzet Rp 500 ribu per hari atau Rp 180 juta per tahun. Batasan omzet memang perlu dikaji secara matang dan bijak agar selain memenuhi rasa keadilan, tak melepaskan obyek-obyek pajak yang telah ada.
Kalau perlu, buat persentase pajak secara gradual—bergerak dari 1 persen hingga setinggi-tingginya 10 persen—sesuai dengan amanat undang-undang dan setara dengan besarnya usaha. Jika tidak, pemerintah DKI sebaiknya berpindah ke ceruk-ceruk pajak yang lebih potensial, belum sepenuhnya tergarap, serta menyentuh kalangan ekonomi menengah ke atas. Mulai pajak mobil mewah, pajak progresif kepemilikan mobil, hingga pajak pembangunan sistem online untuk restoran, hotel, dan usaha hiburan: nilainya bisa sampai Rp 5 triliun sepanjang 2010 saja. Dengan cara ini, mungkin ”keadilan berpajak” akan lebih terasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo