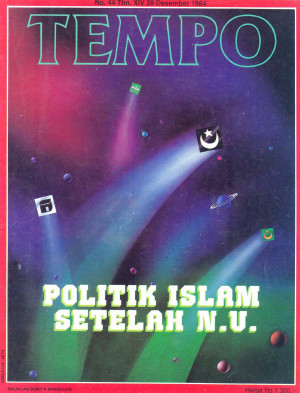KEPADA setiap orang yang menanyakan kabar Muktamar, rekan santri yang baru saja pulang dari Situbondo selalu menjawab: "dahsyat!" Sudah tentu akhir katanya bernada tinggi. Kalau ditulis, senantiasa harus dengan penthung atau tanda seru. Jelas, komentar itu bukan jawaban yang ditunggu. Bahwa pagelaran itu dahsyat, kalau Presiden sampai sederetan menteri dan panglima berkenan memberikan sambutan? Wartawan magang pun tak akan keliru menempatkannya di halaman pertama. Baru belakangan saya mengerti apa sebenarnya yang dibilangnya dahsyat. Rekan santri ini rupanya sangat terkesima dengan keberanian NU melakukan regenerasi. "Bayangkan," katanya, "semua yang terpilih di Tanfidziyah orang-orang muda belaka. Sudah muda, nyleneh lagi." Yang terakhir itu tentu saja lebih tertuju kepada Abdurrahman Wahid, ketua terpilih yang menggabungkan aneka pengalaman sebagai penulis, kolumnis, redaktur, sampai ketua Dewan Kesenian Jakarta. Barangkali karena pengalaman dan keterlibatan di banyak bidang itu, komentar-komentarnya lantas dirasakan nyleneh. Sampai-sampai ada pesan supaya sehabis Muktamar ia lebih mengendahkan diri. Namun, yang dahsyat bukanlah keberanian NU menempatkan tokoh yang kontroversial itu dalam kepemimpinan. Sebab, dalam kerangka tradisi, warna-warni yang menempel pada tokoh seperti Gus Dur, misalnya, hanyalah merupakan pepaes, dandanan yang berfungsi ke luar. Ke dalam, ada beberapa syarat-rukun lain, yang semua dipenuhinya. Bukan saja ia termasuk "orang dalam" yang sudah lama dikenal. Tetapi lebih dari itu ia bahkan berasal dari keluarga pendiri jami'iyah sendiri. Dalam hal ini, sahamnya sungguh istimewa. Ia pun sudah lulus tes sebagai reader kitab kuning besar di depan forum kiai-kiai besar, sesuai dengan tradisi pesantren. Dan yang terpenting dari semuanya, ia menguasai gaya politik yang dikehendaki. Ia bisa mempersiapkan sebuah skema, menyusuri lika-likunya, dan menyimpulkannya dengan elegant. Sesudah ini, penerimaannya di puncak hanyalah sebuah kelaziman logis. Yang ajaib, saya kira, justru menempel pada diri tokoh ini sendiri. Bahwa dari lingkungan yang melahirkannya ia bisa berkembang dalam bentuk yang begitu aneh, adalah suatu keajaiban. Pada dirinya menggumpal pesan dasar Tebuireng, Islam yang mempribumi, ideide progresif Basrah menjelang revolusi Baath, dan perspektif humanis-kerakyatan dalam soal-soal kontemporer. Ia bisa sangat progresif dalam lingkungan yang reputasinya berasal dari pengawetan tradisi, dan bermain-main di atas garis-garis silang yang serasa tidak mungkin. Sementara itu, banyak pihak, baik di dalam maupun di luar, tetap menerimanya sebagai minnaa, "satu di antara kita". Keajaiban yang lain tampak pada pemunculan K.H. Ahmad Siddiq, yang sejak Munas sampai Muktamar tiba-tiba tampil sebagai instant articulator para ulama. Dari tabung yang sudah sangat mampat oleh gaya tekan akidah dan asas tunggal, ia tampil dengan fatwa lentur yang bisa dilepas ke katup pelepas gas. Dan dalam ketegangan antara gerontokrasi dan regenerasi, ia menciptakan lembaga baru, ahlul halli wal aqdi. Dengan itu, perubahan apa pun bisa dilakukan, sebab pada akhirnya semua itu akan berlangsung dalam tilikan para ulama pinisepuh. Lembaga ini memungkinkan perubahan dalam kesinambungan - a change qithin continuity. Lakon, sutradara, dan pemain baru bisa saja berpentas, tetapi teater itu tetap teater para kiai. Jangan lupa, Situbondo adalah pagelaran para ulama. Memang, dua tokoh yang muncul secara mengejutkan itu akan banyak mewarnai kiprah NU di masa mendatang. Tetapi hanya sepanjang restu Kiai As'ad dan parapinisepuh, dan dalam idiom serta kerangka simbol-simbol yang lazim. Sebab, kaidahnya adalah, dalam NU bisa muncul tokoh yang aneh-aneh, bahkan lembaga yang anehaneh, tetapi tidak sikap dan pendirian yang aneh-aneh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini