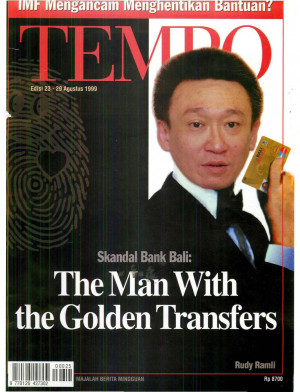Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
CERITA ini bisa dimulai dari sebuah tatapan. Di ma-syarakat yang sakit oleh penindasan, banyak hal bisa diketahui hanya dengan menyaksikan kontak mata antara dua manusia.
Penindasan itu bisa bernama kolonialisme. Ia juga bisa bernama lain. Tapi cerita ini dimulai di Kamerun, dan dimulai dengan kisah Toundi. Seseorang menceritakannya kepada saya dari novel Ferdinand Oyono, Une Vie de Boy.
Toundi, anak muda kulit hitam itu, lari dari desa dan ayah kandungnya. Ia berlindung pada Romo Gilbert. Dari misionaris Prancis ini ia menemukan sebuah jembatan. ’’Aku akan belajar tentang kehidupan kota dan orang putih dan hidup seperti mereka...,” tulisnya dalam catatan hariannya.
Tapi Romo Gilbert meninggal akibat kecelakaan. Dan Toundi pun menjadi jongos di rumah seorang komandan administrasi kolonial, tentu saja seorang kulit putih. Dengan demikian ia jadi ’’anjing sang raja”, dan si anjing-sang-raja dalam masyarakat yang terjajah praktis menjadi ’’raja anjing”. Ada sarkasme tapi juga ada rasa bangga dalam kesimpulan itu.
Tapi pada dasarnya ia memang orang yang ditundukkan. ’’Aku bukan sebuah topan. Aku adalah benda yang patuh.” Pengalamannya ketika ia menghadap Pak Komandan membekas benar dalam dirinya:
’’Ia duduk. Aku menundukkan kepala. Aku bisa merasakan matanya menatapku. Ia menyilangkan kakinya dan meluruskannya lagi. Ia memberi isyarat agar aku duduk di kursi yang terletak di seberangnya. Ia membungkuk ke arahku dan mengangkat daguku. Matanya menembus mataku….”
Seperti dalam cerita Medusa, tatapan sang Komandan mampu melumpuhkan Toundi, dan menjadikannya batu, benda beku yang tak akan berubah. Tatapan itu juga sebuah metafor untuk sesuatu yang lebih luas: setiap orang terjajah akan hadir dan tampil sebagaimana ia dibentuk oleh pandangan si penjajah terhadap dirinya. Ada ’’si Hitam yang seram”, ’’si Pribumi yang malas”, ’’si Timur yang kejam”. Dari percakapan di ruang tamu sampai dengan risalah antropologi, dari gosip sampai dengan apartheid, kita menemukan tatapan yang membekukan orang lain itu di mana-mana. Stereotip menjadi kategori sosial. Yang menyedihkan ialah bahwa si tertindas percaya akan citranya yang dibentuk kekuasaan di luar dirinya itu.
Dari sini kita sebenarnya bisa melihat: penjajahan runtuh bukan dimulai dengan bedil. Dekolonisasi dimulai ketika si terjajah menampik tatapan Medusa itu, dan menarik garis. Pada suatu hari, si Toundi, yang ingin hidup sebagai orang putih, tiba-tiba menemukan sesuatu. Sang Komandan sedang mandi dan minta diambilkan sampo. Toundi masuk ke kamar mandi dan melihat majikannya telanjang. Dan ia terkejut: Pak Komandan ternyata tidak sunat. Bagi Toundi, tanpa sunat, tuannya tampak lebih telanjang ketimbang orang hitam sebangsanya yang dengan lumrah membuka pakaian di sumur di dekat pasar.
’’Penemuan ini melegakanku,” tulisnya. ’’Ia mematikan sesuatu di dalam diriku.” Yang mati adalah ketakutan. Sejak itu, ia tak gentar akan tatapan Komandan. Majikannya marah melihat sikapnya yang berubah dingin, acuh tak acuh itu, tapi Toundi telah menarik batas. Ada sesuatu yang penting dalam penis yang disunat dan yang tak disunat: simbol sebuah komunitas, sebuah adat, sebuah keyakinan. Penis yang disunat menunjukkan bagaimana badan, sebagai alam, dikonstruksikan dan sebuah norma kultural dirautkan di sana.
Dengan demikian sebenarnya beda antara yang disunat dan tak disunat bukanlah beda alamiah yang tak bisa diubah. Namun pada momen ketertindasan Toundi, beda itu telah menimbulkan garis batas yang tak bisa diruntuhkan lagi, seperti beda antara Bani Israel dan orang Filistin dalam Perjanjian Lama. Antara yang disunat dan tak disunat, yang terjadi adalah perang.
Pada akhirnya memang badan. Artinya ’’tubuh”, bukan ’’jasad”. Dalam kehidupan Toundi dan sebangsanya, tubuh memang sudah lama jadi arena penindasan. Di situ kekuasaan dari luar datang menjangkau dan mengendalikan. Warna kulit mereka, raut rahang mereka, gelombang rambut mereka—semuanya jadi tempat pertaruhan antara jadi hamba atau jadi tuan. Diskriminasi rasial bermula ketika sang penindas menatap tubuh sang korban, dan menentukan tempatnya.
Bersama dengan itu adalah anggapan bahwa apa yang ditentukan itu memang alamiah, dan manusia tak bisa banyak berbuat untuk menafikannya. Sesuatu yang dipaksakan pun berlaku: ras, sebagaimana gender, dibuat menjadi ciri yang datang dan hilang semata-mata karena Tuhan.
Tapi sejarah menunjukkan, si tertindas bisa menampik asumsi itu. Perlawanan terhadap penindasan itu dimulai ketika tubuh tak cuma dianggap sebagai obyek dalam tatapan sang kuasa, ibarat lempung di tangan seniman keramik. Seorang teoretikus feminisme, Elizabeth Grosz, pernah mengatakan bahwa tubuh adalah sebuah ’’entitas yang transisional”. Manusia dan tubuhnya senantiasa berada dalam transisi. Tak ada yang bisa menjadikannya final. Tak ada Medusa yang akan menatapnya jadi batu. Sartre salah ketika ia memakai ’’tatapan Medusa” sebagai kiasan untuk hubungan antara ’’saya” dan ’’orang lain”. Foucault keliru ketika ia menggambarkan bahwa kekuasaan (sekaligus pengetahuan) bisa mereduksikan tubuh hanya sebagai korban, lewat satu tatapan dan pengamatan yang dahsyat.
Maka, yang benar mungkin Toundi, si jongos. Ketika ia berubah sikap, sang Komandan tak bisa menaruhnya lagi dalam sebuah kotak. ’’Kamu sudah benar-benar maboul?” bentaknya. Si jongos diam. Dalam novel Oyono, sang korban tidak angkat senjata. Tapi ia telah bisa menatap dan menetapkan bahwa sang Tuan adalah manusia yang telanjang, tanpa epaulet, tanpa kancing-kancing keemasan.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo