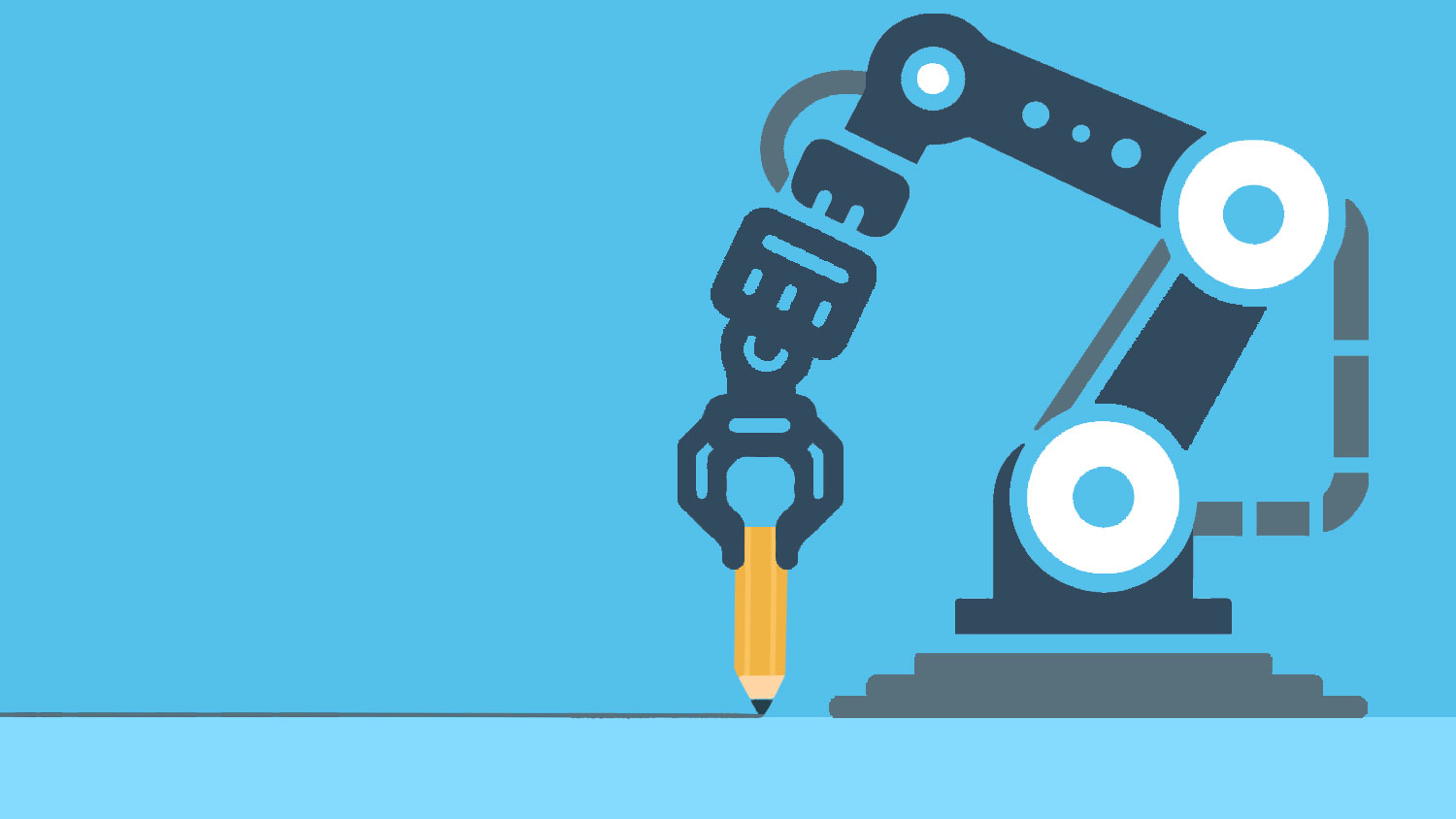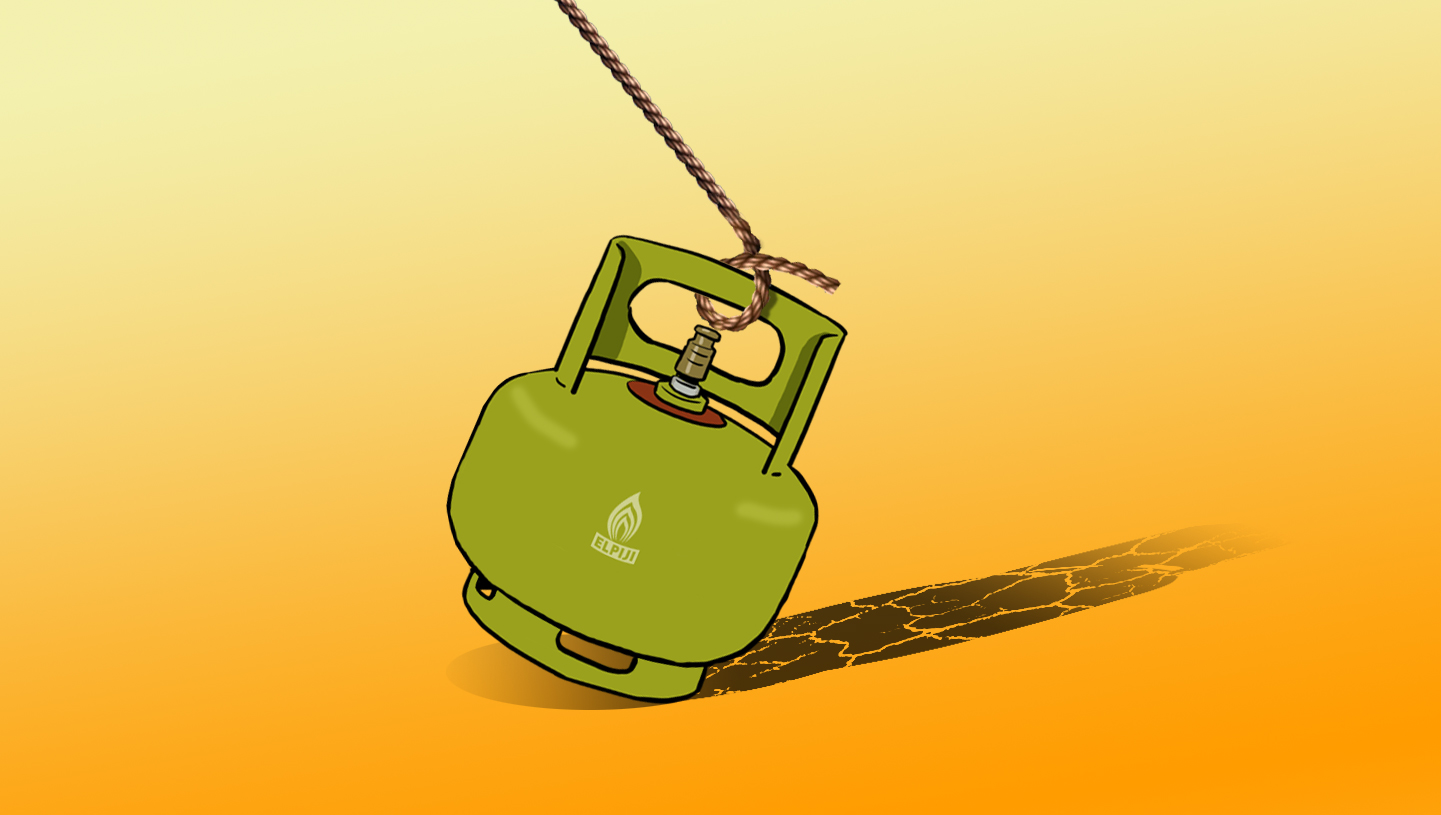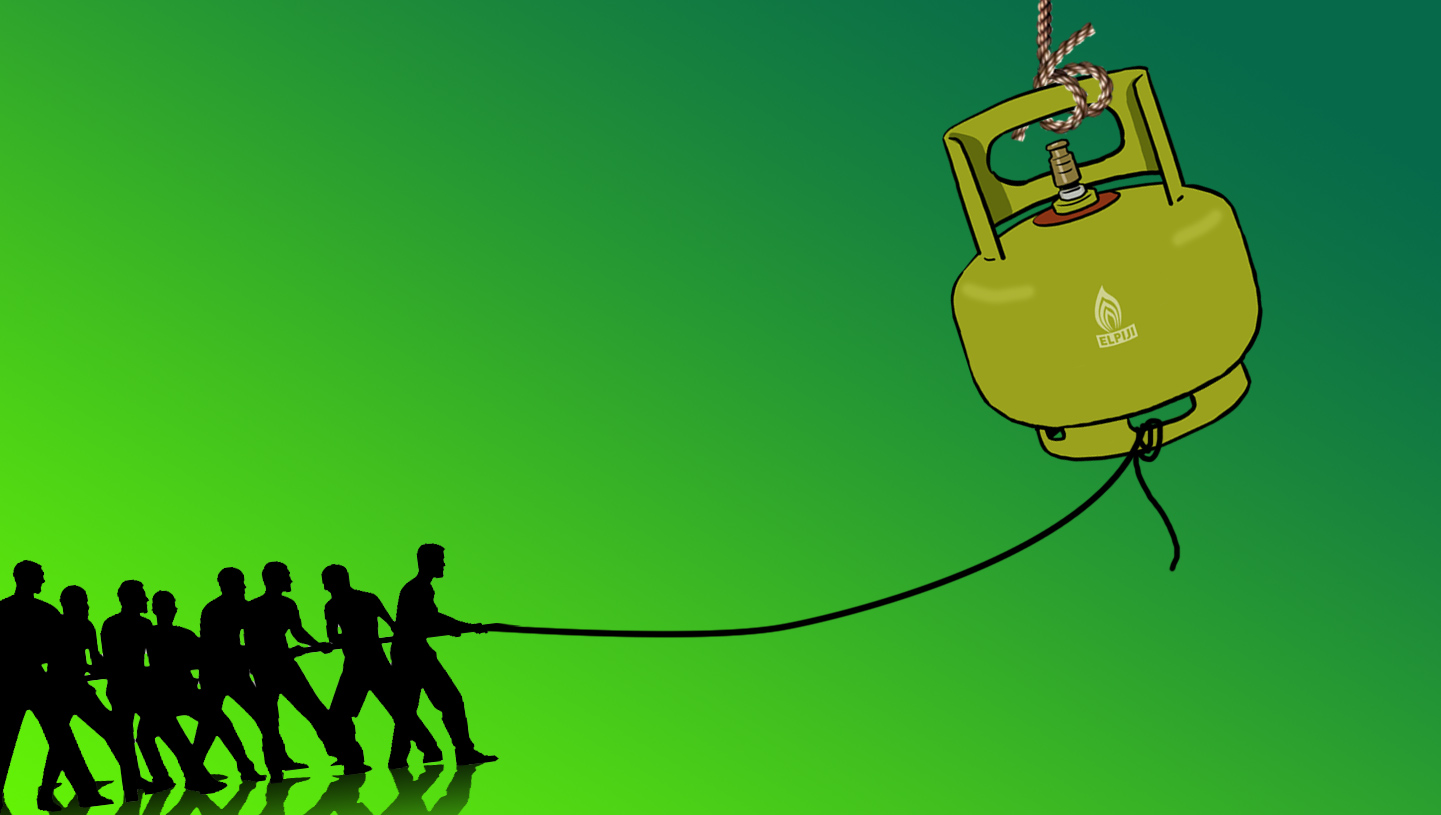Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Hasil survei politik dapat mempengaruhi kecenderungan pemilih.
Responden bisa tidak jujur ketika mengikuti survei.
Pemilih perlu menimbang pilihannya secara rasional.
Satrio Wahono
Magister Filsafat UI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menjelang penetapan calon presiden 2024, suhu politik nasional kita memanas. Hal ini terutama karena banyak lembaga survei mulai sering merilis hasil jajak pendapat mengenai kandidat-kandidat pemimpin negeri ini. Nama-nama yang muncul, antara lain, adalah bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekarang peta survei politik bahkan lebih panas karena lanskap pencalonan semakin jelas setelah partai atau gabungan partai menyebutkan nama calon mereka. Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah mencalonkan Anies Baswedan, PDIP mengumumkan nama Ganjar Pranowo, dan Gerindra menominasikan Prabowo Subianto.
Kita mafhum bahwa tidak semua survei itu murni akademis. Kadang-kadang ada survei yang merupakan pesanan pihak-pihak tertentu demi memuluskan langkah jagoan mereka menjadi orang nomor satu di republik ini tahun depan.
Survei memang menjadi salah satu faktor penting dalam menghela kesuksesan kandidat atau justru menjerumuskan sang kandidat. Artinya, survei politik ibarat senjata dengan efek trisula (triple effects), terutama dalam meraup suara para pemilih bimbang (swing voter) yang merupakan faktor signifikan dalam setiap pemilu di dunia.
Ada tiga efek dari survei. Pertama, bandwagon effect atau efek rangkaian gerbong. Efek ini sering, meski tidak selalu, dimaksimalkan oleh survei yang ingin mendorong nama tertentu. Jadi, ketika masyarakat melihat hasil-hasil survei yang menjagokan nama-nama calon di posisi teratas, mereka diharapkan terdorong untuk ikut arus gerbong opini kebanyakan dan menjatuhkan pilihan kepada nama sang calon di bilik suara nanti meskipun mereka belum tentu tadinya memiliki preferensi politik terhadap kandidat bersangkutan. Tipe-tipe orang yang terkena efek rangkaian gerbong ini biasanya mereka yang bingung menjatuhkan pilihan, tapi enggan berbeda dengan opini arus utama (mainstream).
Kedua, underdog effect atau efek kuda hitam. Dalam efek ini, masyarakat yang bersikap kritis, pemberontak, dan tidak mau ikut arus biasanya kurang menyukai nama-nama calon yang digadang-gadang secara terlalu berlebihan. Mereka justru menaruh simpati kepada nama-nama yang tertinggal atau bahkan tidak tercantum dalam daftar survei. Di bilik suara nanti, para pemilih yang terkena efek ini akhirnya menjatuhkan pilihan pada nama sang kuda hitam (underdog). Dengan memilih sang kuda hitam, mereka berharap akan mampu menggulingkan kemapanan serta menunjukkan diferensiasi preferensi politik mereka yang khas dan tak mau ikut arus.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah contoh kandidat yang sempat memetik manfaat efek kuda hitam ini. Dalam pemilihan presiden pada 2004, nama SBY kerap berada di urutan bawah. Pamornya kalah oleh nama-nama yang lebih mapan kala itu, seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Amien Rais, dan Wiranto.
Namun, seiring dengan berjalannya waktu, efek kuda hitam justru bekerja dan melesatkan nama SBY hingga terpilih menjadi presiden. Apalagi pemilihan presiden saat itu didahului kondisi SBY yang terkesan "dizalimi" oleh calon presiden inkumben Megawati, yang dikabarkan sudah lama tidak mengajak SBY mengikuti rapat kabinet sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Pernyataan Taufik Kiemas, suami Megawati, yang menyamakan SBY dengan "anak kecil yang ngambek" memperkuat efek kuda hitam yang mengantarkan SBY menuju kemenangan.
Ketiga, efek Bradley (Bradley effect). Menurut Burhanuddin Muhtadi, dalam Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral (2019), efek Bradley adalah fenomena di California, Amerika Serikat, ketika Tom Bradley, Wali Kota Los Angeles yang berkulit hitam, diunggulkan oleh banyak survei politik untuk memenangi pemilihan Gubernur California sebagai kandidat dari Partai Demokrat. Namun, hasil pemilihan malah menunjukkan bahwa George Deukmejian, kandidat berkulit putih dari Partai Republik, keluar sebagai pemenang. Ternyata banyak warga California enggan memilih Bradley karena warna kulitnya, tapi mereka menyembunyikan antipati mereka ketika disurvei karena takut dituduh rasis.
Efek Bradley ini dalam derajat berbeda juga terjadi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Saat itu banyak survei mengunggulkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tapi hasil akhir justru menunjukkan Anies Baswedan yang keluar sebagai pemenang. Banyak orang rupanya menyembunyikan preferensi mereka terhadap Anies dalam survei karena khawatir dianggap sebagai radikal dan intoleran.
Dalam konteks sekarang, misalnya, banyak survei menempatkan nama Anies di posisi terbawah dalam daftar tiga besar calon presiden. Maka, bisa jadi efek Bradley yang sesungguhnya sedang bekerja. Sejarah survei pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mungkin saja berulang, ketika responden yang disurvei mungkin segan menunjukkan preferensi mereka terhadap Anies karena takut dianggap mendukung politik identitas yang dipersepsikan sebagai rasis atau berlawanan dengan cita kebangsaan.
Lantas, bagaimanakah kita sebagai pemilih seharusnya menyikapi survei politik seperti survei kepemimpinan nasional atau calon presiden? Sebenarnya, lebih baik bagi kita menganggap berbagai survei itu sekadar sebagai referensi yang bersifat hiburan. Katakanlah semacam "surveytainment". Persis seperti kita menonton analisis para komentator sepak bola tentang siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia. Semua analis sah saja meramalkan siapa yang menang, tapi segala keputusan akan terpulang pada kita sebagai pemilih.
Yang penting adalah kita para pemilih seyogianya sedari sekarang hingga nanti mulai dengan cermat menelaah dan mengamati platform-platform, program-program, janji-janji, dan rekam jejak para calon presiden, calon wakil presiden, dan koalisi partai politik pendukung mereka. Dengan begitu, di bilik suara nanti kita dapat memilih secara rasional dan jernih siapa kandidat terbaik untuk menjadi nakhoda negeri ini untuk lima tahun ke depan.
PENGUMUMAN
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke email: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo