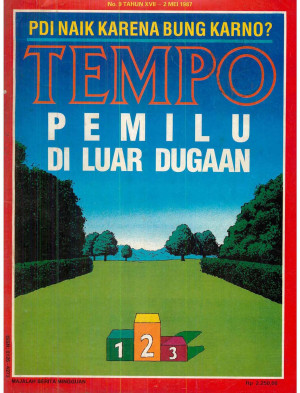GEDUNG di Jalan Imam Bonjol itu kini tak ramai lagi. Padahal, beberapa hari silam, di dalam bangunan di daerah elite Ibu Kota ini seolah ditentukan nasib dunia. Di sini, di gedung bernomor 2, bertengger papan monitor yang mempertunjukkan hasil penghitungan suara dari pemilihan umum yang baru usai, dari seluruh penjuru negeri. Di gedung Lembaga Pemilihan Umum inilah khalayak bergerombol, dengan kertas dan pena. Beringin menang. Semua orang sudah mafhum - bukan kejutan. "Kalau Golkar kalah, dalam bahasa Arab disebut mustahiiil" - kata anak-anak remaja yang turut berkerumun, dengan gaya setengah peduli. Koran-koran pun sudah berhari-hari memuat daftar perolehan suara itu, kadangkala dihiasi foto Pak Dhar, Ketua Umum Golkar, yang sedang tertawa lebar dengan gigi yang memang tidak kalah rapi dibanding milik tokoh iklan pasta. Tapi pemilu sungguh tak sama dengan sekadar tebak-tebakan Porkas atau undian angka. "Pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan demokrasi bangsa," pesan Presiden Soeharto melalui TVRI, dalam pidato resmi menyongsong saat pencoblosan Kamis pekan lalu. "Dalam bilik-bilik suara itulah wujud yang senyata-nyatanya dari rakyat yang berdaulat yang tak dapat diganggu-gugat,' tambah Presiden. Dan wujud yang senyata-nyatanya itu memang cukup mulus terbangun. Hampir 90 juta rakyat Indonesia - banyak dari mereka berdandan rapi seperti di hari raya Idulfitri - berduyun-duyun memenuhi lebih dari 300 ribu tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh pelosok. Terbukti kemudian, Golkar merangkul lebih dari 70% kepala rakyat yang berduyun ke kotak-kotak di semua provinsi itu - termasuk Aceh, yang oleh beberapa pengamat sempat dianggap terlalu tangguh untuk bisa dia rengkuh. Tapi, ya, itulah pemilu: seperti juga kotak-kotak itu tak bulat seperti bola, meramal hasil rinciannya - bukan globalnya - sama sulitnya dengan meramal skor pertandingan Galatama. Siapa sangka, misalnya, bahwa PDI yang selama ini sering diledek sebagai partai gurem - ternyata bisa naik ke papan kedua di daerah prestisius seperti Jakarta. Boleh dnngat, lima tahun silam partai Kepala Banteng ini hanya kebagian dua dari 13 kursi yang bakal ditata. Ya, meskipun gejala bangkitnya Banteng sudah terlihat d saat-saat akhir kampanye ketika tiba-tiba jalan-jalan Jakarta seolah macet total dipadati massa berkaus merah berikut ikat kepala. Usia mereka yang muda-muda dan sangat spontan itu memang bisa segera mengingatkan orang ke massa kampanye 1982 - ke massa PPP yang berkaus dan ikat kepala hijau. Sayang sekali ada keberingasan yang dianggap terlalu, atau ada Peristiwa Lapangan Banteng, yang membuat gelombang hijau itu hanya bisa memegang lima kursi, kuran satu dibanding Golkar yang pada pemilu sebelumnya - 1977- sempat mereka pecundangi. Sayang yang kedua untuk PPP: setelah pada Pemilu 1982 merosot, pada pemilu sekarang gembos. Tak cuma tertinggal jauh dari Golkar yang beroleh tujuh, tapi malah duduk sebagai si bungsu - kalah satu dari PDI yang bisa merebut empat kursi. "Sekarang PPP tak punya maskot yang mampu menarik massa, seperti Rhoma Irama dulu," kata Dr. Taufik Abdullah, pengamat politik LIPI. Sedangkan PDI justru memunculkan tokoh baru penggaet ingatan publik - Megawati Soekarnoputri, yang kehadirannya menyebarkan daya tank sendiri. Jangan lagi dibandingkan dengan Golkar yang menampilkan menteri-menteri yang seolah ingin mendekatkan diri kepada para pemihh mereka, serta puluhan artis pembuat suasana meriah. Kendati begitu, tidak selalu meluapnya massa kampanye identik dengan j umlah besar suara dalam pencoblosan, seperti kasus PDI di Ibu Kota. Lihatlah pengalaman Naro, Ketua Umum PPP, ketika berkampanye di Aceh pertengahan April silam. Umat yang hadir lebih dari dua kali lipat dari yang muncul dalam kampanye Mensesneg Sudharmono di tempat yang berdekatan. Toh partai Broer John itu malah kehilangan dua kursi - satu direnggut Golkar dan satu dicuri PDI. Itu boleh jadi agak membingungkan. Setidak-tidaknya tokoh seperti Dr. Nazaruddin Sjamsudin, KetuaJurusan Ilmu Politik FISIP UI, bertanya-tanya. Pengamat politik Aceh yang menulis masalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam disertasinya itu memang tak menyangka Golkar akan bisa unggul di sana. Tapi ilmu sosial memang bukan sederet angka atau kajian eksak. Menurut laporan Bersihar Lubis, wartawan TEMPO yang meliput pemilu di Aceh, Golkar memang tampak populer di kalangan generasi muda terpelajar. Di umumnya TPS dekat asrama mahasiswa, misalnya, partai pemerintah ini berhasil menang dengan selisih yang lumayan. Agaknya, kampanye PPP yang terlalu bersemangat justru menjadi bumerang untuk kalangan mereka. "Kampanye PPP itu emosional, tak rasional," keluh Azhari Yusuf, mahasiswa tingkat empat Fakultas Ekonomi Syiah Kuala di Banda Aceh. Katanya "Masakan mereka menunjukkan aib jurkam lain dan berjanji akan menghapus pajak." Bisa diduga, barangkali saja Azhari jadi berbeda pilihan dengan orang tuanya yang simpatisan PPP itu. Perbedaan pilihan antargenerasi memang mulai menggejala di kalangan yang berbau sekolah di mana-mana. Paling tidak, itulah salah satu kesimpulan poll TEMPO yang dilakukan menjelang pemungutan suara. Sekitar 1.200 kuesioner disebarkan di kampus universitas dan kampus pesantren di Jakarta, Ja-Bar, Ja-Teng, Ja-Tim, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dari 1.071 lembar yang kembali ke meja Redaksi, tersaring 766 buah yang dianggap memenuhi syarat karena, antara lain, diisi jawaban yang tak main-main. Responden terdiri dari pria (63,05%) dan wanita (36,95%) yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri dan swasta (65,40%) serta pesantren (34,60%). Sebagian besar (67,10%) sudah ikut memilih pada pemilu 1982. Kelompok terakhir itu ternyata menunjukkan perbedaan peri laku dalam dua kali pemilu yang mereka ikuti. Pada 1982, 45,40% dari mereka mencoblos PPP, 36,60% Golkar, 11% PDI, 7% blangko alias Golput. Tapi pada pemilu kemarin, mereka mengaku mencoblos Golkar (39,8%), lalu PPP (23,80%) dan PDI (16,80%). Walhasil, terjadi peralihan suara dari PPP ke Golkar, PDI dan Golput. Berapa yang Golput? Sisanya, yakni 19,6% Yang lebih menarik adalah peri laku responden berlatar belakang NU (33,03%). Pada Pemilu 1982, lebih dari tiga perempat suara mereka jatuh ke PPP Golkar cuma kebagian l8,34% PDI ada juga, 1,78%. Lima tahun kemudian, PDI mendapat tambahan dari mereka menjadi 4,7%. Sisanya dibagi rata antara PPP, Golkar, dan Golput, masing-masing hampir 32%. Adapun pemilih pertama NU, suara mereka malah sebagian besar (54,22%) diberikan kepada Golkar, 32,53% tetap kepada PPP, dan 4,82% untuk Banteng. Golput: 9,43%. Wajar juga kalau Naro mengeluh. "Faktor NU memang mempengaruhi perolehan suara kita," katanya kepada A. Luqman dari TEMPO. Bukan hanya itu. Yang juga sangat penting: daerah kumuh Tanjungpriok, yang pada Pemilu 1982 merupakan wilayah PPP kini jatuh ke tangan PDI. Termasuk daerah Jalan Donggala, tempat tinggal Salim Qadar, atau sekitar masjid keluarga Almarhum Amir Biki di Tipar Cakung, Cilincing. Dua-duanya tokoh peristiwa Priok. Tindakan Salim Qadar (bekas aktivis partai Ka'bah berlatar belakang NU) yang meninggalkan PPP memang diikuti atau sejalan dengan rakyat di sana - tapi bukan untuk pindah ke Beringin seperti Pak Salim, melainkan ke Banteng. "Anak muda di sini rata-rata memang jadi PDI, biarpun waktu kampanye harus beli kaus sendiri," kata seorang kuli pelabuhan di sekitar Jalan Donggala. Selintas, laporan koresponden TEMPO yang meliput penghitungan suara di berbagai pelosok kota-kota besar Indonesia memang menunjukkan indikasi kenaikan suara PDI di daerah-daerah miskin kumuh perkotaan sejenis Tanjungpriok itu. Misalnya saja yang di sekitar Bekasi, di Tangerang, di wilayah Yogya, Medan, Bandung, Indramayu - yang dulu, agaknya sebagian besarnya, merupakan "kampus-kampus Ka'bah". Memang, "Tampaknya di daerah perkotaan PDI mendapat tambahan suara lebih tinggi dibanding pada pemilu 1982," kata Harry Tjan Silalahi, 53, Direktur Pusat Pengkajian Masalah Internasional dan Strategis (CSIS). Perpaduan antara indikator di berbagai TPS ini dan hasil poll TEMPO memang cenderung menyiratkan kesimpulan adanya aliran suara generasi muda: yang elite dan mereka pergi ke Golkar dan Golput, sementara yang kelas bawah ke PDI. Sebuah kesimpulan yang memerlukan elaborasi, memang. I)iperkirakan terdapat 17 juta pemilih muda baru yang tampil pada 23 April-lalu. Bukan jumlah yang terlalu gampan disimpulkan ciri-cirinya. Tapi kalaulah responden TEMPO bisa dijadikan cermin peri laku generasi muda elite lainnya, menjadi menarik untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruh pihan mereka. Dan, ternyata, sebaglan besar dari mereka (34,31%) menyatakan penampilan OPP itu sendiri yang menentukan. Sedang informasi utama performance itu mereka dapatkan dengan membaca di media cetak (46,88%), menyaksikan di tempat kampanye (24,76%), menonton TV (22,50%), dan mendengar siaran radio (4,91 %). Data itu menunjukkan betapa pentingnya medla cetak bagi Informasi penampllan OPP. Tapi itu berarti, lingkungan yang dicerminkannya umumnya bersifat kekotaan. Padahal, seperti berulang kali diucapkan Sekjen Golkar Sarwono, "Peri laku pemilih desa sangat berbeda dengan peri laku pemilih kota." Arkian, Partai Sosialis Indonesia (PSI) dulu, yang menguasai media massa, pada Pemilu 1955 terbukti hanya mampu meraih suara di bawah 6%, tak lebih. Zaman tentu sudah berubah banyak dalam 32 tahun, dan koran sudah masuk desa, resminya - di samping TVRI. Tapi kecenderungan bukan lantas dengan sendirinya berubah total. Terlepas dari media mana yang digunakan responden untuk mengamati penampilan OPP, ternyata PDI dinilai sebagai yang paling banyak mengalami penyempurnaan - tak kurang dari 46,63% yang menyatakan begitu - walaupun yang 45,80% menyatakan tak ada perubahan dan hanya 7,57%, yang menyatakan PDI semakin buruk. (Lihat Diagram). Di samping itu, walaupun citra PDI dalam garis besarnya tampil lebih baik dari OPP lain, masih ada juga hambatan bagi kalangan yang lebih Islam untuk menusuk Kepala Banteng. Masih 40,47% responden TEMPO yang beranggapan PDI sebagai partai nasionalis berbau non-Islam, sementara hanya 6,23% yang melihatnya sebagai justru bersifat Islami. Yang menarik, 87,5% pemilik pendapat terakhir ini berasal dari NU. Sisanya menganggap partai ini nasionalis sekuler. Selain penampilan OPP, faktor yang cukup mempengaruhi peri laku pemilihan generasi muda elite ini adalah orangtua (23,77%), pamor tokoh yang dicalonkan (13,22%), dan pemimpin agama yang dia anut (12,66%), meski masalah agama tak lagi dianggap mutlak dalam pemilu seperti dulu. Para pimpinan formal ternyata tak banyak punya pengaruh - hanya 3,94%. Besarnya pengaruh orangtua itu terutama tercermin dari peri laku responden anak anggota ABRI (73,33% dari mereka memilih Golkar) dan anak pegawai negeri (50,65%, idem). Tapi pengaruh itu berkurang banyak ketika orangtua memasuki masa pensiun: tinggal 44,26% bagi anak purnawirawan ABRI dan 43,90% bagi anak pensiunan Korpri. Sedangkan pada anak karyawan profesional swasta, buruh, dan pedagang, peluang memilih ketiga kontestan berimbang. Pada anak petani, peluang Golkar dan PPP seimbang, masing-masing sekitar 40%, sementara milik PDI hanya seperempatnya. Melihat kecenderungan semakin menciutnya pedesaan dan mekarnya perkotaan, boleh saja diteorikan bahwa masa depan akan mendukung perkembangan PDI. Tapi bila diperhatikan makin luasnya kesempatan pendidikan, Golkar akan tetap punya kesempatan -- asal saja dapat menarik suara yang sekarang pada menggolput. Walhasil, yang belum jelas arah majunya adalah PPP. Selain mengalami kemelut intern berlarut-larut, partai ini masih berada di masa peralihan setelah tercabutnya identitas pembawa aspirasi Islam. Sejumlah 44,09% responden TFMPO tetap menganggapnya partai Islam. "Biar bagaimanapun, PPP partai satu-satunya yang belum kemasukan unsur non-Islam," kata Faisal Biki, adik Almarhum Amir Biki. Namun, 41,30% responden yang lain beranggapan PPP tidak lagi partai Islam -- sementara sisanya menyatakan "tidak tahu." Maklum, dengan berlakunya Asas Tunggal, PDI memang harus segera menyiapkan diri menjadi partai terbuka. Dan bila ini terjadi, di mana lagi tempat orang-orang semacam Faisal Biki? "Kami akan bergerak dari masjid ke masjid," katanya. Tentu tak semua eksponen Islam akan mengambil langkah yang sama. Bianglala aliran dalam Islam bukan hanya terdiri dari dua warna, dan sebagian daripadanya tentu akan lebih dalam lagi masuk ke tubuh Golkar. "Karena itu, bila Golkar menjadi terlalu besar, akan timbul internal struggie antara yang ingin menyalurkan aspirasi Islam dan yang ingin menahannya," kata Dr. Taufik Abdullah. Ketua Umum Golkar Sudharmono bukan tak menyadari hal itu. "Kita usahakan fraksi-fraksi tak terjadi di dalam," katanya. "Setiap orang dapat mengemukakan pendapat. Kita tampung semua. Tapi akhirnya harus ada satu konsep. Saya yakin itu bisa ya, dengan mengembangkan kepancasilaannya." Jawaban itu bukan sekadar slogan. Sebab, seperti dituturkan Taufik Abdullah, "Pancasila, menurut Pak Harto, merupakan ideolo gi terbuka yang harus dilihat secara kritis dan kreatif." Maka, yang harus dilakukan, masih menurut Taufik, "adalah bagaimana menjelajahi ruang kepancasilaan ini hingga batas kritis dan kreatif tadi." Walhasil, kemampuan memahami keseimbangan politik baru tentu saja layak segera dikembangkan. Golkar mestinya menyiapkan kader-kadernya dengan pendidikan politik yang memadai - langkah Ini memang sedang ditunggu para generasi muda elite. Bisa diingat, berkaitan dengan itu, 80,46% responden TEMPO beranggapan peran politik mahasiswa - yang sekarang lesu - harus dihidupkan lagi. Yang jadi masalah, memang, bagaimana melakukannya. Maklum, 46,01% responden TEMPO menganggap ketatnya sistem NKK/BKK menghambat peran politik mahasiswa. Sudharmono, dalam pada itu, menyatakan, "Pelaksanaan program NKK/BKK adalah kebijaksanaan Golkar." Yang diharapkan, tentunya, bagaimana agar NKK/BKK makin lama makin menjadi tak lebih dari hanya persoalan nama. Bambang Harymurti & A. Luqman
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini