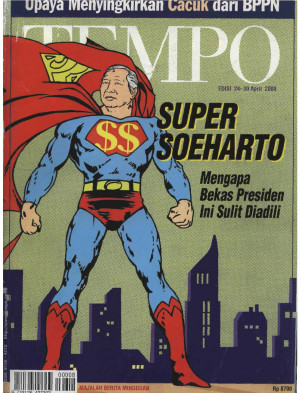SEPERTI diduga banyak orang, pengadilan itu berujung rusuh. Hampir seribu mahasiswa berkerumun di depan Pengadilan Negeri Banda-aceh, Rabu pekan lalu. Dengan yel-yel dan spanduk, mereka mengepung gedung pengadilan untuk memprotes sebuah sidang yang mereka nilai kontroversial.
Sidang itu sendiri—mengadili 24 prajurit Tentara Nasional Indonesia dan seorang sipil dalam kasus pembantaian Teungku Bantaqiah—tak terganggu. Tapi, seusai sidang, hakim, jaksa, dan pengunjung sulit keluar dari ruangan karena tertahan pagar manusia. Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Hasballah M. Saad terpaksa melompati pagar untuk bisa lolos dari kerumunan massa. Polisi yang terdesak mengejar mahasiswa. Bentrok tak terhindarkan. Meski begitu, tak ada korban kecuali seorang mahasiswa yang kepalanya bocor dipentung aparat.
Ketegangan belum luruh. Hakim Ruslan Dahlan mengeluh keselamatannya terancam. "Istri dan anak saya sudah saya ungsikan," katanya kepada Menteri Hasballah seusai sidang.
Pembantaian Teungku Bantaqiah, Juli tahun lalu, memang merupakan salah satu bentuk kebrutalan terburuk TNI, bahkan untuk ukuran Aceh yang terus bergolak. Dua ratus lebih tentara—dari Komando Resor Militer (Korem) 011/Lilawangsa, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dan Komando Daerah Militer (Kodam) Bukit Barisan—mendatangi Pesantren Babul Muqaromah milik Bantaqiah. Sang Ulama, yang sedang mengajar mengaji, dipaksa keluar dan dihujani peluru. Tak hanya Bantaqiah, 57 santrinya ikut terbantai secara sadis; 23 di antaranya dibawa dari pesantren dalam keadaan terluka hanya untuk "disekolahkan"—kata sandi untuk dihabisi—dan mayatnya dibuang ke sebuah jurang.
Peristiwa itu juga menjadi luka terbaru dalam hubungan Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta—yang memang sudah memburuk dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak aneh jika persidangan kasusnya menjadi sorotan tajam di tengah upaya sebagian kelompok Aceh yang ingin memerdekakan diri.
Di samping berjalan lambat, sidang ini dinilai tidak menghadirkan otak penyerbuan brutal itu. Dari 215 aparat yang terlibat, hanya 25 orang yang dibawa ke pengadilan. Semuanya hanya prajurit pelaksana. Sementara itu, komandan lapangan penyerbuan Letnan Kolonel Herohimus Guru tak tersentuh dan pengawas operasi Letnan Kolonel Sudjono "hilang" entah ke mana. Jaksa juga tidak merasa penting mengundang Kolonel Sjafnil Armen, komandan korem setempat.
Padahal, dari Sjafnil-lah perintah penyerbuan itu datang. Melalui telegram tertanggal 15 Juli 1999, dia memerintahkan agar Herohimus dan Sudjono menangkap hidup atau mati Bantaqiah. Perintah itu datang setelah ada informasi bahwa Bantaqiah—ulama yang baru tiga bulan dibebaskan dari penjara—menyimpan seratus pucuk senjata untuk memberontak. Sjafnil sendiri berada di helikopter yang berputar-putar di sekitar lokasi kejadian ketika penyerbuan berlangsung. Artinya, ia memang terlibat aktif dalam operasi ini.
Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang melakukan investigasi terhadap kasus ini September lalu, menyimpulkan bahwa aparat telah memvonis mati Bantaqiah dan pengikutnya tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah. Dalih TNI bahwa para korban terbunuh dalam sebuah kontak senjata juga tidak bisa dibuktikan.
Komisi tadi menunjuk lebih banyak lagi perwira menengah yang terlibat dalam penyerbuan itu. Rencana penyerbuan itu dimatangkan oleh Sjafnil bersama lima perwira lainnya. Mereka adalah Kepala Seksi Intel Korem 011/Lilawangsa Soedjono, Kepala Seksi Operasi Korem Mayor Asro, Komandan Yon 113 Letnan Kolonel Bambang Haryana, anggota Yon 328 Kapten Anton Yuliantoro, dan Wakil Komandan Yon Lintas Udara 100 Kapten Endi.
Kenapa para perwira itu tak tersentuh? Ketua Pengadilan Negeri Banda-aceh Sukarno M. Yusuf mengakui bahwa semua paket penuntutan datang dari Kejaksaan Agung. Sedangkan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengakui bahwa ia menerima pesanan itu dari polisi militer. Direktur Penyidik Pusat Polisi Militer TNI Kolonel Hendardji membenarkannya. "Perintah (Sjafnil) adalah menangkap. Tidak ada perintah untuk membunuh," kata Hendardji. Lalu, soal telegram "tangkap hidup atau mati" itu? Hendardji enggan menjawab. "Soal itu kita serahkan ke pengadilan saja," katanya.
Otto Syamsuddin Ishak, aktivis lembaga swadaya masyarakat Aceh, menuding TNI tengah melindungi perwira yang lebih tinggi: Mayor Jenderal Rahman Ghafar (Panglima Kodam Bukit Barisan kala itu) dan Jenderal Soebagyo H.S. (Kepala Staf Angkatan Darat kala itu). Mengadili Sjafnil adalah menyeret dua orang itu—seperti kasus Timor Timur menyeret Jenderal Wiranto.
Alih-alih menyembuhkan, pengadilan yang tidak adil ini diperkirakan justru merobek luka masyarakat Aceh lebih menganga. Satu luka lagi yang membuat Aceh kian menegangkan di masa depan.
Arif Zulkifli, Tomi Lebang (Jakarta), J. Kamal Farza (Banda-aceh)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini