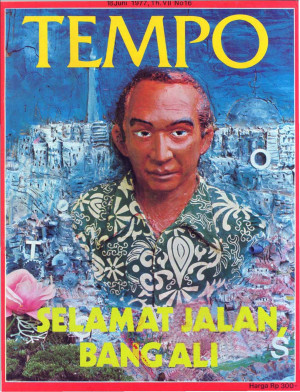"Ada, ada yang ditakuti dari Ali Sadikin itu. Apa? Ali Sadikin
itu orang yang keras.
Bung Karno, 28 April 1966
SEBELAS tahun kemudian, orang yang disebut Bung Karno "keras"
itu masih tetap keras. Ia masih bisa berteriak "goblog" kepada
pembantunya yang berbuat salah - dengan kemarahan yang termashur
itu. Dan ia masih seperti mendera dirinya sendiri dalan bekerja.
Hari-hari terakhir masa jabatannya (akan habis menjelang akhir
Juni ini - lebih cepat dari dugaan semula) ia lalui seolah-olah
ia masih akan tetap ditugaskan di sana. Sampai di kantor jam
6.30 pagi. Kembali ke rumah jam 14.00 atau setengah tiga.
Kemudian mulai jam 17.00 bekerja lagi di rumah termasuk menerima
tamu - hingga jauh malam.
Ia juga masih memilih olahraga yang keras. Bukan sesuatu yang
bisa dilakukan sambil jalan, melainkan latihan kesegaran jasmani
di ruang khusus di Balai Kota tingkat 4. Latihan berlangsung
sampai satu jam, antara lain dengan mengayuh ergo-cycle. Hal ini
dilakukannya dua kali seminggu, di samping berenang di kolam
renang di rumahnya atau terkadang, di tempat lain. Sekali-sekali
ia main sepakbola. Dua pekan yang lalu misalnya ia jadi kiper -
posisi yang kurang cocok dengan semangatnya yang gelisah.
Tapi dengan umur 50 tahun, fisiknya tak urung toh berubah.
Berkat latihan dan disiplin dirinya (ia tak merokok), ada yang
pernah menaksir bahwa kondisinya lebih muda 10 tahun dari
umurnya. Namun rambutnya jelas menipis. Kerut di dahinya lebih
kentara. Ia nampak lebih berat, meskipun tidak pernah gendut (77
kg dengan tinggi 1.78 m). Semua itu menyebabkan ia lebih nampak
angker atau berwibawa. Yang membantu Ali Sadikin, selain
keluarga yang tenang, barangkali juga sifatnya yang spontan,
yang meledak dalam marah dan ketawa. Ia tak diam menahan
perasaan. Tapi siapa yang tidak di"makan" oleh tugas selama
sebelas tahun, dengan kota yang setegang Jakarta?
Sadikin bukan perkecualian. Ia mulai dari tidak tahu apa-apa
sama sekali tentang kota. Ketika Bung Karno, Presiden pertama
dulu menunjuknya jadi Gubernur, isterinya - dokter gigi Nani
Sadikin tertawa karena merasa aneh, bahwa suaminya dapat tugas
itu. Tapi pengalamannya sebagai komandan dalaun ketentaraan toh
ternyata berguna. Terutama dalam mengatur kembali organisasi
pemerintahan daerah. Dan agaknya di sinilah prestasi Ali Sadikin
yang terutama yang justru selama ini tidak terlihat. Seperti
kata seorang pembantunya: "Bagi banyak orang luar kepemimpinan
Ali Sadikin ditandai oleh kejutan-kejutan dan pembangunannya
yang spektakuler. Tapi bagi kami yang di dalam ada hal yang
lebih penting lagi ia meletakkan dasar tertib pemerintahan yang
sebelumnnya belum ada".
Pembangunan yang spektakuler, selain menyebabkan ia dipuji tapi
juga menyebabkan ia dicela -- dan contohnya amat banyak tentang
itu. Juga ucapan-ucapannya, sering mengandung humor tapi terlalu
blak-blakan, sering menyebabkan ia menambah jumlah musuh. Tapi
agaknya apa yang dilakukannya dalam organisasi pemerintahan
daerah sukar untuk dibantah manfaatnya-juga setelah ia tidak ada
di kantor gubernuran nanti. Soetjipto Wirosardjono, Kepala Pusat
Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta, dalam
tulisannya dalam majalah Prisma baru-baru ini menyebut beberapa
pembaharuan yang dilakukan Ali Sadikin secara diam-diam di situ:
� Ia mengakhiri dualisme. Sebelumnya, dalam pemerintahan daerah
terdapat dua perangkat yang secara strukturil terpisah. Yang
satu adalah perangkat pemerintahan pusat (lazimnya disebut:
pamongpraja). Yang lain adalah perangkat otonom. Yang pertama
merupakan aparat Departemen Dalam Negeri, bertugas menjalankan
fungsi pemerintah umum di daerah. Yang kedua adalah aparat
pemerintah daerah, berfungsi melaksanakan tugas yang sudah
dilimpahkan kepada daerah. Dalam waktu kurang dua bulan setelah
pelantikannya, Sadikin membereskan ini - dengan doktrin hanya
ada satu perangkat pemerintah daerah.
Dengan adanya perubahan itu, "saya misalnya, tak merasa jadi
orang pusat", kata Hafiz Fatchurachman. Asisten Sekwilda DKI
yang waktu itu kedudukannya menempatkan dia sebagai orang pusat
yang bekerja di pemerintah daerah. Semangat seperti itu tak
timbul lengan sendirinya. Sebab pengelolaan kepegawaian, dari
seleksi, pengangkatan, penempatan penggajian, jenjang karir dan
semua aturan kepegawaian bersumber pada satu paket
kebijaksanaan, yang berlaku baik untuk pegawai yang berstatus
pusat maupun daerah.
� Ia mempelopori adanya "badan perencanaan daerah". Ali Sadikin
sudah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan sejak 19 Juni
1968. Baru enam tahun kemudian, Bappeda ini berlaku untuk
daerah-daerah lain, berkat Keputusan Presiden tahun 1974.
Bappeda itu kini berfungsi sebagai staf perencanaan dari
gubernur kepala daerah. Tapi waktu Sadikin memulainya, dasarnya
lebih luas dari sekedar pejabat: untuk mengembangkan
keikut-sertaan masyarakat, wakil pelbagai kepentingan yang hidup
dalam masyarakat dimasukkan. Badan ini pun jadinya bukan cuma
diisi oleh birokrasi pemerintah daerah.
� Ia membagi wewenang kepada mereka yang di bawahnya. Sampai Juni
1966, para kepala perwakilan pemerintahan umum di tiga wilayah
Jakarta yakni para bupati -- tidak dilengkapi dengan wewenang
yang cukup. Wewenang pengelolaan pemerintahan terpusat di tangan
gubernur. Sadikin mengubah ini. Dilakukan "dekonsentrasi
teritorial dan fungsionil", dengan membentuk wilayah
administratif "kota", kecamatan dan kelurahan.
Itu, tentu saja, cuma beberapa hal pokok yang dilakukannya. Yang
lebih penting agaknya bahwa ia mulai tidak dengan sikap seorang
petugas yang terhimpit oleh peraturan. "Saya lebih suka
menyebutkan dia juga sebagai entrepreneur", kata Hafiz, ketika
ditanya tidakkah perobahan yang dilakukannya di tahun 1966 itu
melanggar Undang-Undang yang ada. Dengan kata lain, Sadikin bisa
dikatakan mendahului perubahan peraluran -- yang kemudian memang
sering terjadi. Mungkin itulah sebabnya, dengan sifat "keras"nya
itu, ia bisa nampak seperti mau memaksa pergantian ketentuan.
Soetjipto memberi contoh: ada aturan bahwa dari pungutan
pendapatan tanah daerah dapat 40%, pusat 40%. Sadikin bilang
"tidak". Pusat 20% saja. Caranya, kata Soetjipto, "dengan
membuktikan bahwa logikanya lebih genah, lebih adil".
Tidak semua kepala daerah, tentu saja, berani begitu. Ali
Sadikin sendiri pernah mengatakan, bahwa kelebihannya untuk
berkata blak-blakan kepada pusat adalah karena ia salah satu
perwira ABRI yang paling senior. Sikap demikian juga
diharapkannya bisa jadi semacam "pendidikan demokrasi", karena
tak serta merta mengiyakan bahwa yang dikatakan oleh atasan
mutlak benar (lihat: wawancara, hal. 15). Tapi agaknya orang di
"pusat" tak selamanya senang. Soegiharto, Ketua Fraksi Karya di
DPR, misalnya menyuarakan perasaan itu dengan mengecam sikap
Sadikin.
Bagi para pembantunya, sikap Bang Ali punya dasar. Kata
ajudannya, Chris Hutapea, ucapan Ali Sadikin "sebetulnya
dimaksudkan untuk memancing reaksi", sedang "sebelumnya sudah
dilakukan usaha yang cukup lama". Soetjipto punya penjelasan
yang agak lain. Menurut "etik kekaryaan" memang "maki-maki harus
dilakukan di dalam", namun Ali Sadikin juga dididik dalam
pasukan komando. Dalam saat-saat tertentu, ia menggunakan
"terapi kejutan". Kita bikin kejutan, kita juga harus tahu
konsekwensinya, begitu katanya. Setelah itu ia mengukur
kekuatannya: kira-kira ia bisa terus dengan rencananya atau
tidak. Ada juga yang tidak bisa terus. Ir. Wardiman dari Biro II
DKI, menunjuk misalnya ide "defisit aktif". Ali Sadikin
memperkenalkan ini: prinsipnya, penerimaan 100 sementara
pengeluaran 120, dengan kekurangannya dicarikan gantinya oleh
DKI sendiri. Pusat tidak mengizinkan ini, karena bisa ditiru
oleh daerah lain, sementara defisitnya belum tentu benar.
Betapapun Sadikin masih suka mencoba menawar. Tapi lebih dari ke
Marinirannya, ia juga nampaknya memang suka adu argumentasi.
Ketika suatu kali Arief Budiman (kini di Universitas Harvard)
dianggapnya "mengacau" di Gelanggang Remaja, Ali Sadikin dalam
suatu kesempatan melantik anggota Dewan Kesenian (a.l. Arief
termasuk yang dilantiknya) langsung mengecam Arief. Dan langsung
dari podium ia menantang: "Rief, jawab Rief!" Arief memang
kemudian mendebatnya, dan Gubernur melayaninya, dan antara
keduanya tak ada perasaan dongkol lagi. Tak mengherankan bila
kaum intelektuil, para tukang kritik itu, terutama mahasiswa,
merasa ada kecocokan dengan Sadikin. Mereka diam-diam mengagumi
orang ini, orang yang tak takut dan tidak sakit hati bila
dibantah. Mungkin itulah sebabnya Ali Sadikin, yang diangkat oleh
Sukarno dan pernah dicurigai sebagai unsur "Orde Lama" oleh para
muda di kampus UI, kemudian terasa dekat bagi mereka. Diakui
atau tidak, sumbangannya dalam meredakan beberapa peristiwa
demonstrasi mahasiswa ialah karena ia tidak dianggap apriori
memusuhi dan mencurigai mereka.
Dan itu amat penting kiranya bagi sebuah ibukota. Ibukota
negeri-negeri berkembang biasanya mengandung "arus bawah" yang
suka beroposisi. Di Jakarta misalnya, di tahun 1966-1967,
demonstrasi anti Bung Karno paling keras terjadi. Sebab
sementara orang di daerah masih menganggap sang pemimpin
bagaikan setengah dewa, di Jakarta segala gosip yang ganas
berkecamuk -- dan fakta-fakta yang buruk memang dengan lebih
mudah terpaparkan tentang para bapak dan ibu pembesar. Kontras
kehidupan dalam kota yang penuh persaingan ini juga menyebabkan
rasa tak puas mudah terbit - meskipun tidak disuarakan oleh
pers, seperti halnya di zaman Orde Lama dulu, di mana pers
dibungkam. Bagaimana Ali Sadikin menghadapi ini? Mungkin
sikapnya yang gemar adu argumentasi itu cocok untuk tidak
melihat gejala "oposisi-oposisi"-an itu sebagai ancaman -
apalagi ia nampaknya cukup populer. Tapi mungkin juga filsafat
kepemimpinannya menolong. Dalam pidatonya di Manila waktu
menerima Hadiah Magsaysay 31 Agustus 1971, ia menyatakan bahwa
gubernur yang baik adalah "gubernur yang sepenuhnya menempatkan
dirinya sebagai seorang kepala pemerintahan daerah, dari mana
pun dia berasal dan afiliasi politik apapun yang dia anut".
Baginya, "menempatkan diri sebagai seorang gubernur juga berarti
meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau
korps". Dan agaknya kritiknya kepada tiga kontestan sekaligus di
waktu pemilu yang baru lalu - meskipun ia ikut dalam rapat umum
Golkar - merupakan pelaksanaan dari prinsipnya.
Ia nampaknya berusaha benar, untuk bersetia kepada sikap fair.
Kepada TEMPO yang mengkritiknya ia pernah berkata, bahwa tidak
fair kalau dia tak diberi kesempatan membela diri dan membantah
kritik. Ia sendiri membaca sejumlah besar koran dengan lahap,
dan dengan kecepatan yang mengagumkan ("Mungkin dia belajar
teknik baca cepat", kata seorang pembantunya). "Pak Ali
seolah-olah diperintah koran", kata Humas DKI Syariful Alam.
Waktu sarapan ia baca koran, di jamjam kantor awal ia baca koran
-- dan mencoret-coret dengan spidol merah apa saja yang harus
diperhatikan, dan diperbaiki, oleh anak buahnya. Sedikitnya
sehari 20 penerbitan yang ia "garap" begitu.
Tapi adakah ia bersedia menerima kritik dari bawahannya?
Beberapa pembantu dekatnya mengatakan "ya". Ia setidaknya
menciptakan iklim untuk itu, meskipun - kata Soetjipto - bagi
bawahannya yang berlatarbelakang "feodal", kesempatan yang ada
itu jarang dipergunakan. Ir. Piek Muljadi, Ketua Bappeda DKI,
atau Hafiz, biasa saja bila harus menunjukkan mana sikap Sadikin
yang "tidak konsisten" dengan garisnya sendiri. Seperti suasana
di rumahnya, di mana para pembantu rumahtangga nampak cukup
bebas borsikap, bawahan Sadikin menyataksn bahwa hubungan mereka
dengan Pak Ali tidak banyak bersuasana rikuh. Dulu waktu Bang
Ali baru duduk jadi Gubernur mereka punya acara keliling
bersama, menginap di rumah daerah pinggiran, dan di situlah
mereka saling kenal dengan intim. Tiap Rabu juga ada acara minum
kopi dan omong-omong bebas.
Yang mungkin tidak banyak terdengar ialah justru suara dari
kalangun DPRD. Tapi menurut Hafiz, hal ini disebabkan karena UU
yang ada menentukan begitu rupa, hingga hubungan antara
Pemerintah DKI dengan DPRDnya ibrat suami istri. Setiap kali
persoalan diselesaikan di dalam. Nampaknya memang soalnya
kemudian terserah kepada kwalitas para anggota DPRD. Tapi
kiranya asas semacam itu agak kurang konsisten dengan
"pendidikan demokrasi yang diniatkan Ali Sadikin. Toh rakyat di
luar ingin tahu juga bahwa anggota DPRD mereka menyuarakan suara
hati mereka, dan pemerintah daerah mau mendengarkan.
Itu tidak berarti bahwa benturan antara anggota DPRD dengan Ali
Sadikin tak pernah terjadi. Pengalaman Haji Hartono Mardjono SH.
angota DPRD dari fraksi PPP misalnya cukup jelas. Dalam sidang
pleno 1972 ia menkritik ketidak-beresan pembangunan terminal bis
Rawamangun. Ali Sadikin marah besar kepadanya. Di muka sidang
lenkap, tapi setolah hadirin lain diminta ke luar. Sadikin
menyerang Hartono konon sembari menghantam podium. Hurtono yang
waktu itu sudah hampir saja meninggalkan sidang, kemudian
menegtahu bahwa Ali Sadikin bisa jadi baik. Sadikin mengirim
Desun agar Hartono menemuinya. Mereka berbicara selama 5 jam.
Dan menurut seorang pembantu Sadikin. Hartono adalah salah
seorang anggota DPRI yang dihormati Bang Ali. Hartono sendirl
tak pernah sowan ke rumah Sadikin, dan Sadikin sendiri tak
menuntut agar ia disowani. "Hubungan kami tetap zakelijk", kata
Mardjono kepada TEMPO.
Maka seraya ia memuji Ali Sudikin, bahwa orang ini tak punya
sikap munailk, bila jadi tauladan bagi masyarakatnya dan "sulit
dicari gantinya", ia jugu menambahkan kritik. Ali Sadikin
kadang-kadang terlalu mengutamakan strategi, hingga
penyalahgunaan wewenang oleh bawahannya terasa seperti
dibiarkan. Tak berarti ia tak pernah menindak anak buahnya. Tapi
Sadikin pun punya batas - dan juga kesalahan, tentu saja.
Mungkin penglepasannyu dari kursi penjabat Kepala Daerah pada
saat ini justru merupakan alamat baik baginya, sebelum harum
namanya hilang dari Jakarta yang terus berubah. Sebelum orang
lupa mengenang jasa besar yang telah dilakukannya. Sewaktu kita
dengan kagum melih berkata seperti harapan orang yang
melantiknya dulu - "dit heeft Ali Sadikin gedaan, inilah
perbuatan Ali Sadikin".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini