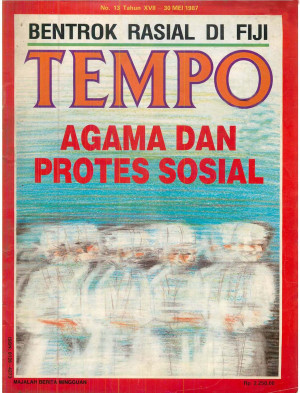KENAPA protes ? Dan mengapa umumnya tampil dengan lambang dan pernyataan agama, yang ingin murni? Banyak penyebabnya, tentu. Dan tak cuma terjadi sekarang, tak juga terbatas di Aceh. Menurut Sejarawan Dr.Sartono Kartodirdjo, yang terkenal dengan karvanya tentang gerakan protes dalam sejarah Jawa, gerakan itu berlangsung secara endemis dalam abad ke-19 dan empat dasawarsa abad ke-20. Itulah masa ketika masyarakat tradisional mengalami berbagai perubahan sosial. Masuknya ekonomi uang, introduksi sistem pajak, dan masalah penggunaaan tanah untuk tebu langsung atau tak langsung menimbulkan gejolak. Ihwal sistem pajak, contohnya, terjadi pada suatu pemberontaka di Cilegon di tahun t888. Kerusuhan di Gedangan (1904) timbul akibat konflik tanah untuk perkebunan tebu. Sebagian gejolak itu berakar pada masalah sosial-ekonomis. Meskipun begitu, manifestasinya lebih bersifat gerakan memaklumkan Ratu Adil - yang lazim disebut sebagai Mesianisme. Dari situ tampak, protes bertujuan mengembalikan suasana dari apa yang dirasakan sebagai zaman edan ke arah suasana zaman keserasian hidup tradisional. Dalam keadaan berhadapan dengan pemerintah yang menjaga ketertiban kolonial, gerakan protes itu mudah mengambil bentuk keagamaan: kehadiran Belanda yang dianggap "kafir" jadi kondisi yang cukup untuk memancangkan panji-panji Islam dalam melancarkan protes yang latar belakangnya sebenarnya sosial itu. Maka, sering pemuka agama atau ulama yang memimpin gerakan protes itu. Mereka agaknya merasa menjadl penJaga atau pemelihara moral masyarakat. Protes, dalam hal semacam ini, dilakukan untuk memurnikan kembali akhlak masyarakat yang dianggap sudah tercemar atau menyeleweng. Tak teramat mengejutkan bila protes semacam itu terjadi di daerah Aceh, justru pada saat proses "modernisasi" berlangsung lebih pesat, melalui komunikasi yang kian deras. Seperti dikatakan Dr. Astrid S. Susanto, ahli komunikasi massa yang kini kepala biro komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan di Bappenas, pembangunan atau modernisasi bisa menimbulkan adaptasi, tapi juga regresi dan agresi. Yang terjadi di dua kota Aceh dua pekan lalu itu (lihat Protes di Balik Jubah) adalah contoh regresi, atau pengunduran diri. "Mereka secara tak langsung mengundurkan diri dan proses modernisasi", kata Astrid. "Artinya, sama dengan pembekuan nilai-nilai yang ada pada mereka". Agaknya, itu adalah reaksi terhadap suatu proses yang memojokkan mereka, dan menyebabkan mereka merasa asing dan terancam. Akibatnya: agresif. "Sebetulnya," kata Astrid, "peristiwa itu menunjukkan bahwa mereka ingin didengar juga." Suatu contoh protes lain terjadi di desa Siblah Coh, kecamatan Ulim, Pidic - 172 km dari Banda Acch. Kala itu, 31 Agustus 1976, Minggu menjelang pukul 23.00 WIB, ada dua grup tari Seudati sedang manggung. Tiba-tiba 300-an datang menghentikan pertunjukan itu. Gerakan protes ini dipimpin oleh Muniruddin, yang telah 18 tahun memimpin Pesantren Babul Muarif. Alasannya: tari Seudati itu kini sering dipentaskan di lapangan terbuka. Penonton perempuan dan lelaki bercampur baur. "Dan ini haram," kata Muniruddin . Alasan lain, tari itu biasanya dimainkan sejak lewat magrib hingga subuh keesokannya. "Penontonnya menjadi malas bekerja,' ujar Muniruddin. Kecuali itu, tarian dengan menepuk dada, paha, dan diselingi gesekan jempol dengan jari manis, "bisa merusak tubuh". Lagi pula, pertunjukan tari Seudat sering ditonton orang seraya berjudi. "Nah. 'kan semuanya menyalahi agama," kata Muniruddin tegas. Bukan hal baru, memang, jika diingat 4 tahun yang lalu kaum ulama di Samalanga Aceh Utara, pcrnah menduduki lapangar pertunjukan Seudati. Protes juga muncu sekitar 10 tahun silam, di Desa Ulec Glee Kecamatan Bandar Dua, Pidie. Kala itu, 50 ulama menentang pertunjukan Seudati yang menyebabkan Kodim terpaksa mengirim dua truk tentara untuk pengaman. Soal ini menjadi serius, sampai-sampai pada 2 April 1972, Prof. A. Hasjmy menulis buku berjudul Bagaimana Islam Memandang Kesenian . Memang, ada perbedaan pandangan dalan hal tari Seudati ini. Prof. Hasjmy, kini Ketua MUI Aceh, berpendapat Seudati tidak bertentangan dengan Islam. "Kalau ada unsur-unsur yang dianggap mengganggu ajaran agama, ya, gampang, dibuang saja," katanya. Dl Jakarta, pun pernah terjadi protes atas pertunjukan tari. MUI Jakarta memprotes pementasan tari Putih-Putih di TIM (November 1976). Tarian ini sebenarnya ingin bersintuhan dengan suasana Islam. Gerak sembahyang, misalnya, dicoba digambarkan dengan stilisasi balet. Tapi pakaian para penari dianggap kurang pantas - balet toh memang harus memberi peran besar pada gerak paha dan kaki. Maka, karya Farida Feisol itu, setelah mendapat sorotan tajam di harian Islam Pelita, akhirnya dilarang dipertunjukkan terus oleh Taufiq Ismail, Rektor LPKJ waktu itu. Mana yang pantas dan kurang pantas bisa dengan cara yang lebih seru dipertengkarkan. Misalnya, sikap antipati terhadap tari pergaulan Barat, yang dulu, di zaman sebelum ada ajojing, disebut "dansa-dansi". Dalam tari ini pria dan wanita berpegangan dan saling merapatkan tubuh, mengikuti irama musik waltz atau lainnya. Bagi orang lain ini betul-betul "tiruan Belanda" atau, bahkan, "haram". Tak heran bentrok timbul. Misalnya, di awal 1952, sejumlah pemuda sampai empat kali membikin keributan di Hotel Du Pavillion, Semarang, yang biasa menyelenggarakan itu dansadansi. Gelas, piring, dan kursi hancur. Di Jakarta, pada pertengahan 50-an juga pernah terjadi demonstran memprotes dansa dan lainlain "krisis moral" - hingga sampai menyebabkan seorang perwira menengah tewas. Pada 27 Juni 1952, di Surabaya juga terjadi Gerakan Antidansa. Inilah gerakan yang tak menilai dansa sebagai kebudayaan Barat, tapi permainan yang berbahaya, yang dapat memperluas kecabulan. Wali Kota Yogya, Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, pada tahun itu juga tak mengizinkan adanya perkumpulan dansa di wilayahnya. Akibat gencarnya protes dansa-dansi ini, atas anjuran Kementerian PPK, di Surakarta pada Januari 1953 diciptakanlah apa yang disebut Tari Muda-Mudi. Inilah tari "untuk membangun kembali adat-istiadat nenek moyang, yang biasa disebut anoman system." Dengan tari ini, muda-mudi diberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain, sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan Handojodiprodjo, Kepala Djawatan PPK Kota Besar Surakarta kala itu. Yang unik ialah Tari Muda-Mudi model Solo ini toh akhirnya diprotes pula. Sebab, dinilai tak ada bedanya dengan "tayub" yang katanya sudah dikubur. Dan, juga karena ada tulisan I LOVE YOU di papan tulis, yang terdapat di ruang latihan tari muda mudi itu. Bila pada 1950-an dansa-dansi sudah dianggap maksiat, bagaimana dengan steambath dan pelacuran di Jakarta yang makin menjamur di tahun 1970-an? Sejak duduk di kelas III SMA, pikiran Fahmi Basya terusik oleh gagasan itu: menghancurkan tempat-tempat maksiat di Jakarta seperti Bina Ria di Ancol. Pada 1976, Fahmi yang waktu itu mahasiswa FIPIA UI dan dosen Sekolah Tinggi Teknik Jakarta, berniat melaksanakan rencananya. Alasannya: tak ada yang memberantas kemaksiatan itu, yang "dibiarkan, malah dipelihara oleh pemerintah". Maka, Fahmi pun mengajak beberapa temannya mempersiapkan diri, antara lain mencoba membuat bom dan alat peledak untuk menghantam tenda-tenda mesum di Ancol. Tiga bom molotov percobaan diledakkan di dekat masjid Arief Rachman Hakim, UI. Selain itu cita-cita membersihkan Jakarta juga didengungkan Fahmi dalam berbagai ceramahnya. Dengan bom. Kalau perlu minta bantuan senjata dari Libya. Fahmi juga pernah mengirim surat ke Gubernur Jakarta Ali Sadikin (waktu itu), tapi tak mendapat tanggapan. Namun, sebelum Fahmi bisa melaksanakan rencananya, ia ditangkap, 1976. Di sidang pengadilan ia menolak didampingi pembela. Ia tidak menilai sidang itu sgbagai sidang pengadilan, "tapi sidang penzariman atau penganiayaan yang diselenggarakan oleh orang-orang yang fasik atau kafir". Fahmi, yang lahir pada 1952, dan yang oleh ibunya dipandang "anak yang terikat hatinya oleh masjid", akhirnya dihukum penjara 5 tahun pada 1978. Protes sering kali muncul ke permukaan secara spontan. Padahal, sebenarnya ada konflik sosial yang terpendam, yang bersifat laten, yang untuk meledak hanya diperlukan sedikit pemantik. Contohnya, kemarahan yang meletup di Bukit Harapan, 120 km dari Medan. Sekitar 200 lelaki mendadak muncul di kawasan pelacuran itu, Jumat malam 17 Januari 1986. Dengan cepat mereka lantas membakar rumah-rumah bordil. Dalam tempo dua jam, 17 rumah "cinta" hangus. Tak puas sampai di situ, keesokan harinya segerombolan lelaki itu mendatangi kawasan bordil Bukit Pelita dan Bukit Selamat, yang berjarak 4 km dari Bukit Harapan. Hasilnya 52 rumah pelacuran lumat dimakan api. Kemurkaan penduduk sebenarnya sudah berproses lama. Pada 1976, mulanya hanya ada satu dua rumah bordil di kawasan itu. Inilah bordil yang dibangun di tengah permukiman penduduk. Berkat para sopir yang suka jajan di situ, makin lama rumah-rumah mesum itu makin banyak. Dalam tempo tujuh tahun, 40 rumah berdiri. Penduduk, sebenarnya, secara resmi memprotesnya. Sebab, para pelacur itu berjoget dan berpelukan dengan langganan tak cuma di kamar, tapi juga di jalanan. Tak cuma itu. Bagaikan sengaja memamerkan diri, para pelacur itu mandi di kamar-kamar mandi yang dindingnya cuma setinggi satu meter. Padahal, kamar mandi itu biasanya berada di halaman depan rumah. Pengaduan disampaikan ke Camat. Tapi tak digubris. Malah pelacur bertambah dengan pesat sampai 200 orang, sementara penduduk desa Halaban cuma berjumlah 300 jiwa. Kemarahan, akhirnya, tak tertahankan. Dan terjadilah huru-hara itu. Bahkan di pulau surga, Bali, pun terjadi gerakan protes. Pada September 1978, kompleks Carik di Kampung Pertapaan Denpasar Timur dibakar. Perkampungan becek di tengah persawahan yang dihuni sekitar 100 jiwa ini memang kompleks pelacuran. Meski lokalisasi WTS secara resmi dilarang di Bali, entah mengapa lokalisasi di Kampung Pertapaan diresmikan lewat suatu upacara. Beberapa banjar di sekitar kompleks itu tak mau menerima Pertapaan menjadi anggota banjar mereka karena takut disebut banjar penampung tempat maksiat. Tapi penduduk tak memprotes peresmian tersebut. Dua hari setelah diresmikan, sekitar 350 warga tiga banjar sekitar kompleks, seusai bekerja bakti beramai-ramai mendatangi Pertapaan dengan membawa bensin. Dengan cepat perumahan WTS itu disulut dan dibakar. Sejumlah orang yang diduga mengendalikan pembakaran diperiksa polisi. Ada kabar burung, pembakaran itu "direstui" kalangan pejabat Kabupaten Badung. Kabarnya, para pejabat itu menganggap cara pembakaran itu paling baik setelah gagal dengan upaya pemberantasan lainnya. Contoh terakhir ini menunjukkan, aparat pemerintah tidak senantiasa berhadapan dengan mereka yang mengeluh. Gerakan protes seperti itu memang sering membingungkan. Ia mencerminkan gejolak masyarakat yang sedang tumbuh. Sering ia terasa seperti menentang arus dan mau mengembalikan keadaan ke nilai-nilai yang terkadang dipandang kuno dan terbelakang. Namun, tak jarang nilai-nilai itu terasa mengandung hal-hal yang luhur dan hakiki, yang memang perlu tetap dijunjung tinggi. Mungkin karena itulah protes masyarakat jangan langsung di cap oposisi, yang perlu ditekan dan dibasmi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini