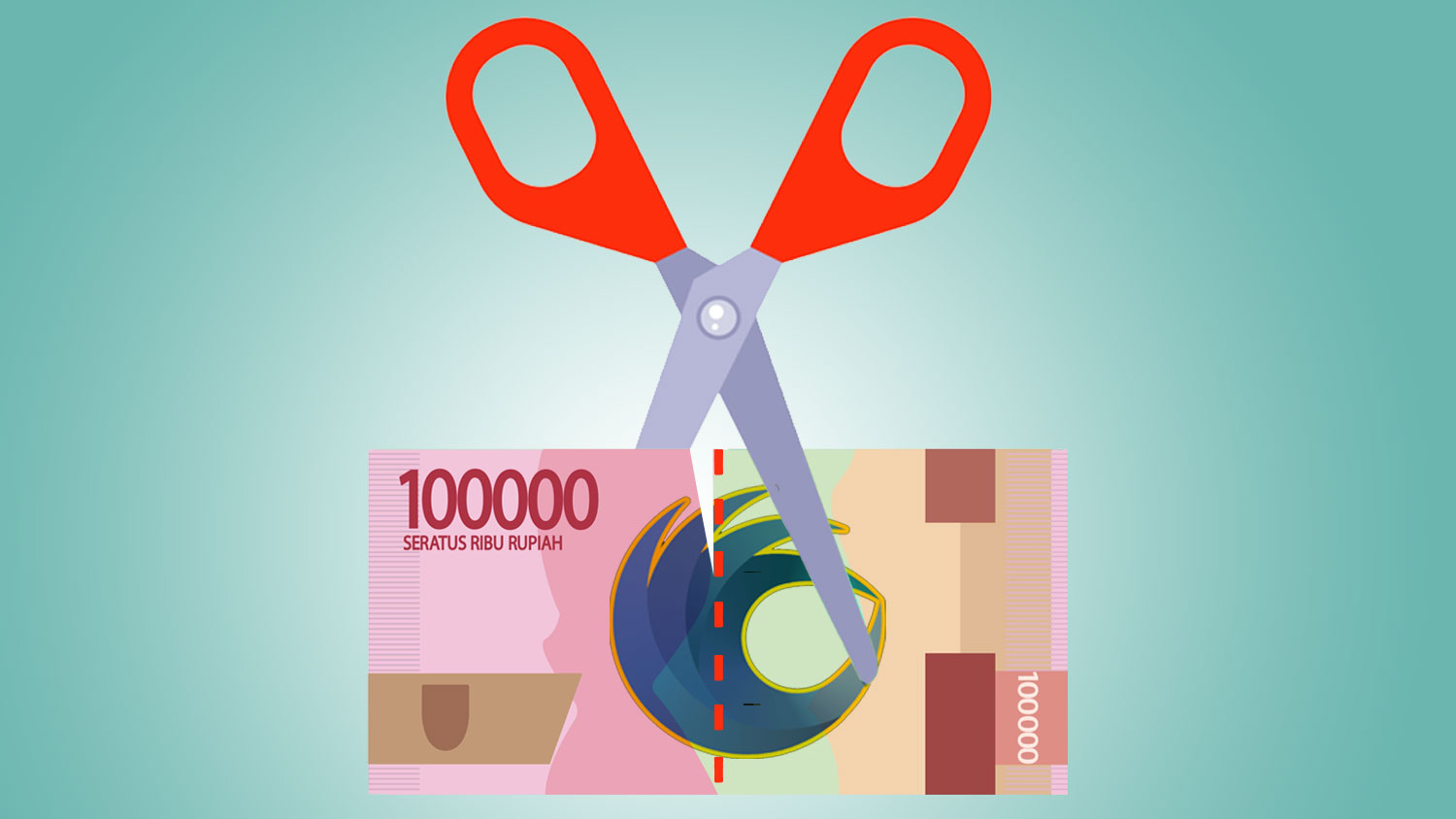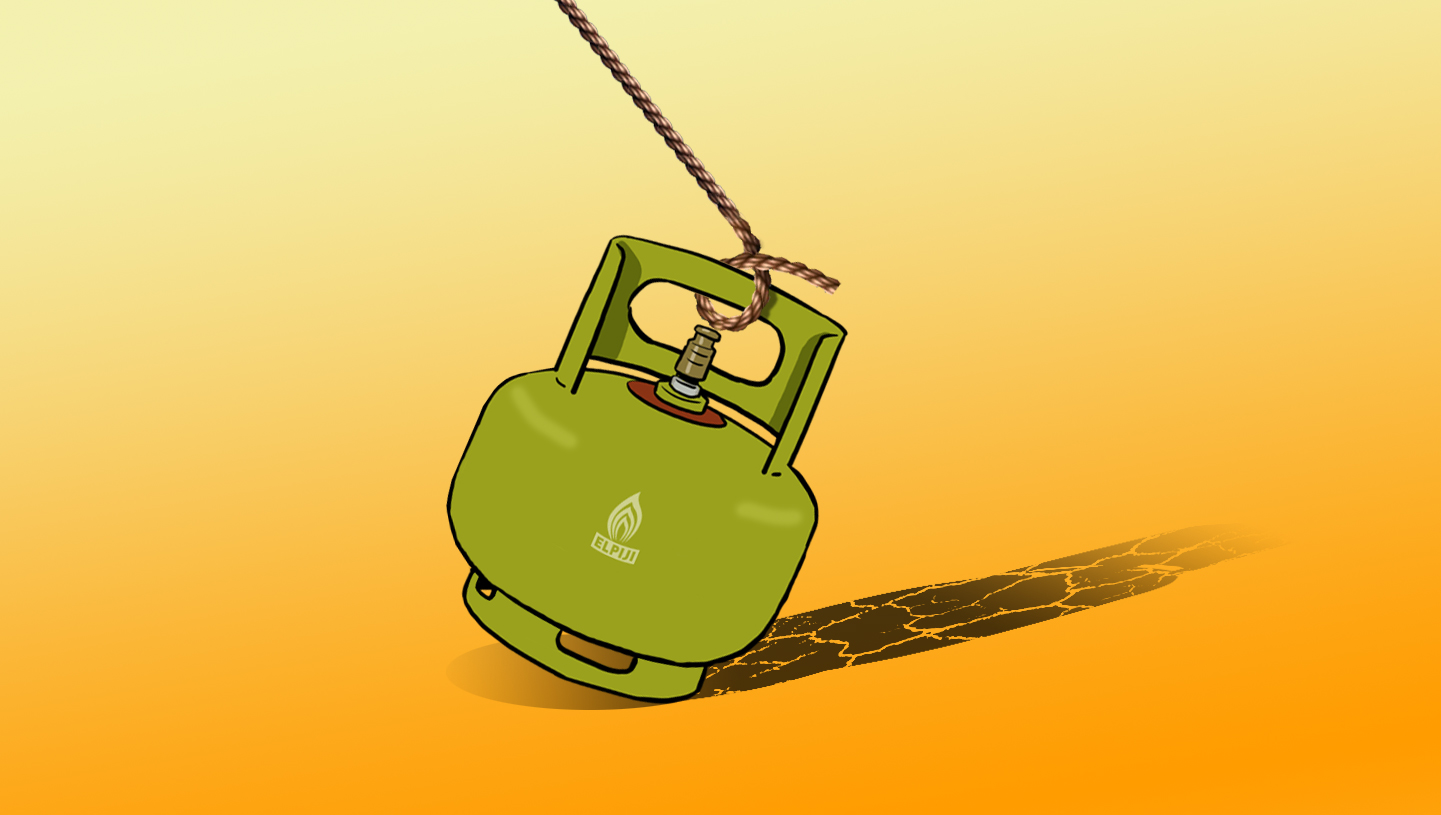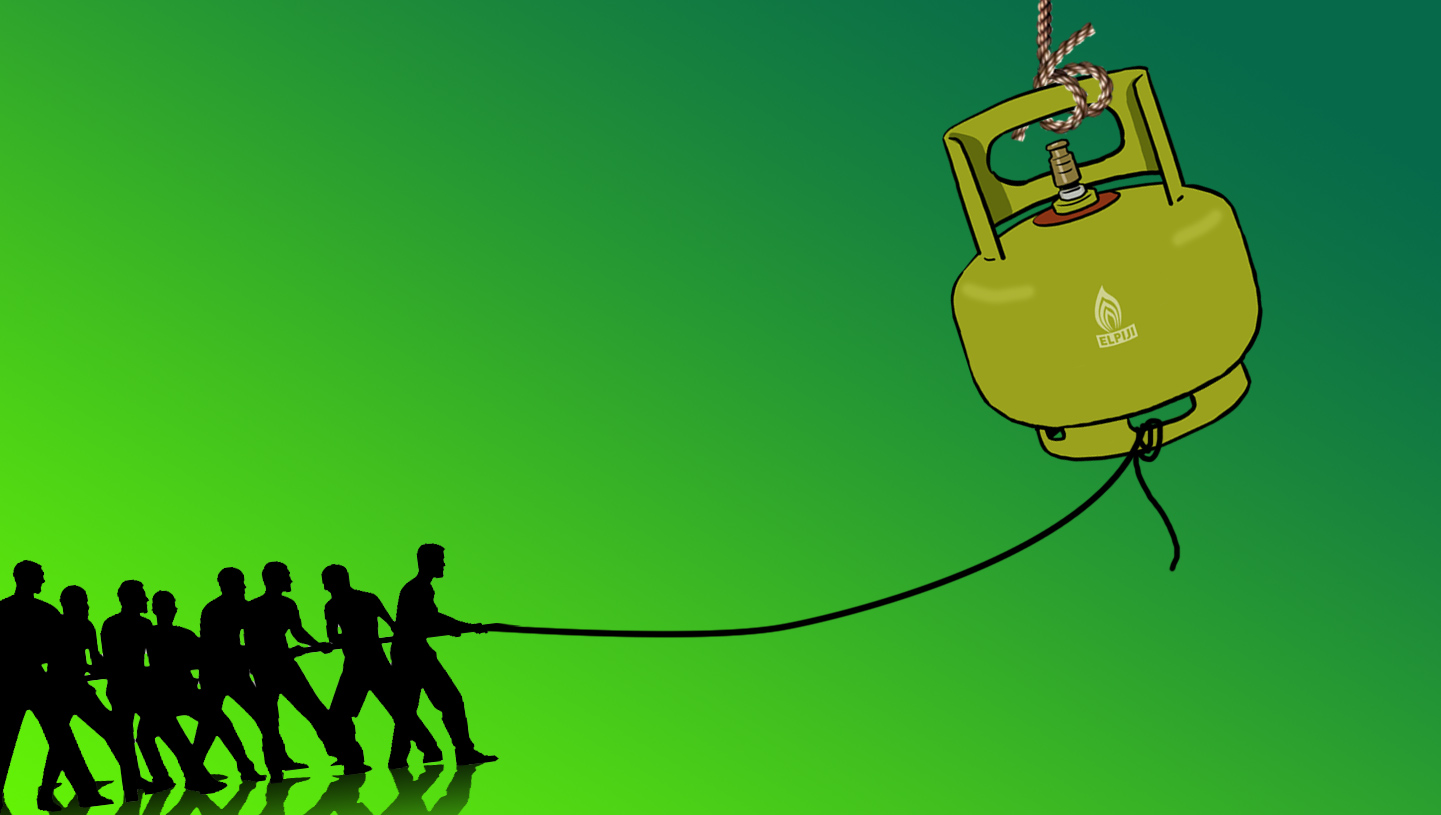Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agama dan kemarahan: keduanya begitu dekat hari-hari ini. Tak di masa lalu, seingat saya. Di waktu saya kecil, di masjid kampung kami, khatib hari Jumat selalu berdiri memegang tongkat yang diukir mirip tombak, tapi kata-kata yang terdengar dari mimbar bersahaja itu tenang, sejuk, halus. Ibadah, sebagaimana diserukan pak kiai, berarti bersyukur kepada Tuhan dengan berbuat baik kepada ciptaan-Nya. Pengeras suara yang dipasang di mustaka masjid tak memekik menguasai udara; cukup menjadi pengingat waktu. Azan itu tak selalu merdu, tapi selalu ramah.
Kini-setidaknya di kota seperti Jakarta-suasana itu tak ada lagi. Kini "Islam" seakan-akan telah jadi kata lain dari "pekik" dan "kemarahan". Ajaran jadi demagogi yang diulang-ulang: selalu ada musuh, penyelewengan, ancaman, ada yang meremehkan "agama kita". Kita diharapkan melihat Islam sebagai korban yang celaka-justru ketika masjid didirikan di mana-mana, tablig diselenggarakan di mana-mana, perempuan mengenakan jilbab di mana-mana, dan berjuta orang bersedia menabung dengan tawakal untuk ke Mekah.
Mereka yang marah, tentu saja, tak melihat Islam-yang-tak-terpuruk itu.
Tapi dari mana amarah itu datang? Mungkin paranoia dan dendam telah menular di tiap benua, di hampir tiap titik peta: Timur Tengah, Asia Tengah, Tenggara, Selatan, Eropa, dan Amerika. Kemarahan membentuk satu era tersendiri.
Kadang-kadang bentuknya pembunuhan. Kadang-kadang teriak "populisme", ketika rakyat banyak berhimpun karena frustrasi dan kecemasan, dan jadi kekuatan politik yang menolak apa saja yang "lain"-mereka yang memilih Trump yang mendirikan tembok di perbatasan, mereka yang takut dan memusuhi imigran, Islam, Afrika, atau LGBT.
Setahun yang lalu, 2017, Pankaj Mishra menulis Age of Anger: A History of the Present, dan dengan tilikan yang tajam, luas, (dan suram) ia melihat hubungan amarah, kecewa, dan abad ke-21. Janji dunia modern, harapan yang dikaitkan dengan Pencerahan dan "kemajuan" sejak abad ke-19-juga kemenangan "demokrasi liberal" dan "globalisasi" sejak abad ke-20-ternyata buntung. Kekuatan perubahan revolusioner dengan bekal Marxisme kalah. Jutaan orang tak bisa menikmati buah yang bertahun-tahun ditunggu. Kesal, cemburu, curiga meruyak. Kekerasan dan perang pun meletus, berupa konflik lokal, juga teror yang tak berhasil mengubah masyarakat-yang menyebabkan frustrasi berlanjut. Sejarawan masa depan, tulis Mishra, mungkin akan melihat kerusuhan yang sekarang bertebaran sebagai tanda awal "perang dunia ketiga, perang yang paling lama dan paling ganjil".
Kita tak menyadari itu. Mungkin karena, seperti pernah dikatakan, perang adalah bapak segala hal: orang dibantai atau terbuang, tapi juga lahir negara baru, perkembangan teknologi-bahkan penulisan novel. Kita tak selamanya waswas.
Tapi kita tak hanya mengalami perang. Seperti ditunjukkan Mishra, pada mulanya adalah amarah. Mishra tak sendiri. Beberapa tahun sebelum Age of Anger, pemikir Jerman Peter Sloterdijk juga berbicara tentang amarah dan sejarah.
Awalnya sejarah Eropa. Dimulai dengan karya puitik Homeros, Iliad, ketika Achilles, pendekar perang yang ikut mengepung Troya, mendengar sahabat dan kekasihnya dibunuh Hektor. "Di awal kalimat pertama tradisi Eropa," tulis Sloterdijk dalam Zorn und Zeit ("Amarah dan Waktu"), "di bait pertama Iliad, kata 'amarah' muncul." Ia terdengar, khidmat dan fatal, sebagai sebuah permohonan (Appell), permohonan yang tak ingin dibantah.
Dengan amarah itu, Achilles menghadapi Hektor dan mengalahkannya. Ia menyeret mayat pangeran itu mengelilingi tembok kota Troya-sebuah pertunjukan dan kebuasan yang memukau. Cerita peradaban, dengan keasyikan dan kebrutalannya, tak berhenti di sana, tentu. Achilles tak sampai hati menolak permintaan ayah Hektor agar jenazah putranya tak terus-menerus dinistakan. Amarah, dalam kisah ini, tak dituntaskan.
Salah satu thesis Sloterdijk yang menarik meletakkan amarah, dorongan "thymotik", sebagai penggerak peradaban yang lebih penting ketimbang libido, gairah erotik ala Freud. Tapi dorongan itu tak serta-merta eksplosif. Peradaban bergerak ketika manusia menyimpan amarahnya sebagai dendam yang dikelola secara efektif, untuk sewaktu-waktu dikeluarkan, dicairkan, seperti uang simpanan dalam bank. Manusia, kata Sloterdijk, membentuk Zornbankwesen, bank kemarahan. Sesekali dalam sejarah, pencairannya berbentuk Revolusi. Sloterdijk menyebut Lenin, bapak Revolusi Rusia, sebagai "entrepreneur kemarahan". Dengan Lenin, mulailah "bisnis besar kemarahan".
Agama juga tak jauh dari itu. Agama adalah "bank metafisik dendam", metaphysische Rachebank. Dalam sejarah mereka, umat agama-agama pernah ditindas; tiap agama adalah peradaban yang terluka. Islam dengan amarah adalah Islam yang dilukai kolonialisme dan disingkirkan dunia modern. Umat dan elitenya menyimpan dan kemudian mencairkan amarah terpendam itu, juga dalam bentuk teror-terutama di abad ke-21….
Sloterdijk menarik dan cemerlang-tapi sebagaimana banyak pendapat yang demikian, tekanannya satu sisi. Peradaban memang bisa digerakkan amarah yang dikendalikan dan dilepas, tapi mungkin ada yang dilupakan: peradaban juga bisa dilihat bermula ketika ego dan nafsu disingkirkan agar tumbuh sesuatu yang melebihi diri: ketika dalam puasa di padang gurun, Yesus menolak kerajaan duniawi dan memilih jalan pengorbanan sampai akhir, ketika Bhisma, dalam Mahabharata, melepaskan haknya untuk menerima takhta dan keturunan, agar dunia tak gagal.
Mungkin kita perlu melihat cerita manusia, termasuk agamanya, juga sebagai cerita pemberian, bukan cuma kemarahan.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo