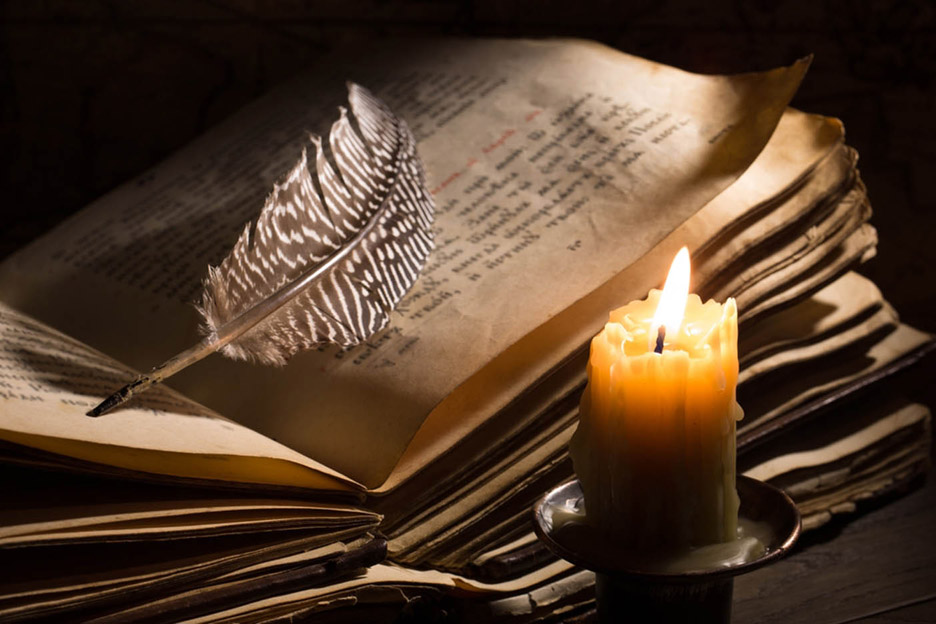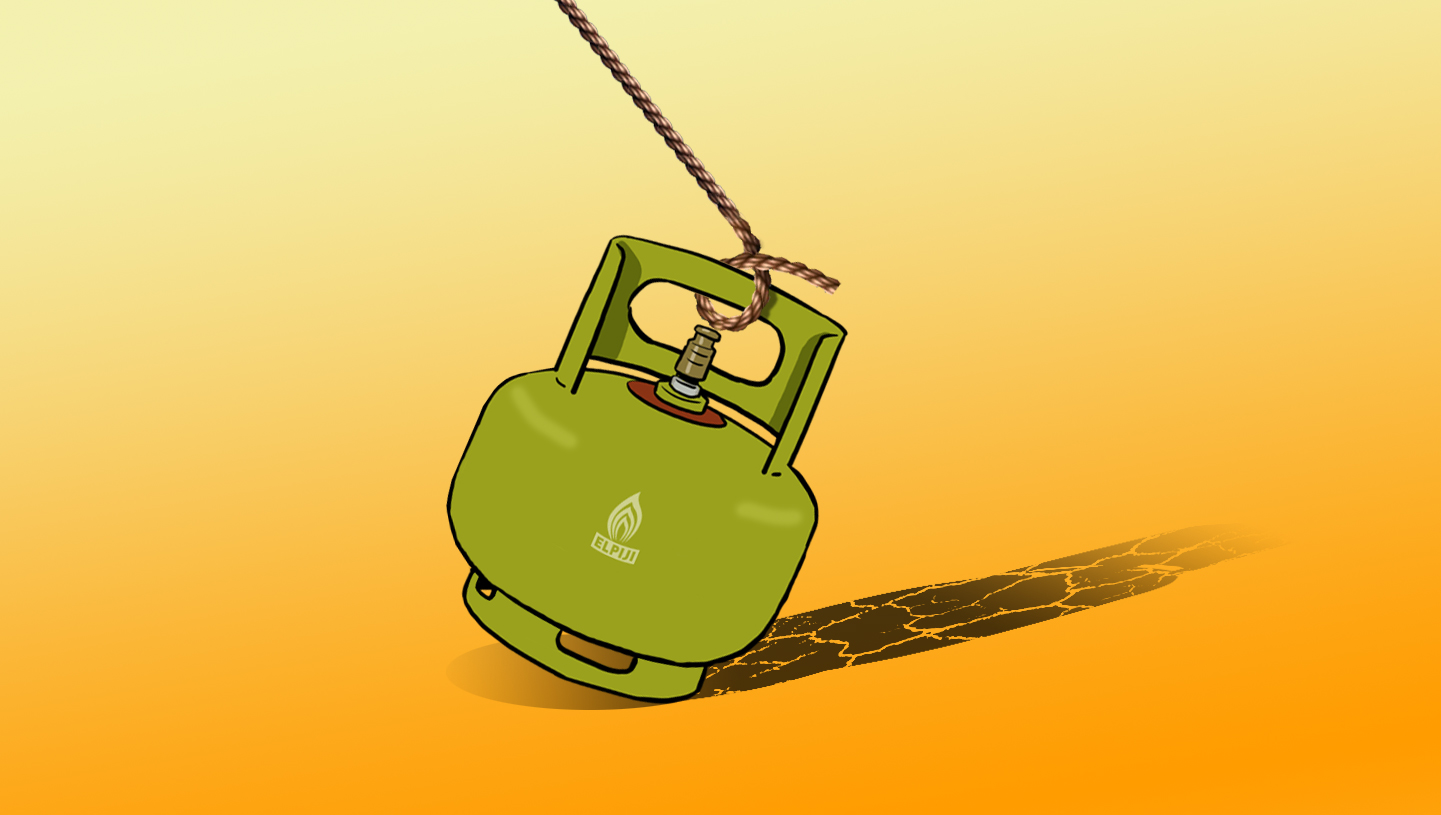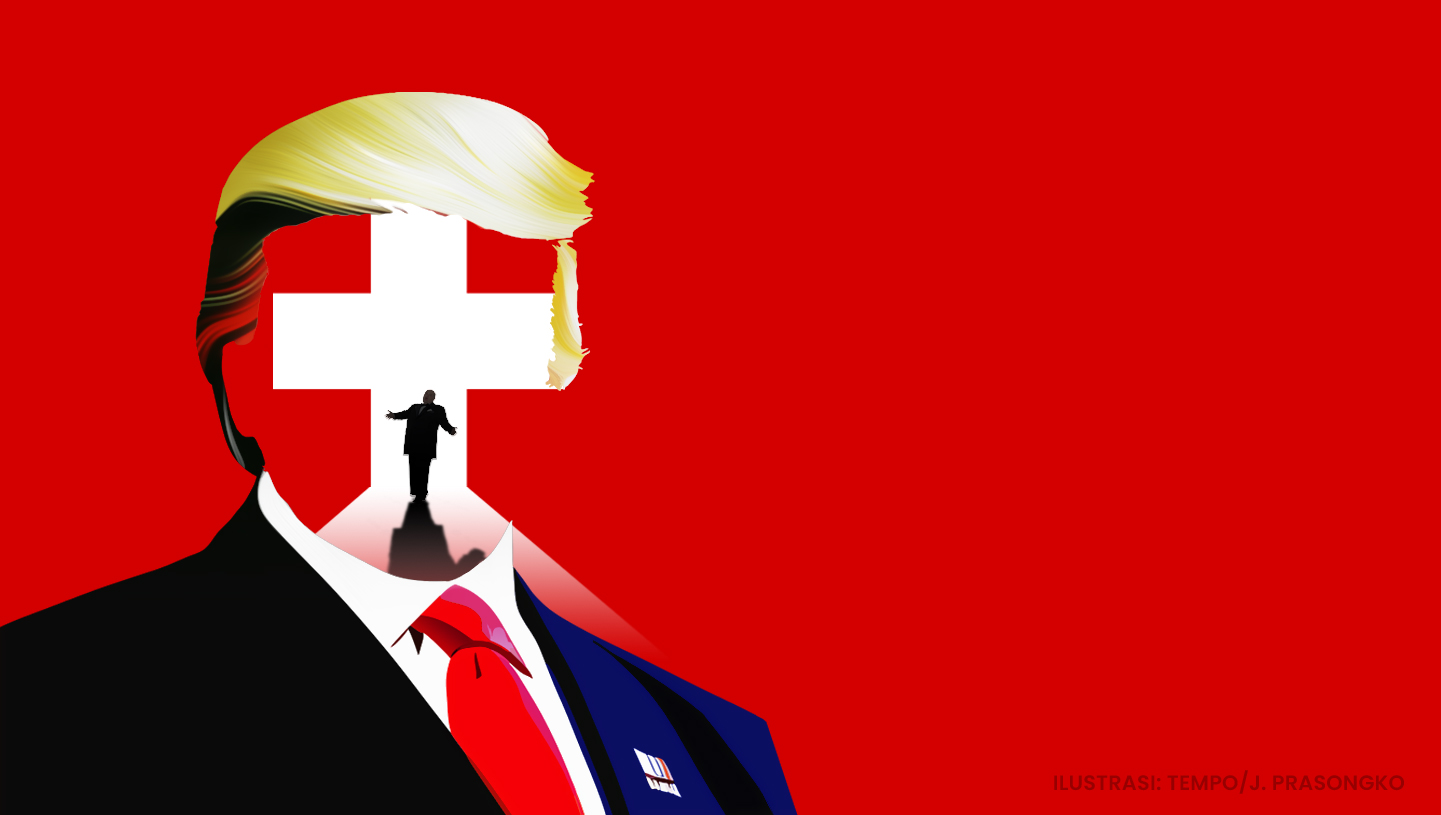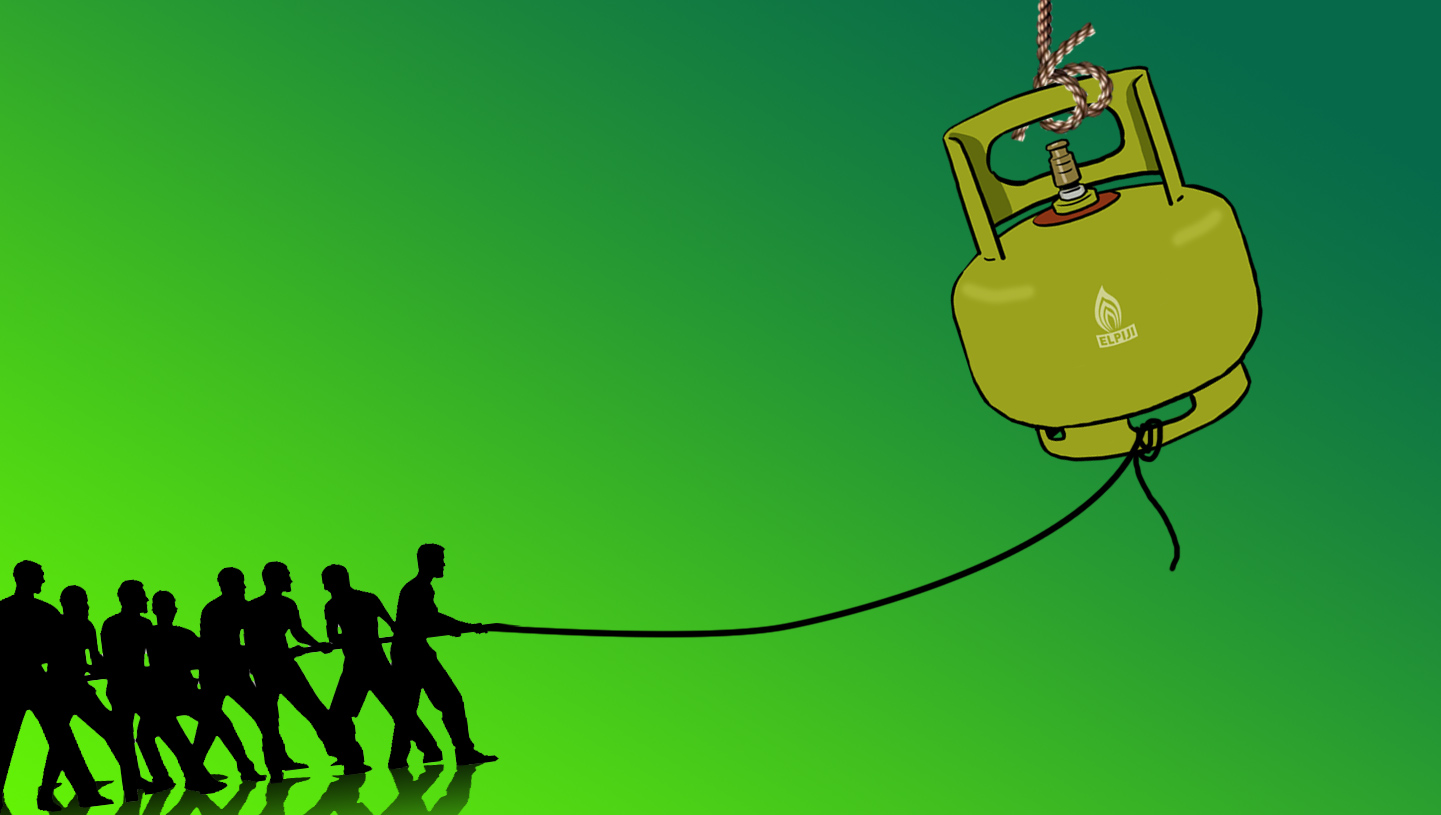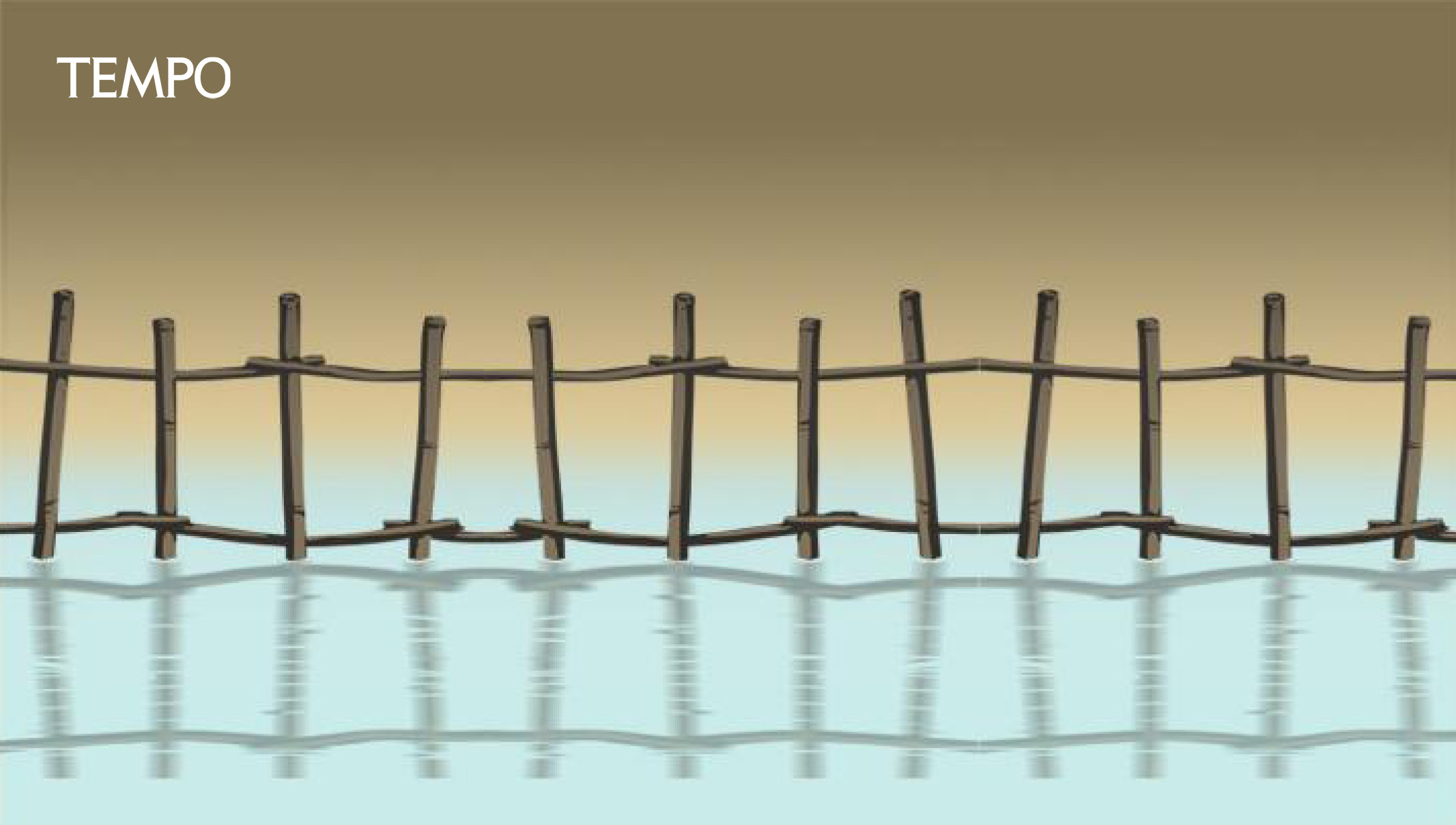Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nova Riyanti Yusuf
Secretary General Asian Federation of Psychiatric Associations
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyoroti banyaknya kasus kekerasan terhadap anak selama masa pandemi Covid-19. Merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), terdapat 3.000 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2020, termasuk 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan 1.848 kekerasan seksual.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bersamaan dengan itu, DKI Jakarta membuat kehebohan dengan menerapkan aturan jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini mengatur bahwa, bila jumlah calon peserta didik yang mendaftar dalam suatu zona melebihi daya tampung sekolah, akan dilakukan seleksi berdasarkan usia dari yang tertua ke yang termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.
Kebijakan DKI ini memicu demonstrasi para orang tua murid ke Balai Kota. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ikut melaporkan hal itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaporan tersebut, Komisi mengatakan bahwa terdapat kasus anak yang sudah melakukan percobaan bunuh diri akibat tidak lulus masuk ke sekolah menengah atas negeri. Bisa dibayangkan, jika informasi yang mengatakan bahwa tidak sampai 20 persen pelajar yang diterima di SMA negeri benar, mayoritas siswa tidak jelas nasibnya. Dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak menentu, bisa dibayangkan beban tambahan orang tua murid untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Jadi, sangat bisa dipahami bahwa Komisi menuntut kebijakan DKI dibatalkan.
Tanpa kisruh pun, pelajar Indonesia sedang menanggung beban psikologis yang sangat besar akibat pandemi. Mereka tidak bisa berangkat ke sekolah dan beraktivitas layaknya orang muda yang aktif di luar rumah menyalurkan energi dan kreativitas bersama teman-teman sebaya.
Masalah kejiwaan remaja tidak harus berwujud diagnosis gangguan jiwa, tapi bisa juga berupa masalah perilaku, emosi, dan hiperaktivitas. Sering luput dari perhatian bahwa anak dan remaja menunjukkan masalahnya melalui perubahan-peruban yang tampak pada nilai yang buruk, kehilangan minat belajar, sering membolos, enggan ke sekolah, tidak naik kelas, menghindari kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain.
Saya pernah melakukan penelitian untuk disertasi program doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia pada 2018. Dengan 910 pelajar SMA/sederajat di DKI Jakarta sebagai responden, ditemukan bahwa hanya 28,4 persen pelajar yang tidak memiliki gejala depresi, sedangkan hampir 70 persen mengalami depresi ringan sampai dengan sangat berat. Sebanyak 39,2 persen mempunyai stresor psikososial tinggi dengan poin tertinggi adalah perasaan bahwa prestasi mereka lebih rendah dari yang mereka harapkan. Artinya, kerentanan jiwa ini telah ada pada mayoritas pelajar di DKI.
Saya mengembangkan sebuah instrumen untuk deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri pada remaja dengan menggunakan empat dimensi, yaitu ketidakberdayaan, kesepian, perasaan menjadi beban, dan perasaan menjadi bagian dari sesuatu. Dengan menggunakan instrumen tersebut, ditemukan 13,8 persen responden mempunyai faktor risiko ide bunuh diri yang tinggi. Pelajar yang terdeteksi berisiko bunuh diri tinggi memiliki risiko 5,39 kali lebih besar untuk mempunyai ide bunuh diri. Keempat dimensi itu berisiko mengalami penguatan dalam kondisi pandemi.
Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, kelompok anak usia 12-18 tahun mempunyai kutub identitas versus kekacauan identitas. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Biasanya mereka akan melaluinya bersama teman-teman yang mempunyai kesamaan komitmen dalam sebuah kelompok. Hubungan mereka dalam kelompok sangatlah erat, sehingga mereka memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota kelompok. Erikson percaya bahwa individu tanpa identitas yang jelas akhirnya akan menjadi tertekan dan kurang percaya diri ketika mereka tidak memiliki tujuan.
Berdasarkan hal-hal di atas, stresor pelajar Indonesia tidak mengalami penurunan, melainkan justru meningkat dan menguatkan dimensi-dimensi faktor risiko ide bunuh diri. Tambahan-tambahan stresor itu di antaranya (1) perasaan tidak ada harapan karena kondisi pandemi yang tak menentu, (2) berkurangnya kesempatan masuk SMA negeri yang mereka cita-citakan, (3) merasa menjadi beban orang tua karena berbulan-bulan harus bersekolah di rumah dan memperberat beban ekonomi orang tua karena tidak berhasil masuk SMA negeri akibat sistem penerimaan murid baru yang tidak mengindahkan aspek kesehatan jiwa pelajar, (4) berlanjutnya isolasi diri sehingga tak bisa bertumbuh kembang bersama secara alamiah dengan teman-teman sebaya yang berakibat pada kesepian dan tidak dapat menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna bagi dirinya, dan (5) dampak psikologis akibat kekerasan.
Kelanjutannya akan seperti apa, tentunya dikembalikan kepada pemerintah DKI. Remaja DKI berisiko bunuh diri akibat beban jiwa yang mereka pikul. Apakah kita tega membiarkan ini terjadi padahal sudah cukup kesedihan kita akibat pandemi?
Minimal ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah DKI. Respons jangka pendek bisa berupa evaluasi sistem penerimaan murid baru yang berkeadilan. Untuk respons jangka panjang, seluruh pemangku kepentingan harus menggunakan pendekatan kesejahteraan mental siswa dalam menetapkan suatu kebijakan. *