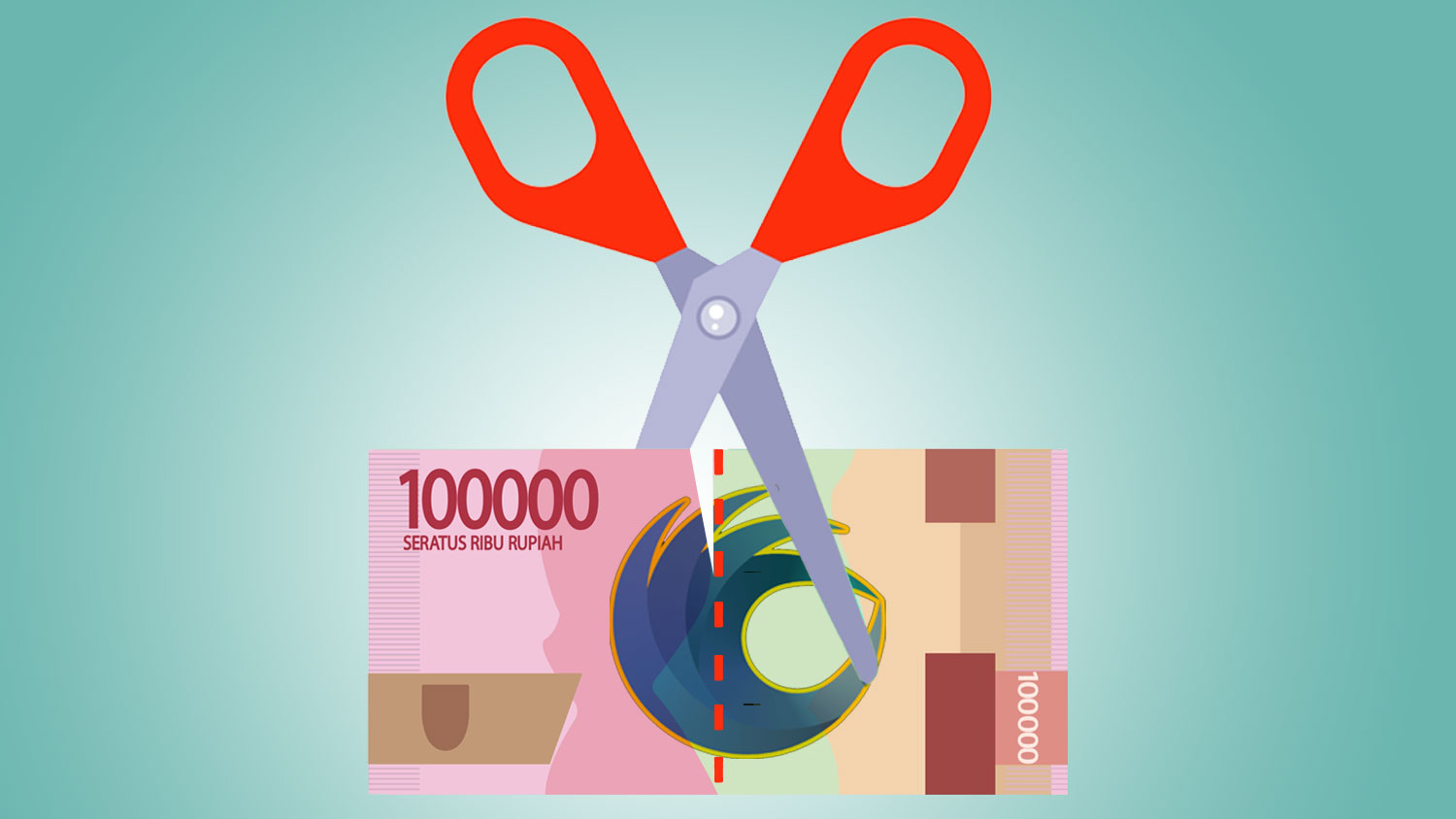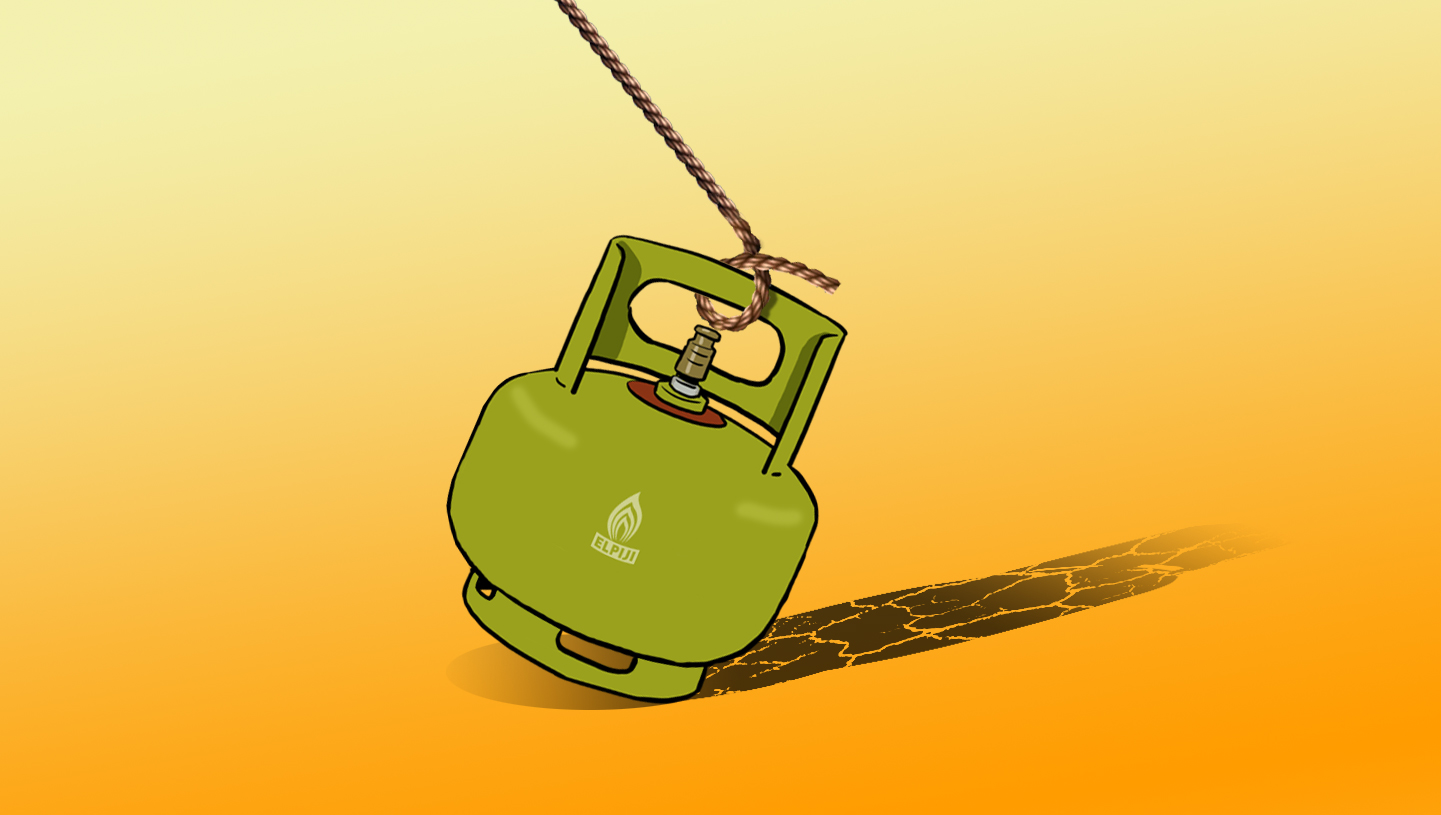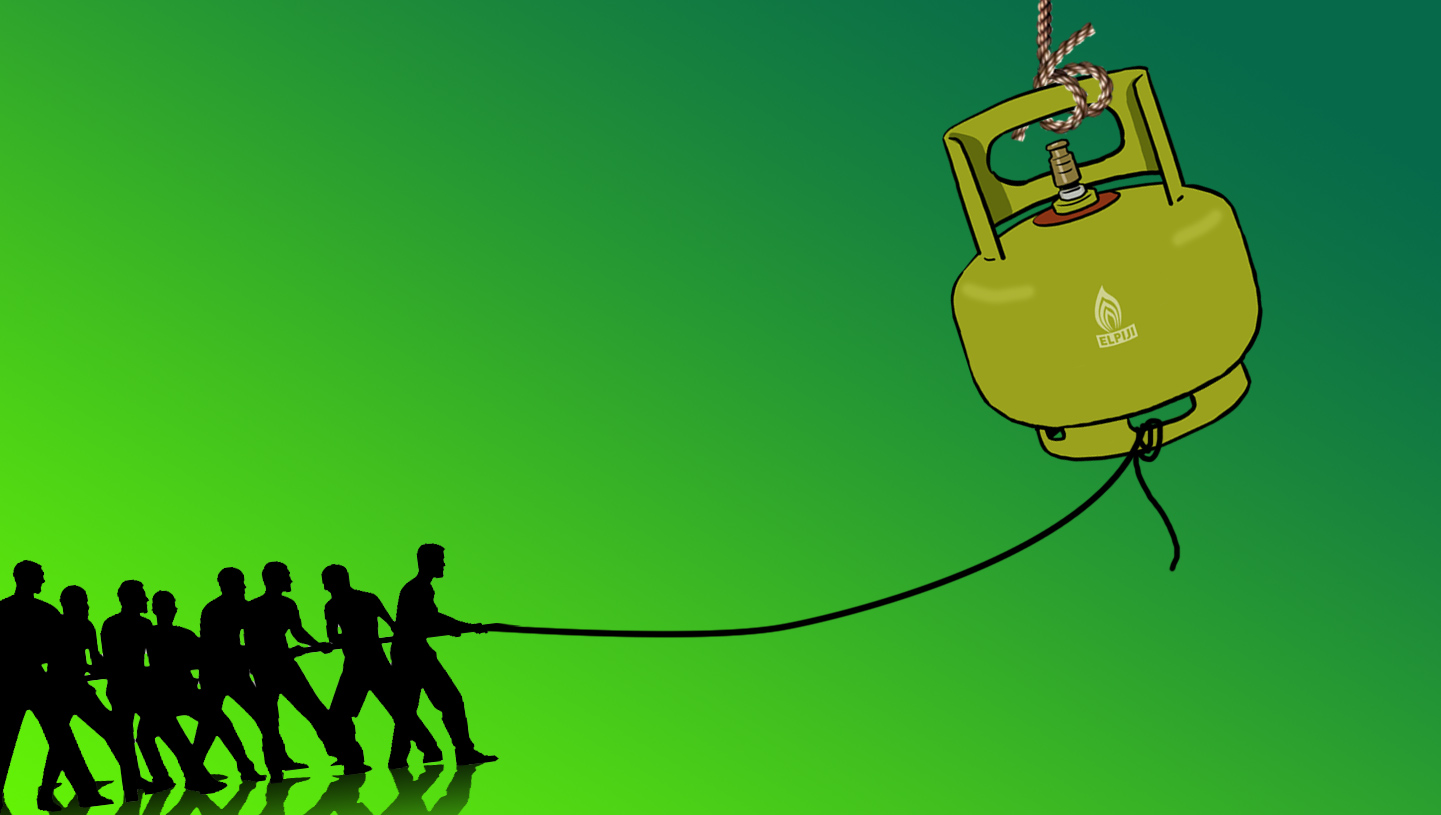KIAI Misbach mencoba memaklumi mengapa banyak orang geregetan melihat sikap agama-agama yang adem-ayem terhadap persoalan hak asasi manusia. Tak sedikit kalangan agama menilainya sebagai konsep kemanusiaan yang sekuler belaka. Dan kenyataannya, seperti demokrasi, konsep hak asasi lahir bukan dari mimbar khotbah di gereja, masjid, sinagog, atau wihara. Benih-benih itu lahir dari diskusi di pabrik dan yel-yel di jalan yang penuh hujatan terhadap otoritas agama. Agama memang cenderung menekankan pada kewajiban, sebaliknya hak asasi manusia menekankan pada hak. Persoalan hak asasi muncul karena adanya kewajiban yang tidak ditunaikan. Bisa dijamin, sekiranya setiap orang telah menunaikan kewajibannya, pastilah gerakan hak asasi tidak relevan lagi. Kesadaran hak asasi adalah kesadaran untuk menagih, sedangkan kesadaran akan kewajiban adalah kesadaran untuk membayar. Membayar lebih esensial daripada menagih. Bahwa sadar kewajiban lebih tinggi daripada sadar hak, kiranya kita sepakat. Masalahnya, bagaimana membuat orang mau membayar kewajibannya. Jika yang harus membayar kewajiban adalah si lemah, sedangkan pemilik hak yang harus dibayar dengan kewajiban tadi adalah si kuat, hal itu pastilah mudah. Misalnya yang berkewajiban adalah rakyat sedangkan yang berhak adalah negara (penguasa), maka mulai dengan cara mengirim surat sampai dengan cara mengirim tentara, pasti negara bisa menagihnya. Tapi bagaimana jika pemikul kewajiban adalah negara (penguasa) sedang pemilik haknya adalah rakyat jelata? Sampai habis seluruh daya dan air matanya pun belum tentu bisa menagihnya. Maka dulu, ketika kedaulatan rakyat belum menjadi cerita, ketika penguasa adalah kelas tertinggi dalam hierarki kehidupan manusia, agama adalah otoritas satu-satunya yang bisa mengatasinya. Setinggi-tinggi derajat penguasa, dia adalah manusia, sedangkan agama adalah suara Tuhan di langit yang menciptakan segalanya. Dengan wibawanya agama berani tampil menggertak penguasa untuk menunaikan kewajiban, membayarkan hak-hak rakyat yang selama ini diingkarinya. Itulah sebabnya mengapa sejarah para pembawa agama Tuhan selalu diwarnai ketegangan, bahkan konflik yang keras dengan para penguasa zamannya. Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Firaun, Sidarta dengan raja Kapilawastu, Isa dengan para bangsawan, dan Muhammad dengan para elite Mekah, seperti Abu Jahal dan Abu Sofyan. Jadi jelas, dalam konteks kekuasaan negara agama (pada mulanya) adalah kekuatan langit yang datang untuk mewakili kepentingan rakyat jelata yang selama ini hanya ditagih kewajibannya oleh para penguasa (al-mala al a'la), tapi tidak pernah dibayar hak-haknya. Bahkan, misi agama tidak berhenti hanya membebaskan rakyat jelata dari dominasi para penguasanya. Agama adalah suatu sistem pembebasan total umat manusia. Dengan ajaran syahadat dan salat-nya, misalnya, Islam membebaskan manusia dari penghambaan oleh sesama, siapa pun dia orangnya. Penghambaan (sujud), hanya boleh kepada Tuhan Yang Esa saja. Lain tidak. Dengan puasa, Islam membebaskan manusia bahkan dari penghambaan oleh nafsu (diri)-nya sendiri. Dengan zakat manusia dibebaskan penghambaan oleh harta dan kuasa (negara) yang dihidupi dari sebagian harta itu tadi, pajak. Dan terakhir dengan ajaran haji, manusia hendak dibebaskannya dari belenggu budaya dan peradaban ciptaannya sendiri. Labbaik allahumma labbaik, hanya kepada-Mu aku datang demikian ikrar mereka tanpa atribut apa pun disandangnya. Tapi, apa mau dikata. Agama sebagai sinar ketuhanan untuk pembebasan manusia, kemudian berubah menjadi bagian dari kekuatan yang diam, atau bahkan aktif membungkamkan. Energi pembebasnya satu demi satu dilucuti dan dicampakkan. Momen- momen pembebasan manusia yang sangat mendasar dan menyeluruh itu akhirnya hanya tinggal ritus-ritus yang sangat detail tapi dangkal. Syahadat direduksi menjadi hanya sebuah ikrar verbal dalam upacara budaya untuk menandai masuknya seseorang dalam komunitas ''kita''. Salat didefinisikan hanya sebagai ''ucapan dan gerakan-gerakan aerobik yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam''. Puasa adalah menahan makan-minum-seks mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Zakat adalah melepaskan harta dalam jumlah tertentu. Dan haji adalah wisata massal ke tanah suci, di Arab Saudi. Bahkan ahli-ahli agama yang merasa memikul tanggungjawab menjaga kemurnian tata cara ritus-ritus mengancam umatnya yang tak menjalankannya persis sama seperti yang (diduga) dilakukan Nabinya. Pelaksanaan ritus yang tidak persis sama dengan tuntutan bukan saja dihukum sia-sia melainkan, katanya, adalah pelecehan terhadap agama (bidah) yang bisa diancam dengan neraka. Maka, seperti para penguasa negara yang berdiri tegak mendominasi rakyatnya, kini para penguasa agama berdiri tegak penuh wibawa di atas umatnya. Keduanya senantiasa menuntut kesetiaan penuh terhadap dirinya. Dan di dalam sejarah, kedua penguasa itu adakalanya bersaing, bergabung di bawah atap yang sama, atau bertetangga dengan pembagian kapling kewenangan antara mereka. Tapi apa pun bentuk hubungan antara keduanya, rakyat atau umat tetap saja ada pada posisi yang harus selalu mendengar, sedangkan mereka di atas yang memiliki klaim untuk selalu didengar. Maka, bisa dimengerti, bagi penguasa dunia (negara) maupun agama, hak asasi dianggap sebagai suara sumbang yang terang- terangan atau sembunyi menghujat otoritas mereka. Tapi kita boleh berharap keadaan bakal berubah. Umat manusia semakin sadar bahwa kebebasannya tidak bisa dilokalisasi hanya pada soal hubungan hierarkis dengan sesama. Kebebasan manusia memiliki dimensi dan muatan yang jauh lebih luas. Agama sejati, sebuah kesadaran yang ada di balik tata cara ritus, telah membukakan cakrawalanya. Bilakah kita beranjak ke sana? Kiai Misbach tidak mengatakannya. Ia hanya melirik ke ulu hati setiap kita, juga ulu hatinya sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini