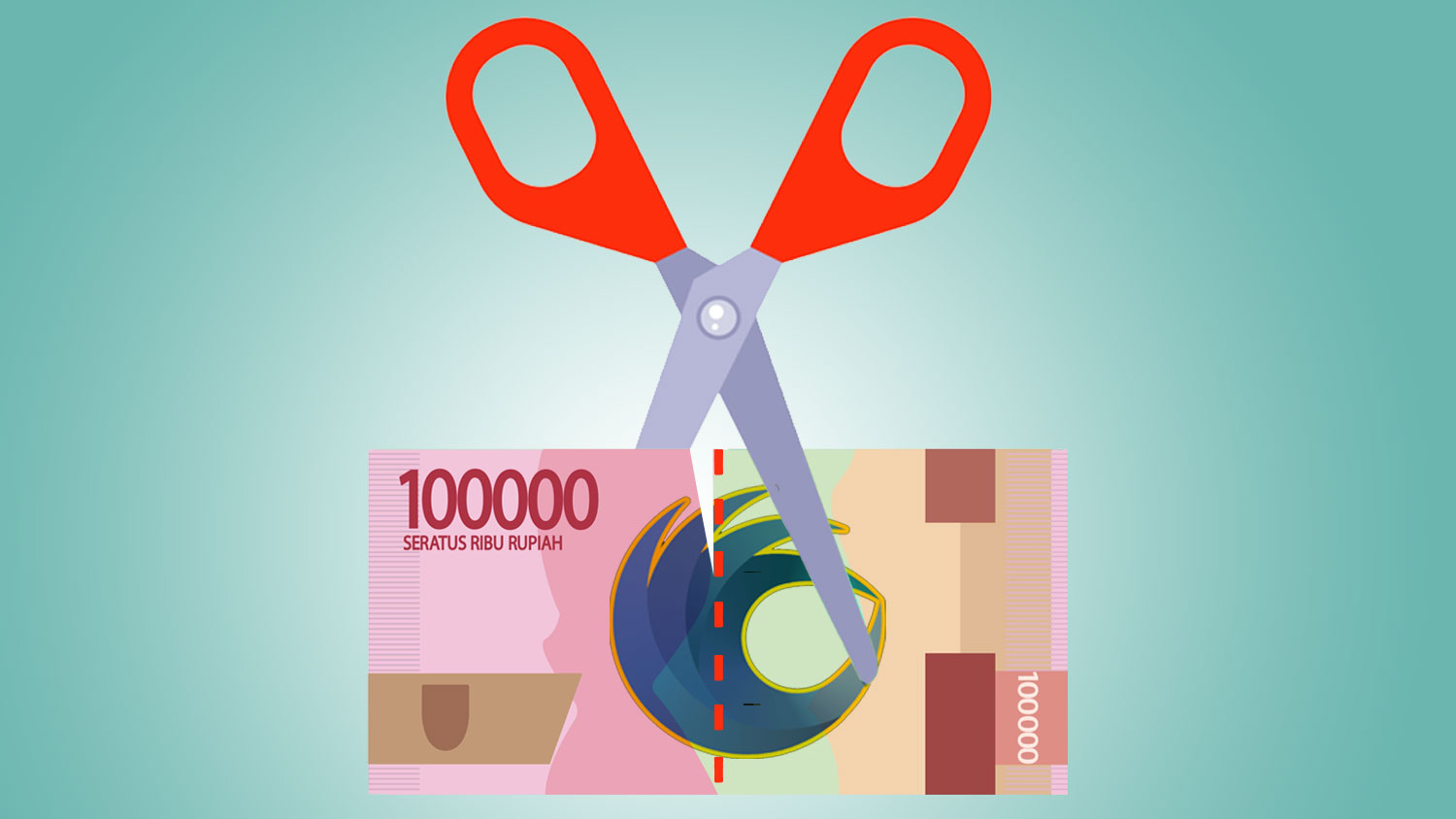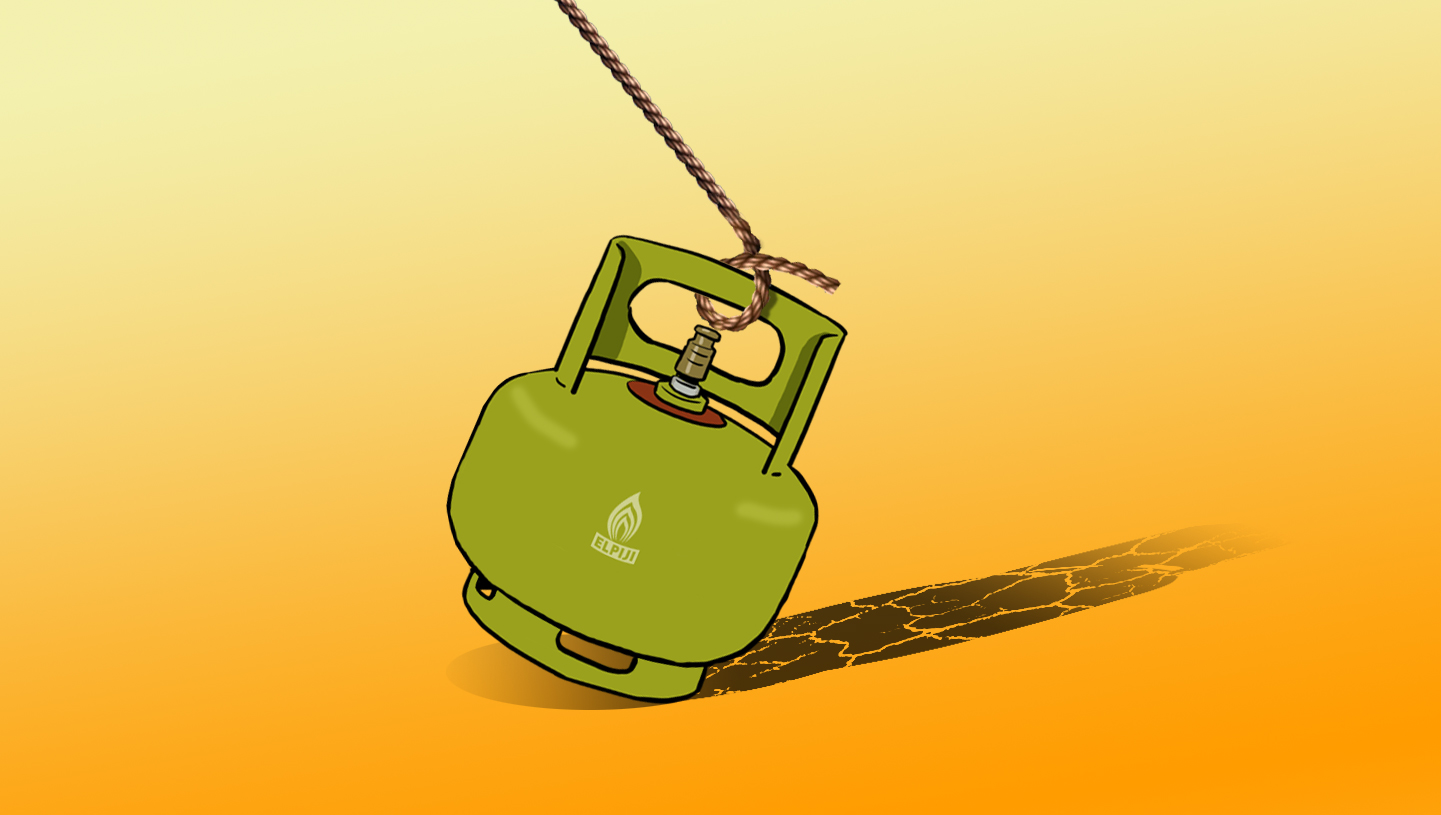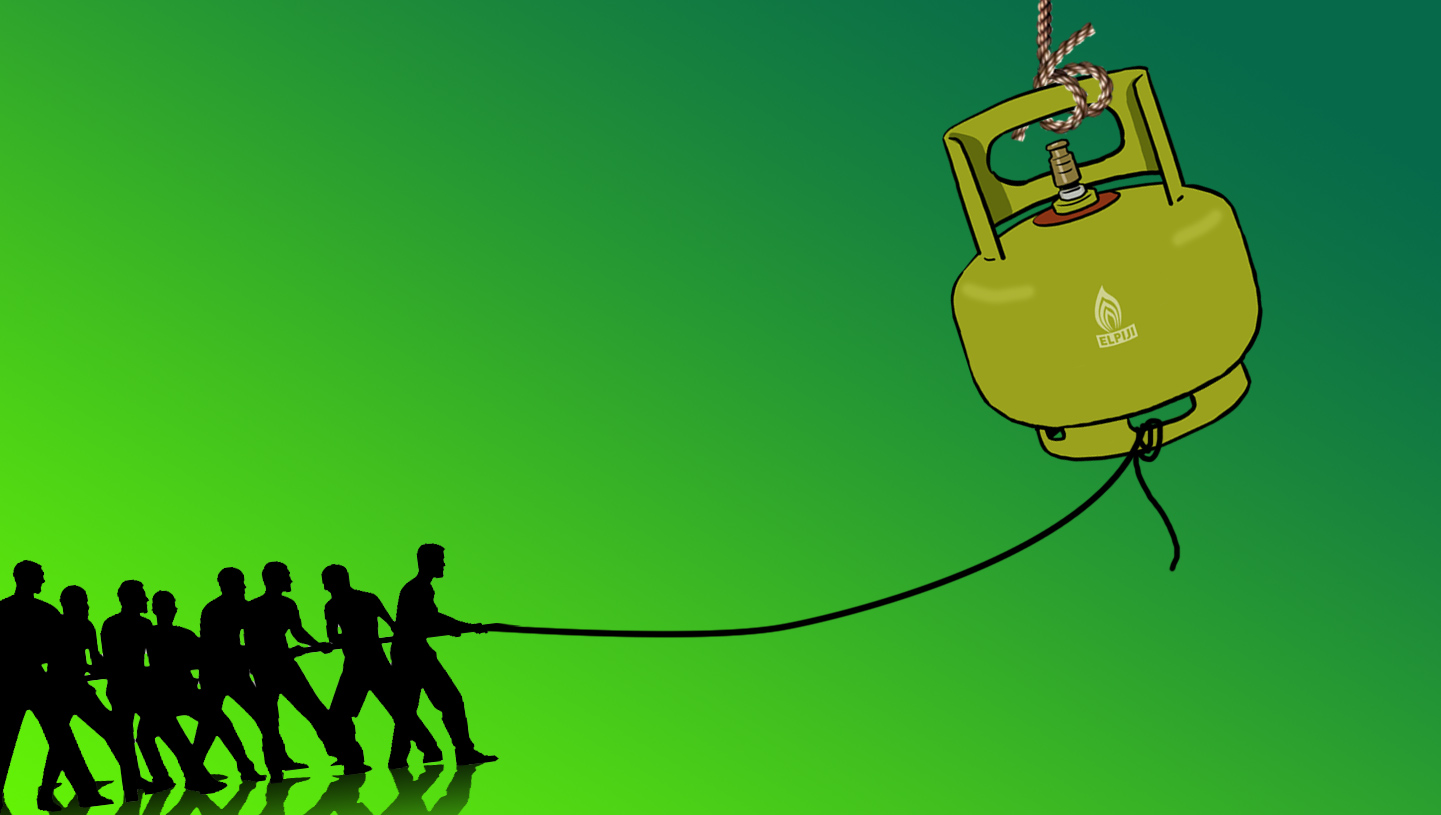Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Pencalonan presiden dan wakil presiden hanya diwarnai kepentingan meraih kekuasaan.
Faktor utama pemicu situasi ini adalah kuatnya oligarki politik.
Oligarki politik membuat politik jauh dari kepentingan rakyat dan hanya berfokus pada kepentingan elite.
Satrio Wahono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sosiolog dan Magister Filsafat UI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menjelang batas akhir pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum 2024, politik kita kian tidak menarik. Berita media dominan diisi manuver-manuver aktor politik untuk sekadar meraih kekuasaan, termasuk ribut-ribut soal batas usia calon presiden. Hal yang sering menghiasi wacana publik justru soal siapa seharusnya berpasangan dengan siapa untuk memastikan kemenangan elektoral. Adapun proses pasang-memasangkan ini juga jauh dari afinitas ideologi atau visi dan lebih pada hitung-hitungan ihwal sosok mana menguasai daerah apa untuk memenangi pemilihan presiden. Hal ini tecermin, misalnya, dari pengumuman mengejutkan ketika Anies Baswedan, bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), berduet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Kondisi politik kita saat ini tampaknya justru antipolitik. Istilah Hannah Arendt yang dikutip Yosef Keladu Koten dalam Etika Keduniawian (2018) ini mengacu pada kondisi yang berlawanan dengan esensi politik sebagai komunikasi dan pertemuan di antara manusia yang membincangkan urusan-urusan bersama lewat cara berpikir secara rasional supaya dunia ini bisa lebih kerasan untuk kita diami bersama orang lain. Situasi politik yang hanya bising dengan intrik untuk memenangi pemilihan presiden saat ini adalah situasi ketika urusan bersama tidak lagi dibincangkan, melainkan hanya dijadikan komoditas politik.
Salah satu faktor utama pemicu situasi antipolitik adalah oligarki politik. Oligarki politik inilah yang membuat politik justru jauh dari kepentingan rakyat dan hanya berfokus pada kepentingan elite. Oligarki politik pada dasarnya adalah proses dan tatanan politik dalam sejumlah kecil individu kaya yang berkuasa karena sumber daya material. Jadi, oligarki adalah politik mempertahankan kekayaan dan memiliki berbagai bentuk seiring dengan berubahnya ancaman terhadap kaum oligark. Para oligark dapat berdiri sendiri dan berkuasa atau melekat dalam rezim otoriter serta demokrasi (Jeffrey Winters, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, Prisma 1, 2014).
Singkat kata, oligarki adalah juga plutokrasi, ketika kekuasaan politik berada dalam genggaman segelintir orang saja, dalam hal ini orang-orang yang memiliki kekayaan dan berkepentingan untuk mengamankan atau bahkan menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Kondisi ini merupakan akibat dari situasi transplacement yang menghinggapi Indonesia sejak awal reformasi. Menurut Samuel Huntington dalam The Third Wave (1991), transplacement adalah situasi ketika proses perubahan dalam suatu masyarakat tidak menghasilkan perombakan total sebagaimana dicita-citakan, melainkan justru ditunggangi oleh pemain lama yang bersalin rupa menjadi aktor penggerak perubahan. Euforia berlebih akibat tumbangnya penguasa otoriter sebagai musuh bersama pada 1998 membuat elemen masyarakat pro-perubahan larut dalam sentimen emosional sehingga abai dalam menentukan agenda-agenda politik konkret ke depan. Terjadilah kevakuman ruang publik yang kemudian secara cepat direbut oleh kaum oligark yang kini justru menikmati buah reformasi berupa penggelembungan aset mereka.
Bentuk penguasaan kaum oligark dalam sistem politik Indonesia bisa dilihat langsung pada salah satu pilar terpenting demokrasi kita, yakni partai politik (parpol) sebagai agen agregasi dan artikulasi kepentingan para perwakilan mereka di DPR yang menentukan sebagian besar jabatan publik ataupun produk hukum. Penelitian Amalinda Savirani dan Arya Budi dalam majalah Prisma Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar partai di Indonesia berciri paternalistik serta klientelistik yang berimplikasi terhadap lemahnya relasi partai dengan konstituen. Paternalisme dan klientelisme dalam partai merupakan situasi ketika partai serta anggotanya tergantung hanya pada satu sosok berpengaruh (paternal) sehingga sulit bagi kader partai untuk bertindak mandiri dan justru terjebak menjadi sekadar pelaksana partai yang tidak bisa bersikap kritis (klien).
Watak paternalistik dan klientelistik partai politik kita sebenarnya tidak terhindarkan karena begitu mahalnya syarat untuk mendirikan parpol. Partai harus memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Belum lagi kewajiban memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan kabupaten/kota serta keharusan memiliki kantor kepengurusan tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Begitu beratnya syarat ini jelas membuat hanya orang-orang dengan kekayaan besar yang mampu mendirikan partai politik sehingga membuka pintu lebar-lebar untuk berjayanya oligarki politik dan sistem kepartaian yang paternalistik serta klientelistik.
Karena itu, salah satu solusi mendasar untuk mengikis oligarki dalam sistem politik kita adalah menyederhanakan secara radikal syarat pendirian partai politik sehingga biayanya lebih murah. Hal ini juga akan menghapuskan persepsi Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi berbiaya mahal (high-cost democracy).
PENGUMUMAN
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebut lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo