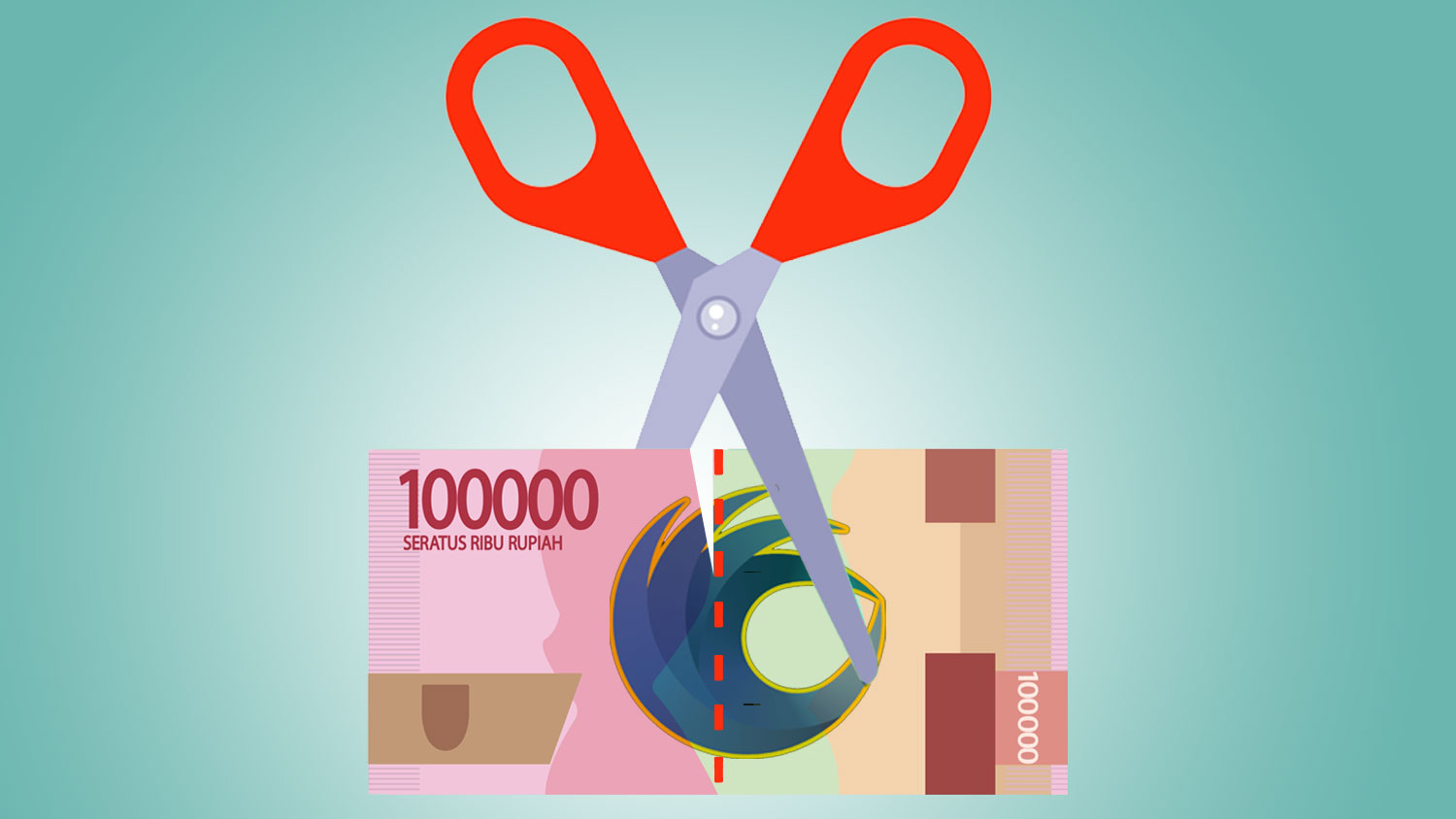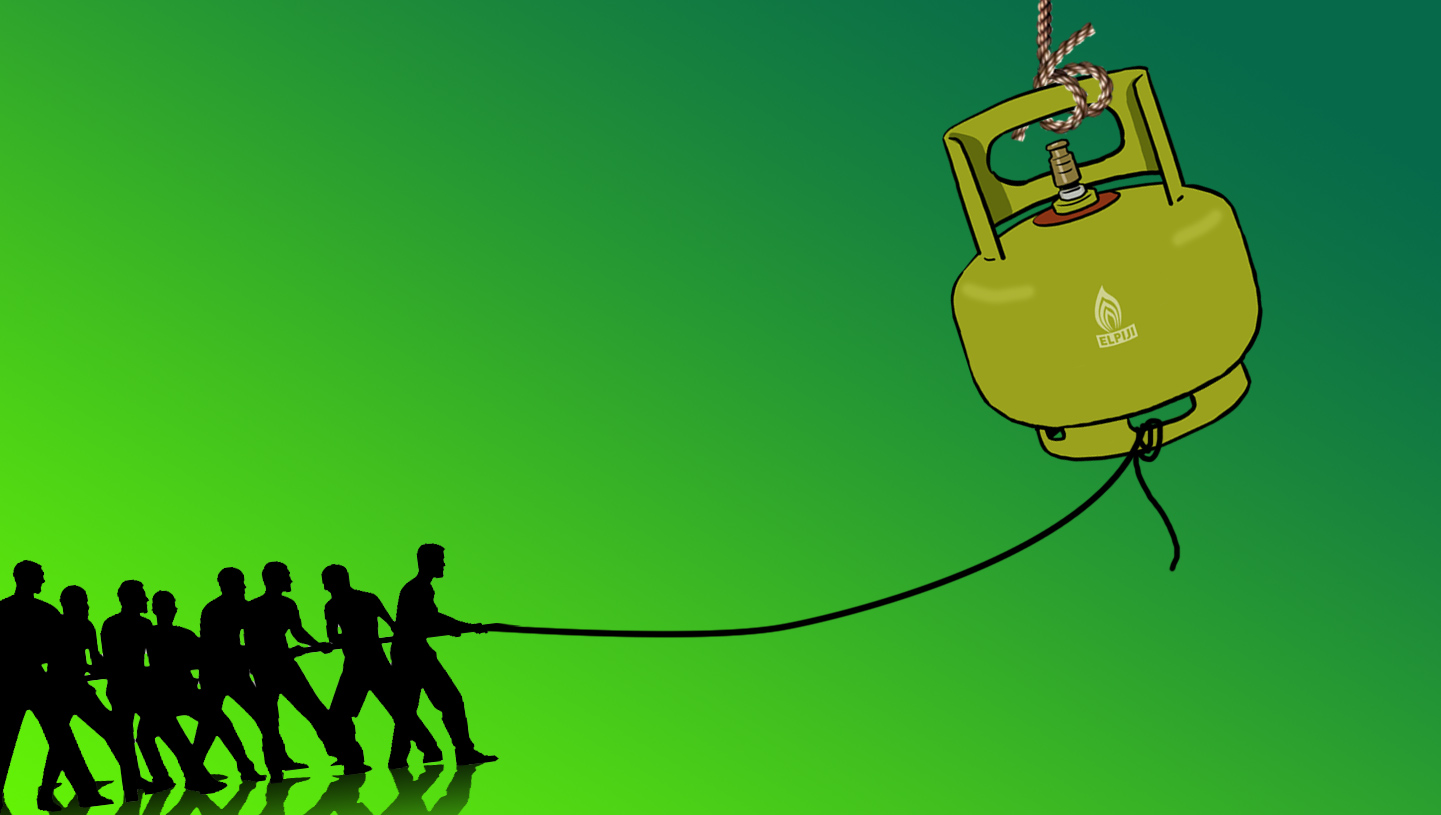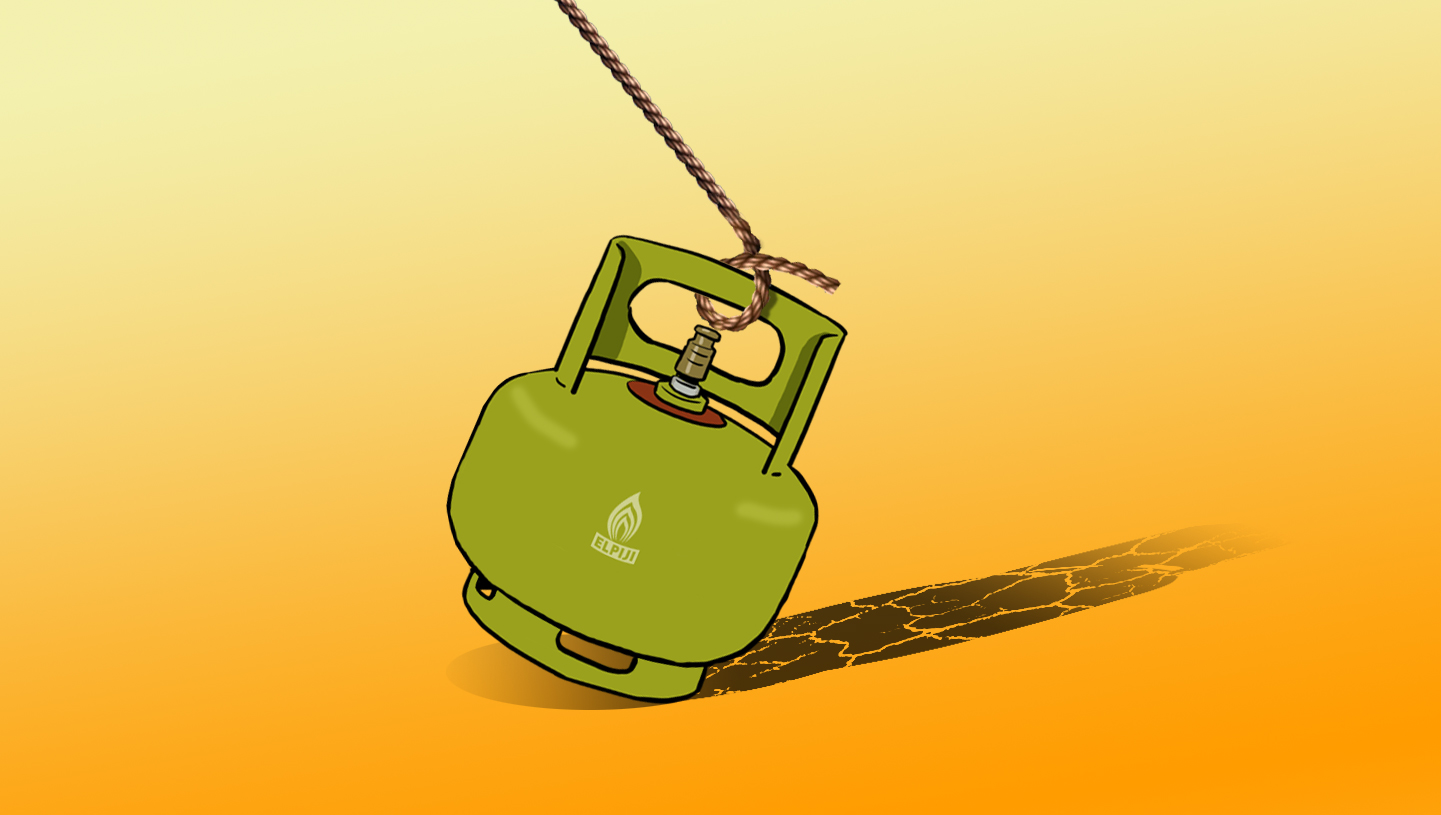Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komitmen untuk memberikan jaminan hak perlindungan dan pemulihan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di masa lalu menjadi salah satu janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang sudah digaungkan sejak pertama kali beliau menduduki kursi kekuasaan tahun 2014.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nyatanya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti Peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Trisakti 1998, Semanggi I dan Semanggi II serta beberapa kasus pelanggaran HAM berat lainnya sampai saat ini masih menjadi utang pemerintah kepada masyarakat Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil dan tuntas. Korban dari pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut belum mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.
Menurut sejumlah pakar hukum dan HAM, ada beberapa alasan mengapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia sulit diselesaikan dan para korban sulit mendapatkan keadilan.
Kuatnya impunitas hukum
Menurut Moh. Fadhil, Dosen Hukum Pidana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia pernah memiliki satu regulasi penting, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR), yang bertujuan untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memenuhi hak-hak korban, sehingga penderitaan korban dapat terobati.
Namun, pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut UU KKR tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memberikan kepastian hukum. Walaupun kini RUU KKR tengah digodok kembali di parlemen atas usulan Komnas HAM, putusan MK kala itu dinilai telah meruntuhkan harapan untuk pengungkapan kebenaran.
Dilema pada perangkat hukum tersebut, menurut Fadhil, menggambarkan adanya belenggu impunitas hukum, karena rezim reformasi sekarang masih terkontaminasi oleh para pelaku pelanggaran HAM berat di masa orde baru.
Eddy O.S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam bukunya yang berjudul “Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM” menyebutkan bahwa langgengnya impunitas disebabkan kuatnya arus politik yang mempengaruhi aspek penegakan hukum, sedangkan ranah politik sendiri masih dikuasai oleh para pelaku.
Pengaruh tersebut mengontaminasi berbagai macam proses penegakan hukum secara in abstracto yakni proses formulasi kebijakan penegakan hukum. Inilah salah satu yang menjadi tembok penghalang pengungkapan kebenaran dan keadilan terhadap korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang turut memperkokoh benteng impunitas terhadap para pelaku.
Untuk menerobos impunitas tersebut, menurut Fadhil, peran masyarakat sipil perlu diperkuat untuk mendorong dan mengawasi pembahasan RUU KKR yang tengah berjalan di parlemen.
Kemudian, demi memutus rantai impunitas dari dalam kelembagaan, pemerintah bersama otoritas terkait, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu menerapkan mekanisme seleksi rekam jejak yang ketat terhadap pejabat-pejabat yang akan mengisi jabatan di badan dan lembaga negara.
Lemahnya implementasi hukum
Menurut Ogiandhafiz Juanda, Dosen Hukum Internasional dan Keadilan Global dari Universitas Nasional, implementas aturan yang ada saat ini tidak cukup memadai untuk dapat memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara komprehensif.
Padahal, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur ketentuan pemberian kompensasi atau restitusi, serta jaminan perlindungan lainnya.
Ketentuan lebih lengkap tentang pemberian kompensasi dan restitusi tersebut juga diatur dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Sayangnya, pemenuhan kompensasi dan restitusi tersebut belum diberlakukan secara efektif dan efisien. Hal ini karena, menurut UU Pengadilan HAM, kompensasi dan restitusi akan diberikan melalui putusan pengadilan.
Ogiandhafiz menyebutkan Peristiwa 1965 sebagai contoh, yang korban atau keluarganya sudah menanti lebih dari 50 tahun namun tidak juga mendapatkan kepastian hukum. Para korban masih harus menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan haknya.
Tidak berjalannya proses peradilan inilah yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM berat.
Menurut Ogiandhafiz, pemerintah harus segera menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan upaya dan langkah yang lebih konkrit, mulai dari proses penuntutan hingga pemulihan hak-hak korban.
Never to forgive, never to forget
Menurut Nunik Nurhayati, Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penyelesaian pelanggaran HAM melalui skema KKR pada dasarnya mengedepankan jalur non-yudisial atau tanpa persidangan.
Nunik menjabarkan ada tiga model penyelesaian pelanggaran HAM.
Pertama, “to forget and to forgive” (melupakan dan memaafkan), yaitu meniadakan proses pengadilan dan melupakan masa lalu. Melupakan dan memaafkan tanpa proses hukum mungkin pilihan yang diinginkan para pelaku. Model ini tidak hanya kontradiktif dengan harapan korban, tapi juga akan melanggengkan impunitas dan tidak memberikan efek jera.
Kedua, “never to forget, never to forgive”, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan diproses secara hukum. Para pelaku akan diadili dan apabila terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman.
Ketiga, “never to forget, but to forgive” (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan). Artinya, kasus diungkap dulu, sampaikan kebenaran, kemudian pelaku diampuni. Model ini bersandar pada proses kompromi.
Menurut Nunik, pemerintah seharusnya mengambil model kedua untuk mengadili kasus pelanggaran HAM masa lalu karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negara hukum. Peradilan HAM merupakan sesuatu yang multlak harus ada sebagai betuk keadilan yang nyata.
Sementara itu, jalur non-yudisial sebenarnya lebih mengarah ke model pertama. Hal inilah yang ditolak oleh banyak pihak terutama para korban dan keluarganya.
Walaupun pemerintah menghendaki jalur non-yudisial, yakni melalui KKR, pemerintah harus tetap terikat pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara universal, yakni kewajiban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM dengan pemenuhan terhadap hak untuk tahu (the right to know), sebagai landasan dalam pemberian pemulihan korban (the right to reparation), dan penegakan pertanggungjawaban melalui penuntutan hukum, guna mencegah berulangnya pelanggaran HAM.![]()
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.