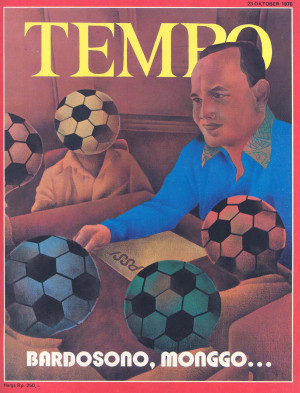TOKOH "Mbah Suro" dari desa Nginggil yang gersang kini mulai
terlupakan. Tapi sebelum peristiwa Sawito, agaknya peristiwa di
tepi Bengawan Sala 9 tahun yang lalu itu merupakan contoh lain,
yang berbeda, tentang bagaimana sejumlah orang ingin berlindung
dan bertahan dalam suatu masa yang mencemaskan.
Waktu itu adaah waktu kejatuhan Bung Karno, waktu peralihan
yang penuh gejolak ke "masa baru". Mulyono, bekas lurah Nginggil
yang berumur kira-kira 46 tahun, sudah dikenal dengan sebutan
"Mbah Suro". Ia bertindak sebagai dukun. Banyak orang
mempercayai kesaktiannya, termasuk orang yang berkedudukan di
kota-kota. Tak heran bila banyak orang datang. Dan desa Nginggil
pun berubah wajah -- bak daerah yang banyak dikunjungi turis.
Lampu-lampu neon dipasang di sana. "Sehingga kalau malam hari
kita ke Nginggil", begitu tulis wartawan Ramelan dalam bukunya
Mbah Suro Nginggil (1967), "kita akan menikmati sinar-sinar
lampu neon di tengah-tengah lingkungan hutan belantara yang
gelap seram itu". Bahkan direncanakan jalanan akan diaspal oleh
Mbah Suro. Aspal sudah tersedia. Tapi kemudian pemerintah Orde
Baru melancarkan operasi polisionil ke desa itu
Genjer-genjer
Adapun penguasa setempat waktu itu mensinyalir bahwa "Pertapaan
Gunung Kendeng" di desa Nginggil itu tempat persembunyian
orang-orang PKI yang lari. Menurut Let. Kol. (waktu itu) Leo
Ngali Maret 1967, satu team penyelidik yang terdiri dari anggota
ABRI dan sipil pernah dikirim ke sana. Mereka diterima para
murid Mbah Suro dan dipersilakan menunggu: katanya, setelah jam
12.00 mereka bakal diterima Mbah Suro (ternyata tidak jadi).
Selama menunggu, mereka dihidangi tarian dan nyanyian, antara
lain lagu Genjer-Genjer, yang menurut pemerintah Orde Baru
adalah lagu PKI. Juga, kata Leo Ngali, para pengikut Mbah Suro
meneriakkan yel "Hidup PKI!"
Mbah Suro diketahui memang sering menyatakan kesetiaannya kepada
Bung Karno. Pertemuan dengan para pengikutnya konon selalu
disertai seruan "Hidup Bung Karno!" (yang lalu disambut dengan:
"Hidup Mbah Suro!"). Ada juga diberitakan bagaimana orang-orang
di dusun itu mengucapkan pernyataan anti para pelajar dan
mahasiswa di kota-kota besar -- yang waktu itu berdemonstrasi
menentang Bung Karno.
Mbah Suro kemudian tertangkap. Anak buahnya berupa pasukan
"Banteng Ulung" dan "Banteng Sarinah" (para wanita) dilumpuhkan
oleh pasukan RPKAD. Sang pemimpin kemudian ditembak mati, "konon
melarikan diri ketika sedang disuruh apel", tulis Ramelan. Satu
regu dokter dan pejabat, kemudian kepada umum membuktikan bahwa
Mbah Suro betul mati. Ketika beberapa saat setelah menyerah si
Mbah yang masih muda itu ditanya apa betul ia kebal, ia
menjawab: "Ah, tidak, Pak. Itu kan hanya orang-orang saja yang
mengatakan".
Mbah Suro memang bukan manusia luar biasa. Paling tidak,
begitulah pengalaman pembantu TEMPO Abdul Bari Ts. yang di tahun
1960 sudah ketemu dengan dia di desa Nginggil. Waktu itu Mbah
Suro atau Mulyono masih berstatus lurah, merangkap dukun. Abdul
Bari waktu itu masih siswa Sekolah Kehutanan Menengah Atas,
Bogor. Dia tengah berpraktek ke hutan -- sampai ke kecamatan
Menden, yang mewilayahi desa Nginggil. Acara: menjejaki para
pencuri kayu jati. Maka untuk mendapatkan data penduduk, mata
pencaharian dan keamanan hutan, ia dan beberapa kawannya bertemu
dengan lurah Mulyono
Waktu itu, menurut mandor yang mengantar praktek, pak lurah atau
Mbah Suro sedang nglakoni. Tak makan nasi sudah selama 2 tahun.
Cuma rokok dan kopi. Juga tiga hari tiga malam pati geni, tak
makan tak minum. Rambutnya sudah mencapai bahu. Badannya tegap
berisi, berpakaian baju hitam seten dan celana sepe dril.
Isterinya berkain, baju brokrat hitam. Di lehernya tergantung
leontin dari emas. Bentuknya: palu arit. "Waktu itu saya sudah
yakin", kata Abdul Bari, "bahwa Mulyono ini BTI (Barisan Tani
Indonesia) atau PKI".
Pertemuan kedua lebih menarik. Dengan 8 rekan, mereka tiba di
Nginggil. Perjalanan agak sukar karena baru banjir. Rumah Mbah
Suro yang berbentuk joglo, berikut pendoponya, dihias janur
kelapa dan pisang berbuah. yang diikat di tiang-tiang. Juga
bendera merah putih. Persiapan kenduri. Mbah Suro sedang
merayakan Mauludan -- sehubungan dengan akan lewatnya yang mbau
rekso ("si penjaga") Bengawan Sala. Acara penyambutan diramaikan
dengan wayang kulit semalam suntuk. Dan Mbah Suro memamerkan
kebolehannya meramal: ia menyatakan bahwa kedatangan rombongan
itu sudah diketahuinya sebelumnya.
Dan dalam rombongan itu memang ada yang mau diobati dan diramal.
Yang mau diobati adalah anak Kepala Bagian Kesatuan Pemangku
Hutan (KBKPH), karena sekolahnya kurang "maju". Yang minta
diramal adalah dua siswa Sekolah Kehutanan, teman Abdul Bari.
"Ingin tahu saja', bisik mereka.
Prosedur ramalan begini: Mbah Suro masuk kamar. Sang isteri dan
seorang cantrik berada di luar, duduk menghadapi orang yang mau
diramal. Agak lama kemudian, sang isteri lemas, lunglai dan
tersandar di kursinya. Dengan bantuan sang cantrik-yang
sekaligus merangkap sebagai pemberi penjelasan -- sang isteri
ditegakkan duduknya. Tapi tetap tak sadar. Lalu ia mulai bicara.
Tapi suaranya besar, suara lelaki. Inilah Mbah Suro, katanya.
Lalu ucapan-ucapan lain yang setengah menggumam dalam bahasa
Jawa --yang tak difahami oleh para siswa dari Bogor itu, sebab
mereka orang Sunda.
Tapi kemudian ramalan diterangkan. Rekan yang satu diramal akan
dipaksa menikah dengan seorang gadis di kampungnya di
Tasikmalaya. Keluarga gadis itu akan memaksanya bahkan dengan
senjata tajam. Tapi jangan cemas: ada jimat penangkis, kata si
Mbah. Betulkah ramalan Mbah Suro terbukti kemudian? Tidak. Hanya
sepulang dari Nginggil pemuda yang diramal itu demam.
Pemuda yang satu diramal baik: enam bulan lagi akan segera ke
luar dari sekolah, dan akan pegang jabatan penting di kehutanan
sekitar situ. Ramalan ini aneh. Waktu itu mereka di kelas dua
Sekolah Kehutanan Tingkat Atas. Untuk lulus dari sekolah, paling
sedikit dibutuhkan 18 bulan lagi -- bukan cuma 6 bulan seperti
ramalan Mbah Suro. Dan ramalan itu memang ternyata tak terbukti.
Siswa yang bersangkutan bahkan tak naik kelas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini