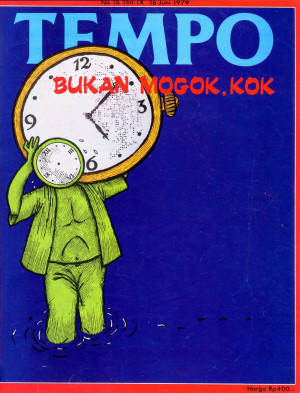LASMIANTI tidak pernah berangan-angan jadi buruh. Cita-citanya
ingin menjadi guru agama. Karenanya begitu tamat Pendidikan Guru
Agama Atas (PGAA), gadis ini ingin segera lekas mengajar untuk
turut meringankan beban orang tuanya yang menanggung 12 anak.
Tapi beslit yang dinantinya tak kunjung tiba.
Lasmianti memutuskan untuk mengembara ke Surabaya mengikuti
seorang familinya. Kebetulan sang famili ini tinggal dekat
pabrik kaos "Asli". Hingga biasa, Lasmianti kemudian bisa
bekerja di sini. "Tapi sebelumnya saya sempat jadi kernet bemo
jurusan Wonokromo-Jembatan Merah," ujarnya. "Sayalah
satu-satunya kernet wanita saat itu," tambah gadis yang kini
berusia 27 tahun itu.
Di pabrik ini, 7 tahun sudah Lasmianti menjual tenaganya.
Belakangan, rekan-rekannya memilihnya sebagai ketua Serikat
Buruh di pabrik yang mempunyai sekitar 600 buruh itu. Sebagai
ketua SB, Lasmianti merasa sedih karena upah buruh di pabrik itu
jauh dari persyaratan yang ditentukan. "Seorang buruh yang sudah
bekerja lebih dari 5 tahun gajinya hanya Rp 85/hari," ujarnya.
Ada juga tambahannya, yakni tunjangan makan dan transpor sebesar
Rp 100/hari. Hingga yang diterima buruh hanya Rp 185/hari.
"Itupun setelah dinaikkan 30% belum lama ini," ujar Lasmianti.
Mengapa buruh tidak menuntut upah yang lebih tinggi? Keadaan
perusahaan ini memang "payah" hingga SB tidak sampai hati
mendesak perusahaan. "Bisa-bisa kalau perusahaan tidak kuat
menggaji, justru kami semua yang diberhentikan," kata Lasmianti.
Direktur perusahaan Asli, Supriyangga (40 tahun) ketika ditemui
TEMPO mengakui perusahaannya tidak bisa menggaji buruhnya lebih
besar karena kelesuan usahanya.
Keadaan semacam itu diakui FBSI Surabaya. "Upah yang paling
minim memang di sektor tekstil," kata Siswanto. Sekretaris FBSI
Surabaya. Berbeda dengan Jakarta, situasi Jawa Timur tampaknya
tidak memungkinkan terjadinya aksi buruh yang "ramai". "Buruh di
sini relatip penakut," ujar Abdurrahman, Wakil Ketua FBSI Jawa
Timur. Tiga SB di daerah industri Rungkut membenarkan pendapat
ini. "Tidak berani mas, nanti dikira macam-macam," ujar seorang
di antaranya.
Gaji rendah ternyata tidak terdapat di perusahaan pribumi saja.
Pada 28 April lalu, sekitar 600 dari 1051 buruh pabrik
pemintalan benang tenun PT Ellegant di Jatiluhur, Purwakarta,
menuntut kenaikan upah lewat Serikat Buruh Tekstil dan Industri
FBSI basis PT Ellegant. Upah harian yang dibayar PT Ellegant
yang merupakan PMA India itu pada buruhnya -- yang sebagian
besar wanita -- adalah rata-rata Rp 200 untuk 7 jam kerja,
terendah Rp 150 dan paling tinggi Rp 900. Di luar itu,
perusahaan menyediakan fasilitas angkutan serta satu kali makan,
ditambah tambahan susu atau kacang hijau untuk yang bertugas
malam hari.
Buruh menganggap upah ini kelewat rendah dan melanggar keputusan
Menteri Nakertrans yang menggariskan upah terendah Rp 414 untuk
7 jam kerja. Pihak perusahaan menolak tuntutan itu dengan dalih:
"Kalau angkutan dan makan itu dihitung dalam komponen upah
ketentuan Rp 414 itu sudah terpenuhi," kata seorang pejabat PT
Ellegant.
Permusyawaratan yang kemudian dilakukan hanya menghasilkan
persetujuan PT Ellegant untuk menaikkan upah menjadi Rp 175
untuk 8 jam kerja. Kanwil Naker Purwakarta tampaknya tak bisa
berbuat banyak melerai sengketa ini. "Kemampuan kami hanya
sampai tingkat menganjurkan, bukan wewenang memaksakan
keinginan," kata Untarwan, Kepala Kantor Perwatan Purwakarta.
Pekan lalu perselisihan ini diajukan ke P-4 D Jawa Barat untuk
diselesaikan.
Sengketa juga terjadi PT Indorama, yang juga pabrik
pemintalan benang tenun PMA India. Di sini pernah terendah
Rp 250/hari untuk 7 jam kerja. Masih di wilayah Jatiluhur, di 2
pabrik pemintalan benang tenun PT Indaci dan PT Texfibre yang
PMA Jepang, hampir tak pernah terjadi sengketa. Di PT Indaci
misalnya, upah minimal Rp 470/hari untuk 7 jam kerja. Makan
sekali sehari serta fasilitas pengangkutan juga tidak dimasukkan
dalam komponen upah. "Jadi apa yang harus diributkan lagi?" kata
beberapa buruh PT ini.
Hampir semua buruh yang ditanya tidak bersedia disebut namanya.
Tidak ada lain yang bisa disimpulkan kecuali ini menunjukkan
bahwa buruh tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Walau upah
rendah, sering mereka terpaksa tunduk menerimanya. Bayangan
pengangguran tampaknya begitu menghantui mereka. "Di desa, kami
mau kerja apa?", kata seorang buruh dari SuL,ang pada pembantu
TEMPO Hilman Eidy.
Tidak semua buruh takut memperjuangkan haknya. Ook Mujoko (30
tahun), karyawan Hotel Horison mencoba melakukan itu dan
akibatnya ia kehilangan pekerjaannya. Ook yang bekerja di hotel
ini sejak 1975 merasakan banyak kejanggalan yang merugikan
karyawan. Misalnya tidak adanya peraturan perusahaan,
kesejahteraan karyawan yang diabaikan serta pembagian uang
servis yang jelas. Pada pertengahan 1977 timbul gagasannya untuk
berusaha memperbaiki nasib rekan-rekannya melalui pembentukan
SB. "Saya menyadari risikonya. Saya tahu banyak karyawan di
beberapa tempat yang dipecat karena membentuk SB."
SB Pariwisata Basis Hotel Horison, melalui banyak rintangan
akhirnya terbentuk juga. Tapi Ook yang dianggap penggeraknya
memperoleh getahnya. Maret 1978, Ook yang bertugas di bagian
Cost Control dipindah ke Cafetaria Copacabana "untuk
mengembangkan kariernya." Ook menolak dan akibatnya ia diskors.
SBPB Hotel Horison yang beranggotakan 465 dari 556 karyawan
menuntut agar Ook dipekerjakan kembali dan sengketa ini kemudian
dibawa ke P-4 Daerah. Keputusan PD Ook harus dipekerjakan
kembali. PT Metropolitan Realty International Unit Hotel Horison
naik banding ke P-4 Pusat. Dalam sidangnya 15 Januari lalu, P-4
P memutuskan agar Ook dipekerjakan kembali dan menerima upah
penuh selama tidak bekerja. Keputusan ini tidak bisa diterima PT
MRI yang kemudian bahkan menggugat P4 Pusat dan Ook Mujoko di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut pembatalan keputusan
itu. Pengadilan sampai saat ini belum memutuskan sengketa ini,
tapi sementara proses ini berlangsung Ook telah terpilih menjadi
Sekretaris Buruh Pariwisata DKI Jaya. Untuk menghidupi
keluarganya, 10 bulan terakhir ini Ook bekerja sebagai sopir
taksi. Menyesal? Ook menggeleng. "Ini memang sudah niat saya.
Saya malah merasa terhibur. Sekarang Hotel Horison sudah
berhati-hati kalau menindak karyawannya," katanya.
KASUS sengketa perburuhan yang sampai ke meja pengadilan
memang tidak banyak. "Sebetulnya kalau semuanya sudah menghayati
HPP mustinya tidak usah sampai ke pengadilan. Perbuatan itu bisa
dinilai tidak punya iktikad baik," kata Sekjen DPP FBSI Sukarno.
Keresahan akibat kondisi perburuhan bisa juga timbul tidak pada
buruh itu sendiri, tapi pada masyarakat setempat. Beberapa bulan
lalu pada suatu malam pabrik roti "Asia Biskuit" di Tabing,
dekat Padang, yang mempekerjakan 600 buruh dihujani batu. Para
buruh panik dan berlarian dan kerusakan-kerusakan kecil terjadi.
Siapa pelemparnya?
Lewat ruangan surat pembaca di koran daerah di Padang pemuda
setempat mengaku sebagai pelaku. "Itu peringatan dari kami,
sebagai protes mengapa wanita dipekerjakan semalam suntuk,"
tulis mereka. Lebih separuh pekerja pabrik roti ini memang
wanita dan bekerja bersama buruh pria dalam suatu ruangan.
Semalam suntuk lagi. "Mereka berpacaran secara bebas," kata
seorang pemuka masyarakat Tabing pada pembantu TEMPO Muchlis
Sulin.
Usia buruh wanita itu masih sangat muda, sekitar 16-19 tahun.
Meskipun mereka bekerja untuk mencari nafkah hidup. "tapi itu
bunga sedang berkembang, kata seorang pemuda Tabing. Maksudnya,
dalam usia begitu mereka bisa tergoda dan rusak. Untunglah
Tripida Kecamatan Koto Tengah cepat turun tangan. Penertiban
segera dilakukan, juga lewat Kantor Perwatan dan FBSI Padang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini