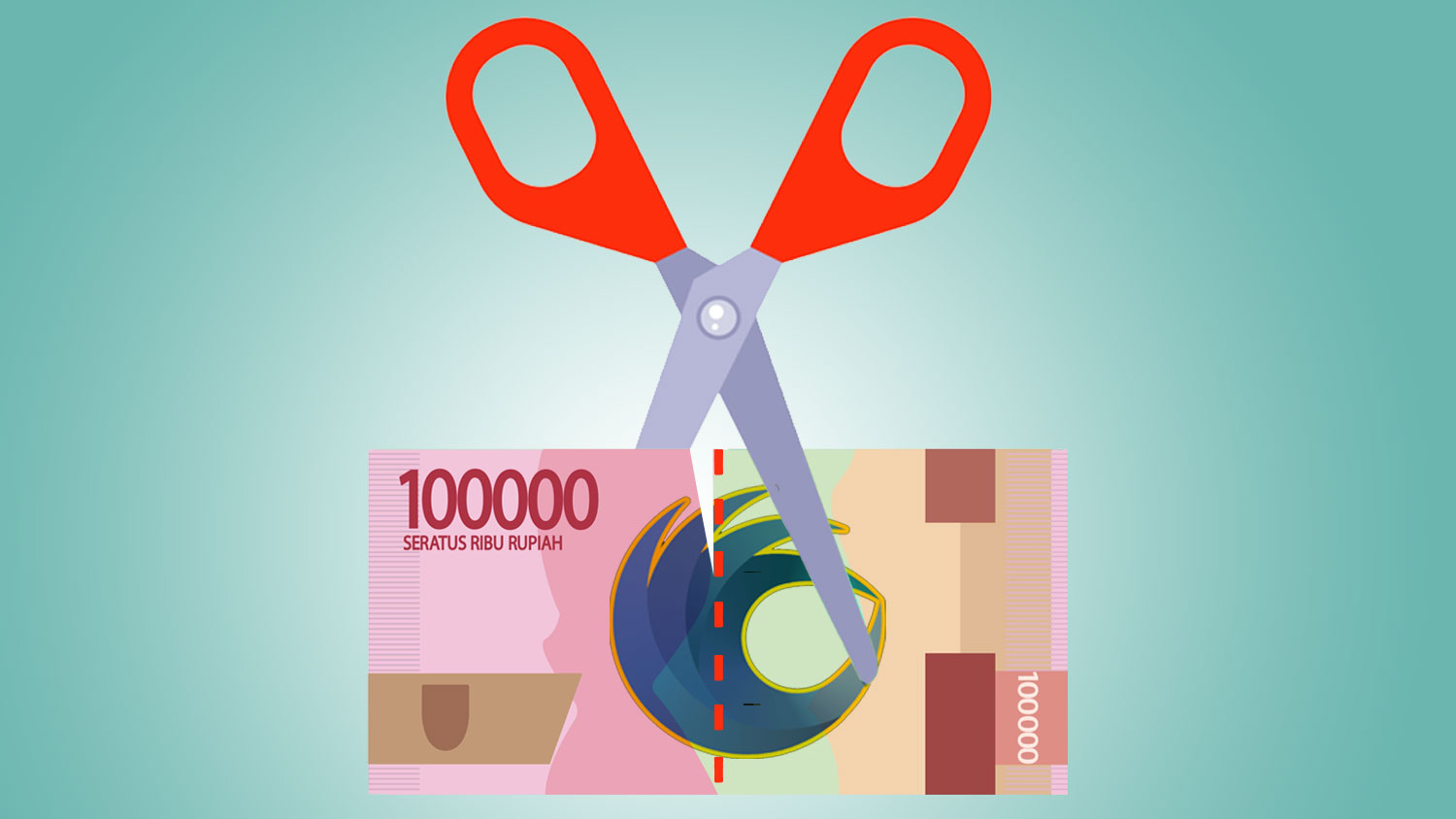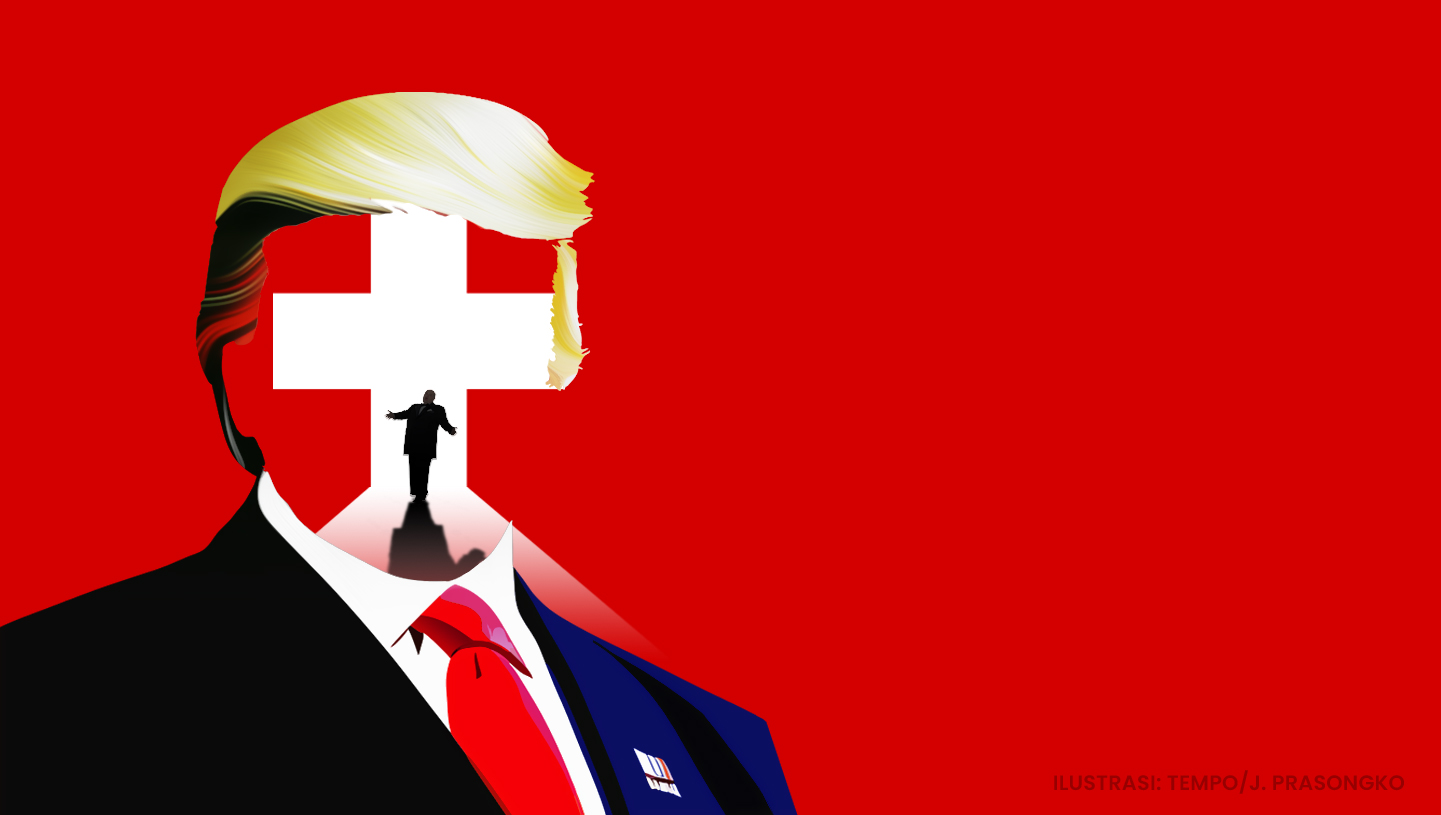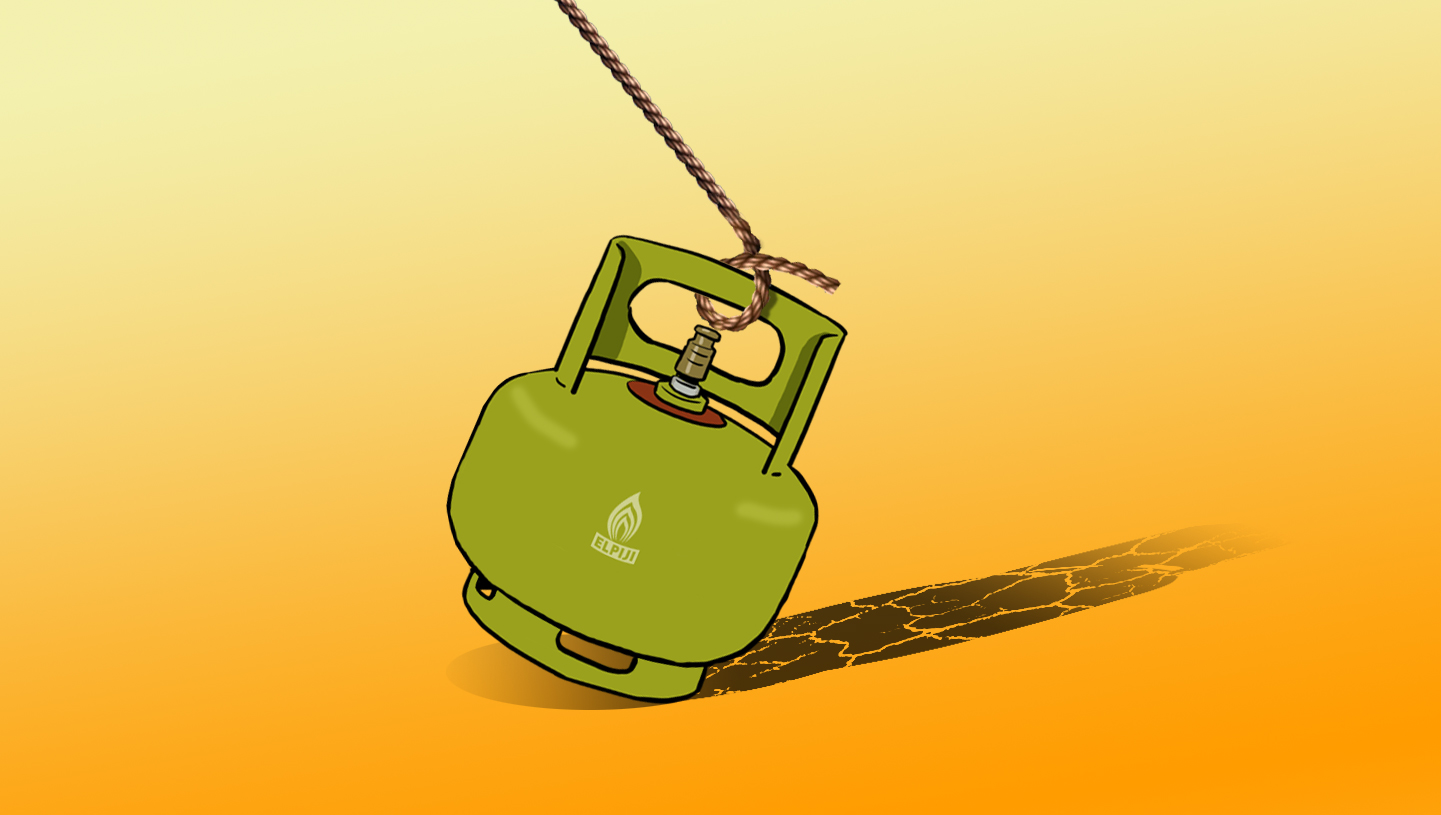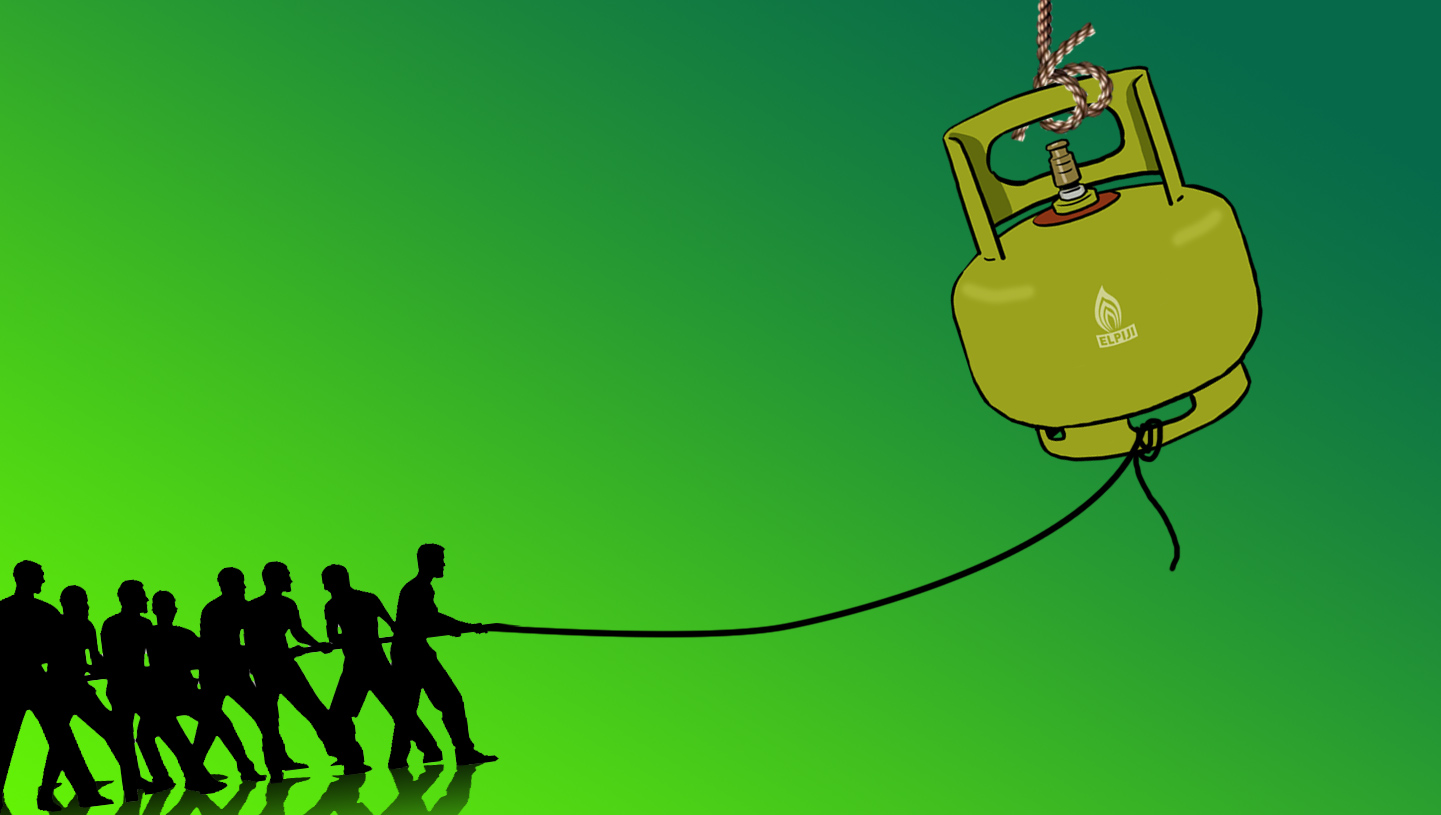Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Satrio Wahono
Magister Filsafat UI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudah sebulan lebih memasuki 2020, dunia kian menghadapi ancaman eksistensial besar bernama krisis lingkungan. Di Indonesia, kita sudah melihat bencana banjir yang menghantam berbagai penjuru negeri pada awal tahun. Di Amerika Serikat, badai salju datang silih berganti menebar kerusakan di sejumlah negara bagian. Paling terbaru, Australia justru mengalami bencana kebakaran hutan paling dahsyat sepanjang sejarah dan menewaskan hampir satu miliar tanaman dan satwa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jelas isu pemanasan global bukan lagi isapan jempol. Pemanasan global mengakibatkan mencairnya es di kutub utara dan selatan hingga menaikkan permukaan laut sekaligus menimbulkan perubahan iklim plus perubahan badai. Suhu bumi yang panas secara ekstrem bisa menimbulkan kekeringan luar biasa yang berujung pada kebakaran hutan parah sebagaimana terjadi di Australia.
Sesungguhnya, inilah buah yang dituai umat manusia karena abai menerapkan prinsip-prinsip etis dalam relasinya dengan lingkungan. Lebih konkretnya, umat manusia sudah lama mencampakkan etika bumi (land ethics) sehingga bumi pun membalas dengan menunjukkan murkanya lewat berbagai fenomena anomali iklim dan bencana-bencana alam.
Digagas oleh Aldo Leopold (1991), etika bumi mengajarkan bahwa etika secara ekologis merupakan pembatasan tindakan manusia demi alasan keberlangsungan hidup. Etika ini bertumpu pada asumsi bahwa individu adalah anggota dari satu komunitas yang terdiri atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling tergantung. Di satu sisi, insting manusia menuntut dia untuk berkompetisi demi meraih posisi dalam komunitas, tapi di sisi lain etikanya mendesak dia untuk juga bekerja sama supaya ada tempat bagi dia untuk berkompetisi. Singkatnya, etika bumi mengajari kita untuk memperluas batasan komunitas, tidak hanya berlaku pada sesama manusia, tapi juga mencakup tanah, air, flora, fauna, dan juga bumi itu sendiri.
Artinya, etika bumi mendedahkan perubahan peran Homo sapiens, dari penakluk bumi menjadi sekadar salah satu anggota bumi bersama komponen-komponen lingkungan lainnya. Homo sapiens atau umat manusia harus menghargai komponen-komponen lingkungan itu sama seperti mereka menghormati dan bertoleransi kepada sesama manusia (Leopold, 1991).
Ajaran etika bumi membuka wawasan etis kita bahwa, jika kita tidak bertoleransi kepada sesama warga negara bumi, misalnya dengan melakukan eksploitasi berlebihan terhadap tanah atau menggusur habitat satwa secara berlebihan, kerukunan antar-warga bumi akan terkoyak seraya melahirkan konflik antar-warga berupa krisis lingkungan dan gelombang bertubi-tubi kerusuhan (baca: bencana) alam.
Sebagai contoh, fenomena menjamurnya ular-ular di sejumlah daerah di Indonesia sejatinya dampak dari tergusurnya habitat ular-ular liar tersebut oleh proyek-proyek permukiman manusia. Kemunculan lebah super yang menewaskan sejumlah orang di beberapa daerah di Jawa juga disebabkan oleh hilangnya habitat lebah tersebut, sehingga mereka merangsek masuk ke area permukiman manusia yang telah menggusur mereka.
Celakanya, terkadang proyek-proyek semacam itu dibuat bukan dalam rangka subsistensi atau memenuhi kebutuhan dasar manusia, melainkan sekadar menjadi aksi spekulatif pemupukan kapital dan laba para pengusaha real estate dengan embel-embel investasi. Inilah yang disebut budaya hidup-lebih dalam kapitalisme global. Budaya ini merupakan satu cara memandang dan melakoni hidup dengan sebuah nilai-dasar saat kita merasa wajib mendapat lebih dari apa yang telah kita miliki (Dahana, 2015).
Budaya hidup-lebih menjadi budaya menimbun dan tidak terpuaskan untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Penganut budaya ini adalah orang-orang serakah yang rakus mengkonsumsi penanda-penanda yang seakan membuat mereka keren. Padahal kepuasan mengkonsumsi penanda itu laksana seseorang yang kehausan dan meminum air laut: dahaga itu tak akan kunjung selesai.
Jadi, sebab mendasar dari krisis lingkungan adalah pencampakan etika bumi. Karena itu, solusinya juga harus mendasar: pengadopsian etika bumi lewat metode ekoliterasi. Menurut Fritjof Capra (2004), ekoliterasi adalah strategi untuk menggerakkan masyarakat luas agar bisa memeluk secepatnya pola pandang baru atas realitas kehidupan bersama mereka di bumi dan melakukan pembaruan-pembaruan yang diperlukan.
Dalam konteks sekarang, strategi itu harus diisi dengan konten berupa etika bumi. Sekolah di berbagai tingkatan akan menjadi sarana efektif untuk menanamkan etika bumi sejak dini sekaligus membekali anak didik dengan cara-cara praktis merawat lingkungan, seperti mengurangi pemakaian kantong plastik, tidak lagi membeli minuman ringan berkemasan plastik, menanam bibit-bibit pohon, dan menggunakan kertas bekas sebagai coret-coretan atau kertas gambar.
Dengan pengadopsian etika bumi secara bertahap, generasi kita sejatinya berupaya untuk mewariskan kondisi lingkungan yang tetap layak ditinggali bagi generasi berikutnya.