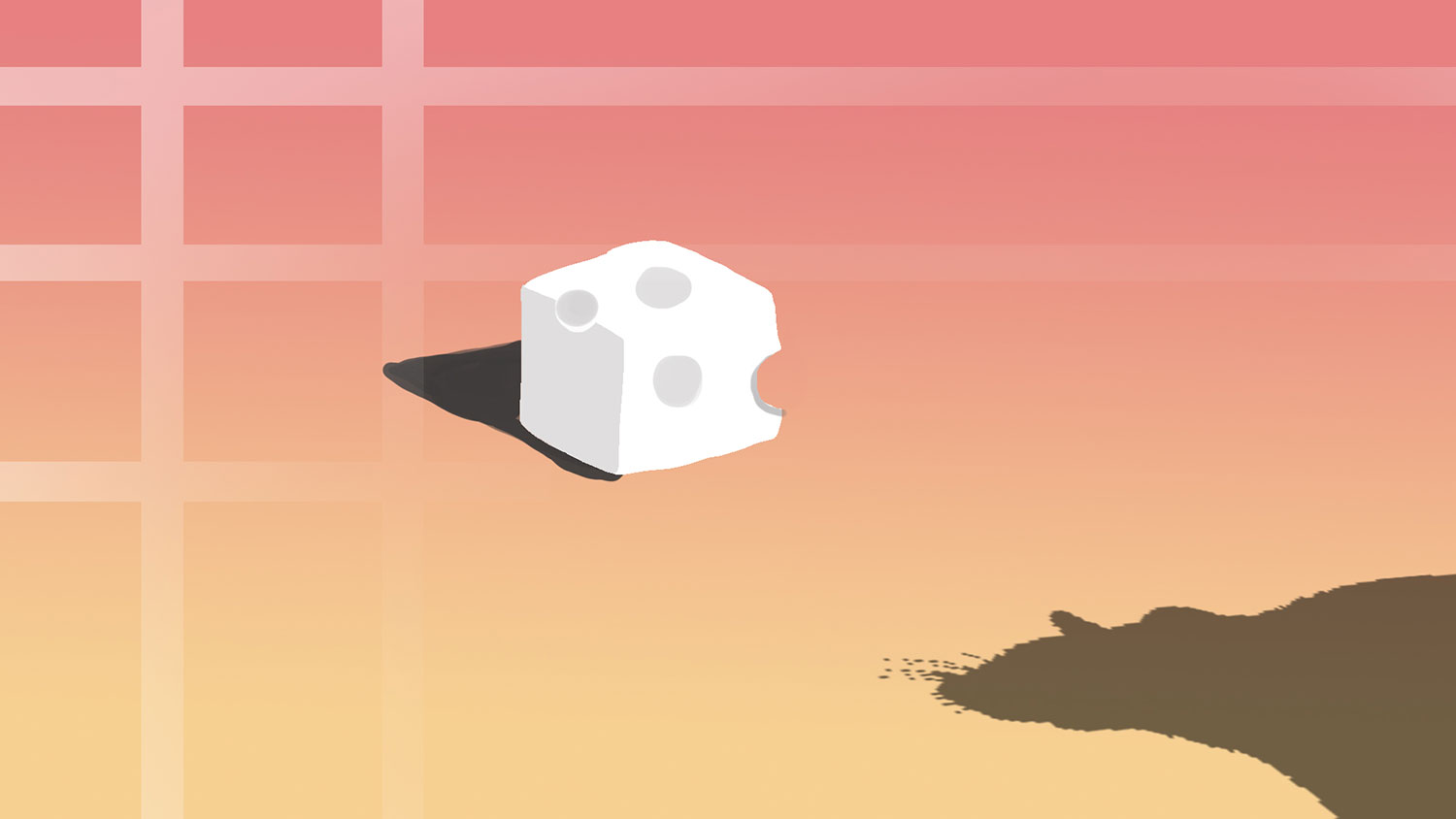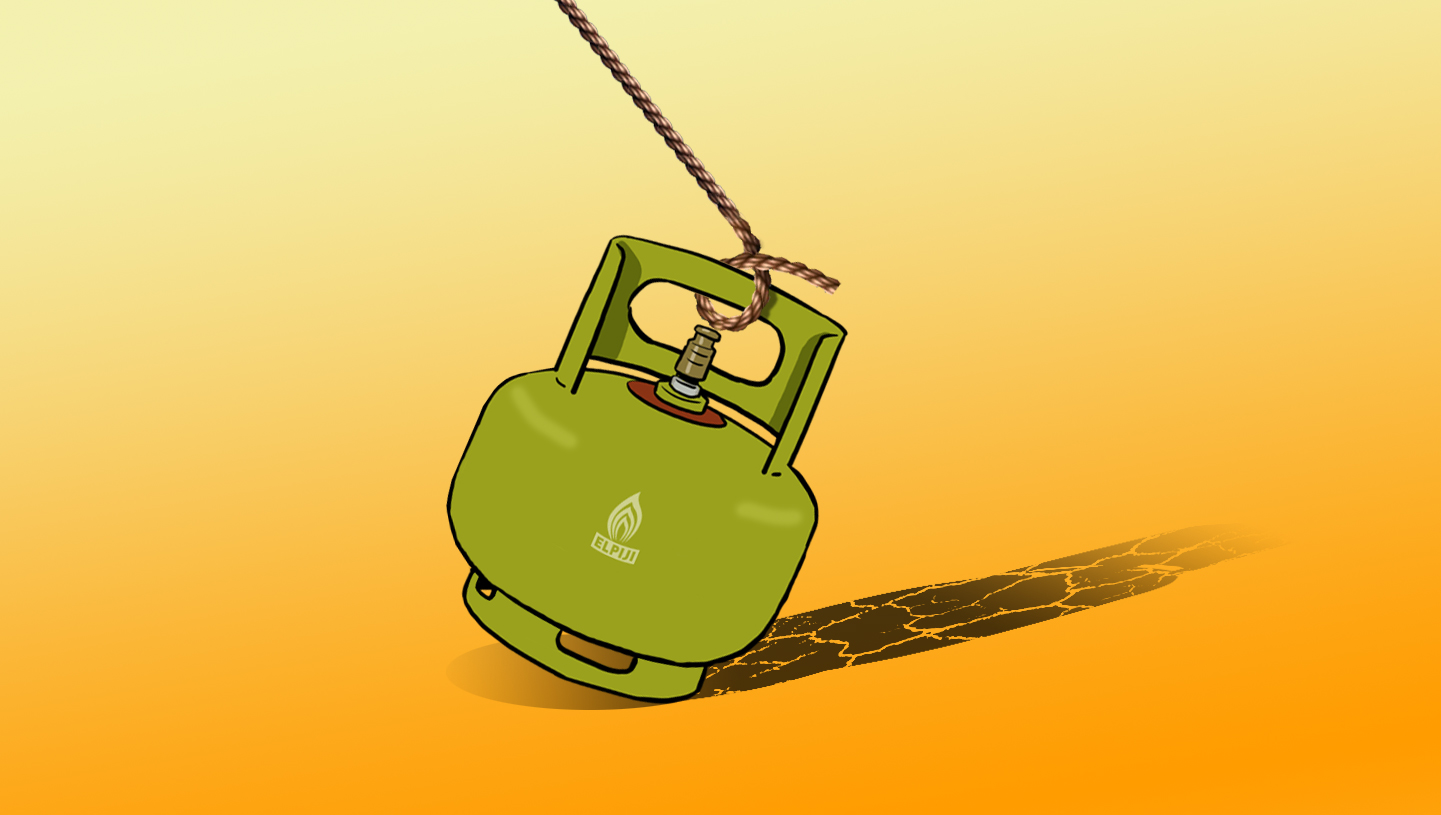Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah jadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Praktik culas seperti ini sudah kerap mewarnai lakon pejabat-pejabat daerah.
Perbaikan sistem pemilihan umum harus menjadi agenda prioritas dari pemerintah.
Kurnia Ramadhana
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepercayaan masyarakat kembali dikhianati. Kali ini pelakunya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Pejabat dengan sederet prestasi mentereng tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat praktik suap dan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pembangunan infrastruktur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Label tersangka kepada Nurdin semakin menambah daftar panjang kepala daerah yang terlibat praktik korupsi. Data KPK menunjukkan, sejak lembaga antirasuah ini berdiri, setidaknya sudah 125 kepala daerah, dari gubernur, wali kota, hingga bupati, yang secara silih berganti mengenakan jaket oranye bertulisan "Tahanan KPK". Ironisnya, para pejabat yang mendapatkan mandat langsung dari masyarakat untuk memimpin daerahnya ini justru merampok dana konstituennya sendiri.
Dugaan korupsi yang dilakukan Nurdin sebenarnya bukan barang baru. Praktik culas seperti ini sudah kerap mewarnai lakon pejabat-pejabat daerah. Polanya pun sangat sederhana. Ada sebuah proyek yang akan dijalankan di suatu daerah. Selanjutnya kepala daerah langsung memerintahkan dinas terkait untuk mempermudah oknum pengusaha tertentu agar bisa mendapatkan paket pekerjaannya. Dalam konteks perkara yang menjerat Nurdin, bekas peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award itu diduga menerima uang senilai Rp 5,4 miliar dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dari beberapa kontraktor proyek.
Melihat modus kejahatan yang dilakukan Nurdin, yang memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik, rasanya tak salah jika dikatakan ia telah terjebak dan terjerembap dalam lingkaran setan korupsi politik. Mengutip kalimat seorang begawan hukum yang baru saja wafat, Artidjo Alkostar, korupsi politik mengindikasikan adanya penyalahgunaan amanat, mandat, dan kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi.
Pertanyaan lanjutannya, apa yang menyebabkan terjadinya korupsi politik? Untuk menjawab pertanyaan ini, rasanya penting untuk melihat kembali editorial Koran Tempo pada Senin lalu. Ada satu kata penting yang mungkin dapat menjelaskan faktor utama adanya korupsi politik, yakni "klientelisme". Praktik klientelisme ini memang sering menyasar negara-negara yang menganut sistem demokrasi, terutama turut pula menghantui aktor-aktor politik pemenang kontestasi pemilihan umum (pemilu). Efek dari praktik tersebut pada akhirnya akan menciptakan relasi negatif yang lazim disebut dengan istilah patron-klien.
Hubungan patron-klien pada dasarnya dapat didefinisikan secara beragam. Dalam konteks praktik korupsi, pola yang terjadi hampir pasti serupa. Setidaknya ada dua model hubungan patron-klien yang sering tampak antara penguasa korup dan kalangan pengusaha. Pertama, patron berupaya mengembalikan modal yang telah diberikan klien saat ia mengikuti proses politik. Pada bagian ini, proses yang dimaksudkan tidak hanya berpusat pada pembiayaan kampanye, tapi juga menyasar saat calon ingin mendapatkan rekomendasi dari partai politik.
Tak bisa dimungkiri, sudah banyak testimoni yang lahir dari kontestan pemilihan umum mengenai mahalnya ongkos rekomendasi partai politik, dari La Nyalla Mattalitti (bakal calon Gubernur Jawa Timur), Siswandi (bakal calon Wali Kota Cirebon), Budi Heriyanto (bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Batubara), Jhon Krisli (bakal calon Wali Kota Palangka Raya), Asmadi Lubis (bakal calon Bupati Toba Samosir), hingga Dedi Mulyadi (bakal calon Gubernur Jawa Barat). Nilainya pun fantastis. Hampir seluruh bakal calon tersebut menyebut angka miliaran rupiah untuk bisa mendapatkan tiket dari partai pengusung.
Setelah itu, pembiayaan lanjutan ada pada fase kampanye. Pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri pada 2019 menarik untuk dicermati. Dapat dibayangkan, biaya kampanye yang harus dikeluarkan peserta pemilihan kepala daerah pada level kabupaten bisa mencapai Rp 25-30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah provinsi bisa melambung hingga ratusan miliar dan bahkan triliunan rupiah. Hal ini tentu tidak bisa dianggap angin lalu. Jika praktik ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan tidak mungkin seluruh kepala daerah akan melakukan praktik korupsi pada waktu yang sama.
Data di atas menjelaskan masalah relasi patron-klien tadi. Maka, menjadi hal yang masuk akal jika kepala daerah kemudian membuka akses selebar-lebarnya bagi pihak-pihak yang telah membantu proses pemenangannya untuk mendapatkan proyek-proyek tertentu.
Kedua, patron akan mencari klien baru dengan memperdagangkan proyek di daerah kekuasaannya demi meraup keuntungan sekaligus mencari tambahan modal untuk mengikuti ajang politik selanjutnya. Praktik ini sering dilakukan oleh para kepala daerah menjelang akhir masa jabatan.
Dalam banyak penindakan KPK yang melibatkan kepala daerah, sebagian di antaranya terkonfirmasi bahwa uang hasil korupsi diduga akan digunakan untuk membiayai pemilihan kepala daerah selanjutnya. Ini tampak dari kasus mantan Wali Kota Kendari, Asrun; bekas Bupati Ngada, Marianus Sae; mantan Bupati Subang, Imas Aryumningsih; bekas Bupati Jombang, Nyono Suharli; dan terakhir mantan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Hal itu membuktikan bahwa dampak negatif relasi patron-klien yang bersumber dari klientelisme bukan sekadar isapan jempol.
Saat ini, Nurdin dan kroninya telah diproses hukum oleh KPK. Namun ada beberapa catatan penting yang mesti disampaikan perihal pengungkapan perkaranya. Pertama, dalam proses penyidikan, KPK harus mendalami adanya kemungkinan penerimaan-penerimaan lain yang diperoleh Nurdin semasa menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Berkaca pada teori klientelisme dan masa jabatannya yang sudah memasuki paruh waktu, besar kemungkinan proyek-proyek lainnya juga dijadikan bancakan korupsi.
Kedua, penyidik juga harus menelusuri aset-aset Nurdin dan membandingkannya dengan laporan harta kekayaannya selama ini. Tatkala ditemukan adanya ketidakcocokkan, patut diduga aset tersebut berasal dari kejahatan, entah melalui pencucian uang ataupun penerimaan-penerimaan gratifikasi.
Ketiga, agar adanya efek jera, saat proses persidangan, penuntut umum harus memasukkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap yang bersangkutan. Hal ini penting agar publik tidak lagi dihadapkan dengan calon-calon yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Lingkaran setan politik ini tidak akan selesai dengan penindakan yang dilakukan oleh KPK. Perbaikan sistem pemilihan umum, terutama pengawasan pada level partai politik dan pembiayaan kampanye, harus menjadi agenda prioritas dari pemerintah. Jika hal itu tidak dilakukan, sistem demokrasi di Indonesia hanya akan menghasilkan pejabat-pejabat yang siap menggarong uang rakyat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo