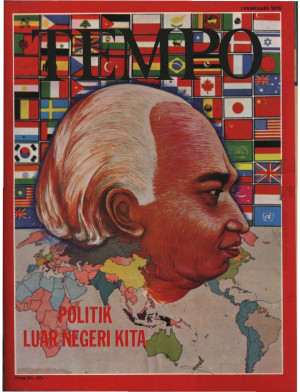SETIAP perumus politik luar negeri Indonesia, sejak Hatta s/d
Adam Malik, akan menyebut dua kata ini: "bebas" dan "aktif'. Di
tahun 1948, misalnya, Bung Hatta di depan Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) bicara dengan judul "Mendayung di antara
dua karang". Waktu itu masalah "pro-Amerika" atau "pro-Rusia"
nampaknya merupakan masalah nyata -- dan Indonesia tak ingin
memihak. Netral? Tidak. Indonesia tak juga ingin pasif, tapi
aktif. Dan "aktif", menurut Bung Hatta dalam tulisannya di
tahun 1953, berarti berusaha bekerja giat ke arah terpeliharanya
perdamaian dan meredanya ketegangan antara dua blok, melalui
usaha-usaha yang sedapat mungkin didukung mayoritas anggota PBB.
Kini Adam Malik, kurang-lebih 10 tahun berturut-turut jadi
Menteri Luar Negeri, pun akan menyebut politiknya bebas dan
aktif. Begitu pula para Menteri Luar Negeri lain sepanjang
sejarah Republik. Hanya bagaimana itu"bebas dan-aktif" dalam
pelaksanaannya agaknya tergantung dari kecenderungan tiap orang,
dan juta keadaan zaman. Di bawah ini adalah ikhtisar gambaran
politik luar negeri Indonesia sejak Kabinet Hatta:
� KABINET HATTA Desember'49 - September'50 dan KABINET NATSIR
(September '50 - April '51): Hubungan dengan Barat umumnya
baik, tapi juga tak menolak hubungan dengan Blok Timur. Hatta
mengirim delegasi ke Uni Soviet musim semi 1950. RRT yang baru
setahun umurnya diakui. Dutabesar RRT diterima Hatta, meski
belum ada duta Indonesia ke Peking. Natsir mengikuti pola ini.
Baik Hatta maupun Natir menyatakan kepada Pilipina di
Konferensi Baguio akhir 1950, bahwa Indonesia tak ingin jadi
anggota blok regional yang anti-komunis dan pro-Barat. Namun
Natsir menghalangi langkah di Parlemen untuk mengakui Ho
Chi-Minh. Sementara itu, tawaran bantuan AS diterima, berupa
pinjaman dan bantuan teknis ekonomis. Tapi bantuan militer AS
ditolak.
Di PBB, sebagai anggota baru, Indonesia abstain waktu resolusi
mengutuk pihak komunis dalam Perang Korea sebagai "agresor".
Sikap ini dikecam oleh partai-partai oposisi, yang menghendaki
agar resolusi itu ditolak oleh Indonesia. PNI menganggap politik
luar negeri Hatta dau Natsir gagal. Kepentingan nasional serta
prestise Indonesia di dunia tak tercermin di situ.
� KABINET SUKIMAN April '51 - April '52) dan KABINET WILOPO
(April '52 - Juli '53): Kedua Perdana Menteri berkecenderungan
memperkuat hubungan dengan Barat, meskipun pendukung mereka
ingin melihat yang sebaliknya. Kedua Kabinet menunda pertukaran
missi diplomatik dengan Uni Soviet. Tapi awal 1953 Parlemen
mengeluarkan resolusi agar hubungan itu dilakukan dalam waktu
setahun. Pertengahan 1951, Kabinet Sukiman menolak 16 pejabat
kedutaan RRT untuk masuk Indonesia tanpa persetujuan lebih dulu
dari Deparlu. Tapi pemerintah menunjuk seorang charge d'affaires
(bukan dutabesar) ke Peking. Soal yang penting ialah soal RRT
dan PBB. Dengan ditopang AS, PBB menyerukan embargo perdagangan
terhadap RRT yang dicap sebagai agresor di Korea. Kabinet
Sukiman ikut, meskipun Indonesia di PBB menyatakan abstain dalam
resolusi embargo itu. Yang paling menyolok dalam masa Sukiman
ialah terbongkarnya usaha pendekatan antara Dutabesar AS
Cochrall dengan Menlu Ahmad Subardjo. Subardjo, begitu kabar di
awal Pebruarl 1952, membuat ikatan dengan AS, sesuai dengan
Mutual Security Act (MSA) yang menghendaki jaminan tertentu
sebagai balasan terhadap bantuan AS. Kabinet Sukiman jatuh
setelah terbongkarnya perundingan rahasia ini. Kabinet Wilopo
yang menggantikannya mewarisi kesulitan perkara MSA itu,
sementara para pendukungnya di kalangan PNI mendesak sikap baru
dalam politik luar negeri -- kira-kira sama dengan desakan PKI.
Desember 1952, Parlemen menyetujui suatu perjanjian baru dengan
AS: bantuan akan diteruskan tanpa Indonesia menyatakan ikatan
apa-apa sebagai imbalannya. Misi Militer Belanda yang ada di
Indonesia dipulangkan, meskipun resolusi di Parlemen agar Irian
Barat direbut dengan kekerasan berhasil dielakkan oleh
pemerintah.
� KABINET ALI (Juli 1953 - Agustus i955): Perbaikan hubungan
dengan Uni Soviet dan RRT dilakukan, dengan pertukaran duta
besar. Indonesia jadi tuan-rumah Konperensi Bandung yang
terkenal itu di tahun 1955. Sikap A-A (Asia-Afrika) pun mulai
nampak dalam masalah jajahan Perancis di Afrika, soal NATO dan
SEATO, Indo Cina, dan krisis Timur Tengah: setidak-tidaknya di
masa ini sikap lebih dekat ke suara Blok Timur ketimbang ke
Blok Barat. Kabinet Ali pertama ini meningkatkan kampanye
perebutan Irian Barat di PBB, dan menyesali pemerintah Taiwan,
Vietnam Selatan dan Korea Selatan.
� KABINET HARAHAP (Agustus 1955 - Maret 1956): hubungan dengan
Barat membaik kembali lebih hangat. Kabinet ini adalah kabinet
Masyumi dan PSI, sementara itu PKI dan PNI dalam oposisi. Tapi
satu-satunya tindakan politik luar negeri yang terpenting di
sini, usaha perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat,
gagal. Kabinet ini mengembalikan mandatnya setelah Pemilu
pertama 1955 selesai.
� KABINET ALI Maret 1956 - April 1957): Pemilihan Umum
memperlihatkan kemajuan kekuatan PNI dan PKI, meskipun golongan
Islam masih merupakan jumlah yang kuat -- cuma terbagi dalam
tiga partai besar. PSI kalah. Dengan perimbangan politik yang
baru itu Ali Sastroamidjojo ditunjuk kembali sebagai Perdana
Menteri. Di masa ini Uni Indonesia - Belanda dikuburkan.
Hutang-hutang Indonesia pada Negeri Belanda juga dinyatakan tak
berlaku. Usaha mengembalikan Irian Barat ditingkatkan di dalam
dan di luar PBB. Indonesia berunding dengan Uni Soviet untuk
pinjaman sebesar AS $ 100 juta dan berunding pula dengan RRT
soal yang sama. Kabinet Ali menyatakan reaksi keras kepada
agresi Inggeris-Perancis di Suez, meskipun tak menyatakan kritik
waktu Uni Soviet "menindak" Hungaria.
Kabinet Ali jatuh karena memburuknya hubungan antara pemimpin
sipil dengan militer. Suasana politik begitu rupa hingga
Presiden Sukarno bertindak: meninggalkan sistem parlementer
Barat. Sejak saat itu. politik luar negeri Indonesia digariskan
sendiri oleh Bung Karno, yang di tahun 1958 membubarkan
Konstituante dan kembali ke UUD '45 -- di mana Presiden tak lagi
cuma "tukang stempel".
� ZAMAN SUKARNO (1958-1966: Tahun-tahun awal masa ini diributkan
oleh pemberontakan para perwira militer di daerah. Para
pemberontak secara resmi dituduh menerima bantuan militer dari
"kaum imperialis". 18 Mei 1958, pasukan pemerintah menembak
jatuh pesawat yang dinaiki oleh Allan Lawrence Pope, warganegara
AS, sebelumnya tentara dan berada di Pilipina serta Taiwan.
Hubungan dengan Blok Barat, khususnya AS, tentu saja memburuk.
Juga hubungan dengan Belanda. Usaha diplomatik untuk
mengembalikan Irian Barat gagal, begitu pula tekanan lain yang
berupa pengambil-alihan milik Belanda di Indonesia yang terjadi
di bulan Desember 1957. Maka Bung Karno pun memutuskan
menghadapi Belanda dengan senjata. Waktu negeri Barat menolak
(tentu saja) melengkapi Indonesia dengan kapal terbang, kapal
dan peralatan lain buat menyerang sebuah anggota NATO, Indonesia
berpaling ke Uni Soviet Januari 1961 pinjaman untuk beli
senjata ditandatangani. 1 Mei 1963, Irian Barat kembali.
Masa ini juga merupakan masa meningkatnya kegiatan -- dan konon
juga massa PKI. Antara Juli 1959 dengan April 1963, PKI
mengklaim suatu kenaikan anggota dari 1,5 juta menjadi lebih
dari 2 juta, sementara anggota organisasi massanya naik dari 7,8
juta sampai dengan 12 juta. Meskipun begitu, politik luar negeri
tak jauh berbeda dari thema "bebas-dan-aktif" yang lama. Setelah
Konperensi Non-Blok di Beograd September 1961, Presiden Sukarno
berpidato di depan Majelis Umum PBB. Ia menyatakan salah
pandangan yang melihat bahwa dunia cuma terbagi dua sebab ada
kekuatan ketiga, yaitu kekuatan Non-Blok. Namun pandangan Bung
Karno ini berubah kemudian, bersamaan dengan masuknya Indonesia
dalam "konfrontasi" dengan Malaysia. Dalam Konperensi Kairo
tahun 1964, Bung Karno mencanangkan "Era Konfrontasi" -- yaitu
antara "the new emerging forces" dengan "the old established
forces" Gagasannya tentang "kekuatan ketiga" dengan demikian
ditinggalkannya, barangkali karena adanya peredaan ketegangan
antara AS dengan Uni Soviet. Kawan utama Indonesia waktu itu
adalah RRT. Indonesia bahkan keluar dari PBB, untuk membentuk
semacam PBB sendiri, Conefo (Conference of the New Emerging
Forces) yang gedungnya kini jadi Gedung DPR di Senayan . . .
� ZAMAN ORDE BARU (1966 sampai sekarang ): Jatuhnya Bung Karno,
hancurnya PKI dan konsolidasi pemerintahan Orde Baru praktis
membalikkan gerak politik luar negeri kita ke arah yang
berlawanan dengan aman Bung Karno. Tentu saja kata "bebas dan
aktif" masih dianggap pegangan. Indonesia masuk kembali ke PBB,
menghentikan konfrontasinya dengan Malaysia dan Singapura,
menyelenggarakan kerjasama regional ASEAN dan mengintensifkan
hubungan dengan negara-negara Barat khususnya yang tergabung
dalam IGGI. Semua tentang ini sudah banyak diketahui. Juga
diketahui pula, meskipun tak selamanya terdengar tegas dan
jelas, kritik bahwa politik luar negeri kita kini "terlalu ke
sebelah Barat". Kritik terbuka B.M. Diah yang dilontarkannya
dalam harian Merdeka baru-baru ini adalah dalam thema itu.
Adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyalahkan Indonesia
dalam masalah Timor Timur memang menyebabkan terbitnya kritik
dan perenungan kembali tentang politik luar negeri kita.
Seakan-akan jadi jelas buat pertama kalinya bahwa Indonesia
"terpencil" di dunia tak punya teman. Benarkah?
Baik suara di Majelis Umum maupun dalam Dewan Keamanan mengenai
satu kasus -- dalam hal ini perkara Timor Timur -- belum dengan
sendirinya membuktikan bahwa ada yang salah dengan pandangan
politik luar negeri kita dewasa ini. Mungkin sebabnya hanya
kurang rapinya koordinasi antara pelbagai lembaga di Indonesia
dalam mengambil keputusan untuk Timor Timur. "Sudah suatu
prestasi bahwa negara-negara Eropa Barat ternyata abstain", kata
seorang pejabat senior, "sebab mereka bisa saja ikut mengutuk
kita". Meski begitu, tak berarti bahwa kasus yang satu di PBB
itu bukan hal yang bisa disepelekan. Diplomasi Indonesia selama
ini memang kurang, dalam hubungan dengan apa yang kini merupakan
suara kuat di PBB, yakni negeri-negeri berkembang. Setidaknya,
bila dibanding dengan seringnya Indoneia bertemu dengan
negara-negara donornya, yang kaya yang tergabung dalam IGGI.
Diplomasi Indonesia di luar itu juga tak seluas dulu: lebih
sering terbatas pada negara-negara ASEAN.
Mungkin karena kenyataan, bahwa ide-ide besar yang mencoba
merangkum kepentingan luas di dunia seperti dulu ternyata kini
tak jalan. Asia-Afrika telah membuat sejarah di tahun 1955, tapi
kemudian solidaritas A-A merosot di sana-sini. Ini terutama
tampak ketika RRT dan India konflik, di masa dua bintang
Konperensi Bandung, Nehru dan Chou En-lai, masih hidup.
Pengertian "Non-Blok" sementara itu memang sering membingungkan,
khususnya di masa detente dan terurai-berainya masing-masing
Blok. Gagasan persatuan negeri berkembang atau "Kelompok 77"
menghadapi negeri maju mungkin satu-satunya yang bisa masih
berarti. Meskipun siapa tahu perpecahan antara negara eksportir
minyak, yang dianggap sudah mulai kaya, dengan negeri miskin
tulen, bakal segera muncul.
Itu tak berarti bahwa zaman ini dapat dibiarkan terus tanpa
gagasan-gagasan penting untuk memperbaiki keadaan dunia,
khususnya di bidang hubungan internasional. Sikap mau
"pragmatis" untuk kepentingan sendiri semata-mata bisa
menjuruskan orang ke politik senang-sendiri yang tanpa moral dan
tanpa solidaritas. Keterlanjuran ke arah itu dapat berakibat
keterpelcilan benar-benar. Dalam politik hubungan
internasional, walaupun sering ada yang kotor, secara obyektif
tetap dibutuhkan sikap beradab. Sebab kita hidup di dunia yang
belum kehilangan akal sehat dan moralitas 100%. Artinya, masih
selalu ada orang lain yang menilai kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini