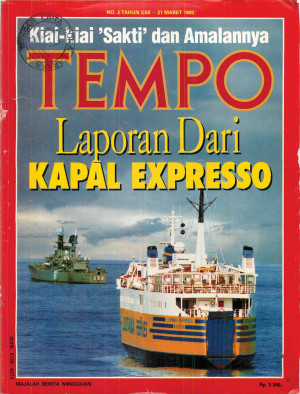INI mungkin tandatanda baik, bahwa suasana keterbukaan di sini telah semakin berkembang. Tak ada lagi kecanggungan seorang pejabat membantah keterangan pejabat yang lain, secara terbuka. Misalnya, Senin malam pekan lalu, Wakil Sekretaris Kabinet, A. Hamid Atamimi, mengundang wartawan di kantornya guna mendengar penjelasan Sekretariat Negara (Setneg) atas pernyataan Menteri Kehakiman Ismail Saleh. "Keterangan Pak Ismail kami nilai tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya," ujar Hamid, yang ketika itu didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris Kabinet, Bambang Kesowo. Keterangan yang menjadi soal itu disampaikan Ismail Saleh kepada wartawan di sela rapat kerja Menteri Kehakiman dengan Komisi III DPR, awal bulan ini. Ketika itu sang Menteri mensinyalir, sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang telah diserahkan Departemen Kehakiman kepada Setneg sampai kini belum diketahui nasibnya. Menurut Ismail, sampai hari ini sudah 12 RUU-nya yang "nyangkut" di Setneg. Di antaranya termasuk RUU yang amat penting seperti RUU Perseroan Terbatas, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan RUU Bantuan Hukum. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan bahwa sebelum dibahas di DPR, RUU yang disusun oleh departemen harus diajukan ke presiden. Sebelum sampai ke tangan presiden, RUU itu harus disampaikan ke sekretaris kabinet, yakni Menteri Sekretaris Negara. Ternyata, menurut Ismail, Setneg bekerja lamban. Ia menduga hal itu disebabkan kurangnya tenaga perancang undang-undang (legal drafter) di lembaga negara yang bertugas memeriksa RUU, sebelum diteruskan ke presiden. "Dulu, sewaktu saya menjadi kepala biro hukum di Setneg, saya rajin memeriksa RUU yang masuk satu per satu. RUU yang masih belum sempurna segera dibuatkan catatan dan diberitahukan kepada instansi pembuatnya agar disempurnakan," kata Ismail Saleh. Sejak 1967, Ismail Saleh memang berkecimpung di Setneg. Terakhir, tahun 1978, ia menjabat sekretaris kabinet. Benarkah Setneg sekarang lamban? Itulah yang dibantah Hamid Attamimi. Masalahnya, menurut Hamid, justru terletak pada departemen maupun lembaga nondepartemen, sebagai pihak yang mengajukan dan menyusun RUU. Sesuai dengan instruksi presiden tadi, bila ide untuk membuat RUU telah disetujui presiden, instansi pemrakarsanya mulai menggarap RUU. Mula-mula menteri yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan instansi lain yang bersangkutan. Ini diperlukan, mengingat jangkauan suatu RUU sering bersifat lintas sektoral. Materi RUU yang akan diajukan Departemen Kehakiman, misalnya, boleh jadi berkaitan dengan urusan Departemen Luar Negeri. Jadi, proses penyusunannya dilakukan oleh "panitia antardepartemen". Bila itu sudah beres, menteri yang punya prakarsa harus melaporkan hasilnya kepada menteri dari instansi yang bersangkutan. Sebab, meskipun staf masing-masing sudah duduk di panitia antardepartemen, mungkin saja menteri yang diajak bekerja sama menggarap RUU itu punya pendapat lain. Bila di tingkat ini tidak terjadi persoalan, baru RUU itu diluncurkan ke Setneg. Ternyata, menurut Bambang Kesowo, mekanisme ini sering ditabrak. "Belum pernah ada satu RUU pun yang sudah selesai di tingkat panitia antardepartemen dikonsultasikan dengan menteri lain. Begitu selesai, langsung saja diajukan ke presiden lewat Setneg," katanya. Akhirnya, ujar Bambang lagi, terpaksa Setneg yang meminta persetujuan menteri-menteri lain yang terkait. Dan ini memakan waktu lama. "Kalau bisa memperolehnya dalam waktu setengah tahun, itu sudah untung setengah mati," tegas Bambang Kesowo. Itu hambatan di proses awal. Hambatan berikutnya terjadi bila ternyata RUU tersebut terpaksa dikembalikan oleh Setneg ke pembuatnya untuk disempurnakan. Pengembalian itu bisa disebabkan karena secara substansial RUU itu masih banyak bolongnya, atau karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara politis. Ternyata, proses ini sering berlarut-larut. Hamid Atamimi memberi contoh bagaimana RUU Pemasyarakatan dikembalikan kepada Departemen Kehakiman untuk diperbaiki karena materinya tidak menggambarkan apa dan bagaimana sistem pemasyarakatan itu. "Nyatanya sampai sekarang kami belum menerima kembali perbaikannya," katanya. Contoh lain, tentang RUU yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara politis, yaitu RUU Perubahan UU Nomor 3 PNPS 1962 tentang Penawanan dan Pengusiran. RUU ini juga diajukan oleh Departemen Kehakiman. RUU ini antara lain berisi larangan terhadap seseorang untuk meninggalkan tempat tertentu. Atau sebaliknya, bisa digunakan untuk mengusir seseorang dari tempat tertentu. Isi RUU ini, menurut Atamimi, masih sama dengan ordonansi tentang Externering dan Internering, yang pernah ada di zaman kolonial. "Dilihat dari segi cita-cita bernegara, falsafah dasar negara, maupun tinjauan hak asasi, secara politis RUU ini sangat sulit dipertanggungjawabkan," katanya. Bila memang banyak RUU yang seperti ini, tugas Setneg, yang kata Mensesneg Moerdiono sebagai pengaman RUU sebelum sampai ke tangan Presiden, tentu bertambah berat saja. Bisa diduga RUU pun akan menumpuk di sana. Apalagi, tampaknya, departemen-departemen kini cukup produktif membuat RUU. Tahun lalu, misalnya, ada 13 RUU yang dibahas di DPR, 7 di antaranya telah disahkan menjadi undang-undang. Sedang tahun 1990 DPR menerima 10 RUU. Dalam jumlah ini belum termasuk RUU yang masih nyangkut di Setneg. Hingga Maret ini, menurut Atamimi, ada 20 RUU yang masih menginap di Setneg. Beberapa di antaranya bahkan sudah beberapa tahun di sana. Perinciannya, 12 RUU diajukan Departemen Kehakiman, 3 RUU dari Departemen Luar Negeri, dan 8 RUU dari departemen lain. Priyono B. Sumbogo dan Linda Djalil
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini