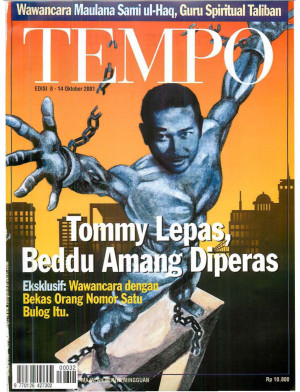BANYAK korupsi, sedikit koruptor. Begitulah keganjilan negeri ini. Hampir setiap hari terdengar keluhan korupsi di mana-mana: kantor polisi, bank, kantor suatu departemen, kelurahan, dan sebagainya. Namun, untuk menemukan seorang saja pe-lakunya, susahnya bukan alang-kepalang.
Indikasi kasus korupsi tak terhingga jumlahnya, diberitakan meriah oleh media massa, tapi tak satu pun maling berdasi yang kunjung dikenali. Sebagian besar jejak perbuatan mereka hilang—sengaja dihilangkan, dilupakan, tertutup kasus berikutnya, atau ”di-SP3-kan” (surat perintah penghentian penyidikan). Bob Hasan, terpidana tujuh tahun kasus korupsi pemetaan hutan oleh PT Mapindo Parama, termasuk di antara yang sedikit itu. Alhasil, korupsi ibarat angin: terasa desirnya, tapi tak jelas wujudnya.
Dalam rangka memotret wajah korupsi itulah, Selasa pekan ini, lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia mengumumkan hasil survei nasional mereka tentang korupsi. Kemitraan merupakan wadah kerja sama antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat madani, sektor swasta di Indonesia, serta masyarakat internasional (United Nations Development Bank, World Bank, dan Asian Development Bank). Lembaga ini diketuai oleh Erna Witoelar dan Nurcholish Madjid.
Adapun survei skala besar itu sendiri merupakan yang pertama di Indonesia. Hasil survei itu penting demi mengonfirmasikan anggapan yang beredar di tengah masyarakat bahwa korupsi memang terjadi di Indonesia. Dalam bahasa Andi Mallarangeng, pakar politik yang menjadi salah satu anggota Kemitraan, ”Akhirnya, kita memiliki fakta tentang bagaimana pendapat orang Indonesia tentang korupsi, dan ini bukan sekadar gosip atau rumor.”
Survei yang berlangsung dari Januari sampai Maret 2001 itu dilaksanakan oleh biro riset Insight. Jumlah respondennya 2.300 orang—terdiri atas kalangan rumah tangga (1.250 orang), bisnis (400 orang), dan pejabat pemerintah (650 orang)—yang berasal dari 14 provinsi.
Dari survei terungkap bahwa sekitar 65 persen responden mengaku pernah menyuap atau menyogok pejabat. Sebaliknya, para pejabat yang diwawancarai dalam survei itu memperkirakan hampir setengah dari mereka (48 persen) memang pernah menerima suap.
Besarnya biaya suap atau sogokan, menurut responden dari kalangan rumah tangga, rata-rata mencapai satu persen dari total pendapatan bulanan mereka. Sedangkan responden dari kalangan bisnis mengaku menghabiskan lima persen dari revenue tahunan untuk ”upeti” bulanan.
Menurut John T. Noonan, penulis buku Bribes: the Intellectual History of a Moral Idea, korupsi memang mencakup praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Adapun bentuk korupsi yang paling umum ditemukan adalah ”suap” dan ”sogok”, yakni pemberian sesuatu kepada pejabat agar yang bersangkutan berbuat sesuatu yang sebenarnya wajib dilakukan secara gratis. (Sebenarnya kan mereka digaji?) Pemberian itu bisa berbentuk uang, mobil, tanah, perhiasan, rumah, seks, makanan dan minuman, perhiasan emas atau perak, saham, ataupun perangkat golf—pendeknya hal-hal yang membuat pejabat ngiler.
Sementara itu, mayoritas responden mempersepsikan korupsi sebagai penyakit yang mesti dibasmi. Responden yang berasal dari kalangan rumah tangga bahkan menilai korupsi sebagai masalah sosial yang sangat serius, malah lebih penting dari urusan pengangguran, instabilitas politik, krisis ekonomi, serta rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan. Itu sebabnya mayoritas responden sepakat menentang praktek tak terpuji tersebut.
Lewat survei tergambar bahwa korupsi terjadi karena beberapa hal. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya mental pejabat disebut responden sebagai penyebab utama terjadinya praktek haram tersebut.
Karakter organisasi sebuah lembaga publik juga sangat menentukan peluang terjadinya korupsi. Manajemen anggaran dan kuatnya nilai-nilai antikorupsi yang dianut oleh suatu lembaga, misalnya. Jika diterapkan, itu merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan tinggi-rendahnya praktek korupsi di dalam lembaga yang bersangkutan ketimbang pengaruh para pegawainya secara individual. Dengan kata lain, semakin bagus sebuah perusahaan mengelola keuangannya, kian rendah pula praktek korupsinya.
Di mata responden, lembaga publik yang paling bersih dari praktek korupsi adalah tempat ibadah—masjid, gereja, pura, dan wihara. Kantor pos, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat juga dinilai responden sebagai lembaga yang relatif bersih. Sebaliknya, lingkungan penegak hukum—jaksa, hakim, polisi, dan terutama polisi lalu-lintas—dianggap sebagai sarang korupsi.
Sayang, walaupun praktek korupsi itu terjadi di depan mata, kebanyakan responden diam saja alias enggan melapor. Sebagian besar dari mereka (71 persen) beralasan tak tahu ke mana harus melapor bila mengetahui adanya korupsi.
Fakta itu memperlihatkan dua hal: responden sudah tak mempercayai aparat penegak hukum, atau kampanye tempat pengaduan korupsi semacam Kotak Pos 9000 yang dulu dikelola kantor wakil presiden (semasa Try Sutrisno) tak efektif mencapai sasaran. Presiden Megawati, yang telah bertekad mendirikan pemerintahan yang bersih, perlu memperhatikan hasil ini. Mekanisme pengaduan korupsi mungkin perlu dihidupkan lagi. Kalau perlu, sediakan saja kotak pengaduan semacam itu di setiap departemen dan kantor pemerintah.
Wicaksono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini