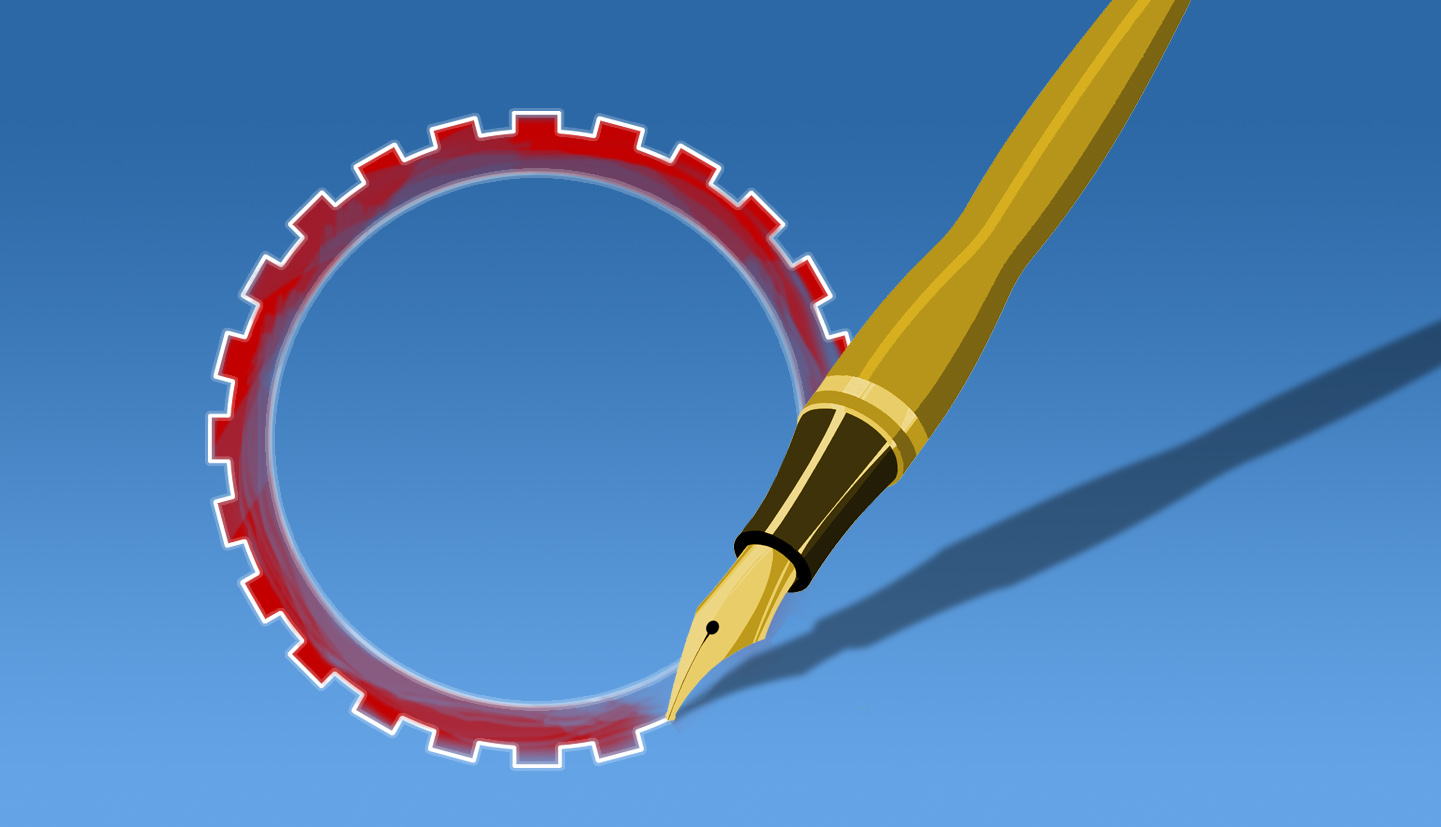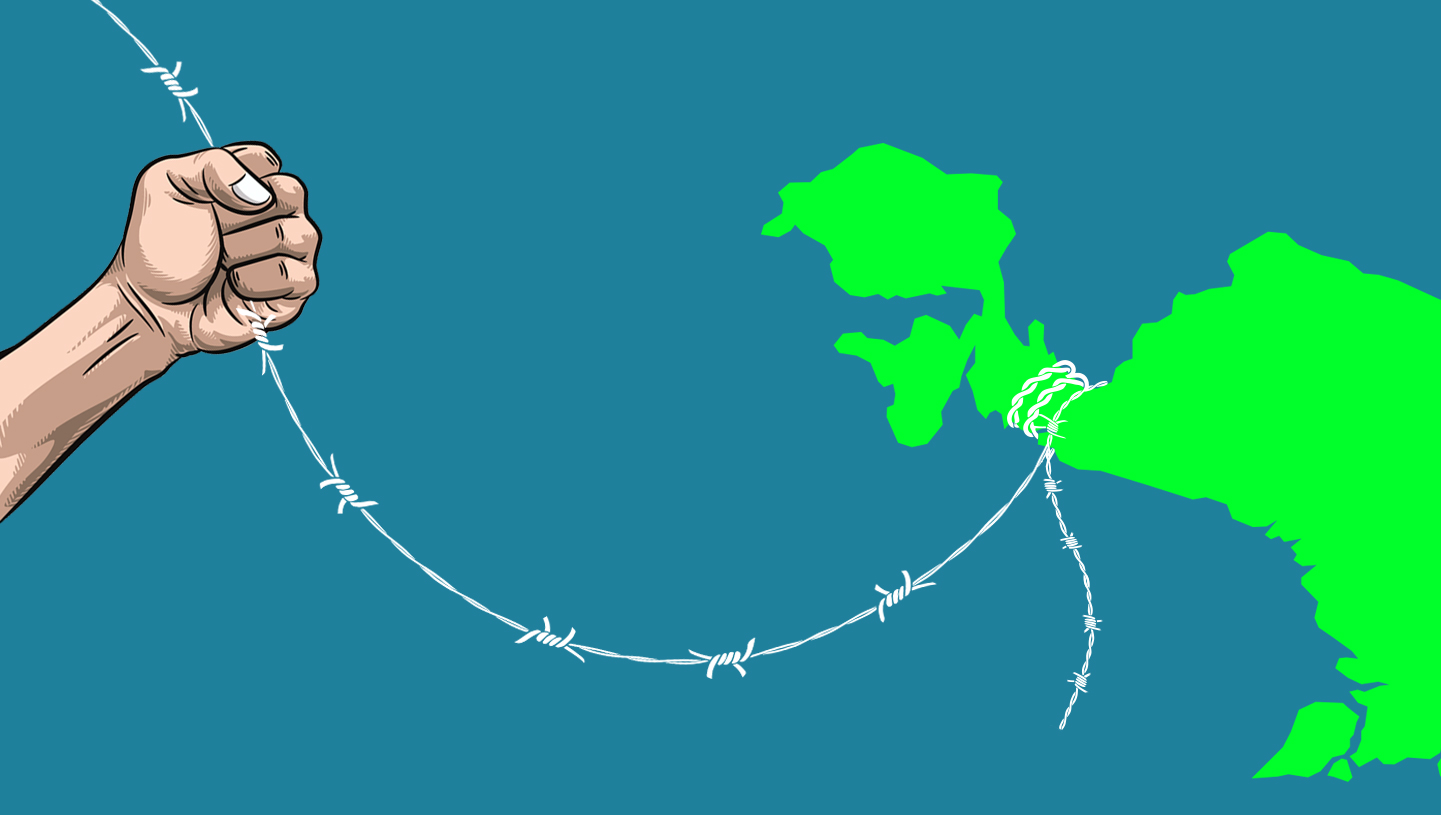Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Serikat pekerja dalam industri media massa sering diperlakukan sebagai ancaman oleh manajemen.
Meskipun indikasi pemberangusan serikat tampak jelas, pelanggaran tersebut hampir tidak pernah diikuti dengan tindakan hukum yang nyata.
Seharusnya keberadaan serikat pekerja yang kuat dipandang sebagai upaya memperkuat demokrasi.
PADA 31 Agustus 2024, hanya selang beberapa jam setelah berdirinya Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI), CNN Indonesia memecat sembilan jurnalis yang menggagas serikat pekerja tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peristiwa ini merupakan satu dari sederetan praktik pemberangusan serikat pekerja di industri media massa Indonesia. Tentu posisi jurnalis yang rentan di bawah kendali korporasi media tidak hanya merugikan hak-hak pekerja, tapi juga membahayakan demokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdirinya SPCI dipicu oleh keputusan sepihak manajemen yang memotong gaji karyawan sebesar 10-30 persen. Manajemen beralasan, langkah ini perlu dilakukan untuk efisiensi di tengah merosotnya bisnis media massa.
Awalnya pemotongan gaji dijanjikan hanya berlangsung selama tiga bulan, dari Juni hingga Agustus 2024. Namun kenyataan berbicara lain. Alih-alih keadaan membaik dan normal kembali, kesejahteraan jurnalis justru makin diabaikan. Maka sejumlah jurnalis berupaya untuk berserikat agar bisa menegosiasikan hak-hak mereka, tapi justru berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Baca juga:
Fenomena ini bukan hal baru dalam industri media massa Indonesia. Tahun lalu, Kantor Berita Antara mencopot Abdul Gofur dari jabatan fungsionalnya karena mengkritik PHK terhadap 32 jurnalis. Meski ia adalah Ketua Serikat Pekerja Antara, kritiknya dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat oleh perusahaan.
Pada 2020, beberapa pengurus Serikat Pekerja Jawa Pos dipaksa menerima tawaran “pensiun dini”. Mereka yang menolak diancam dengan PHK. Lagi-lagi upaya serikat pekerja menyoroti kebijakan perusahaan yang merugikan berujung pada tindakan represif.
Dari berbagai contoh ini, terlihat jelas bahwa serikat pekerja dalam industri media massa sering diperlakukan sebagai ancaman oleh manajemen. Setiap ada upaya untuk menyuarakan kepentingan pekerja, reaksi perusahaan adalah sanksi, baik berupa pemecatan maupun intimidasi.
Pendirian Serikat Pekerja Media Dianggap Tabu
Pertanyaannya, mengapa iklim represif ini tumbuh subur dalam industri media massa di Indonesia? Jawabannya adalah tidak terjaminnya pelindungan hukum terhadap serikat pekerja. Padahal kita memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjamin hak pekerja untuk berserikat.
Pasal 43 Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut bahkan mengancam siapa pun yang menghalang-halangi hak pekerja untuk berserikat dengan pidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda Rp 100-500 juta.
Meskipun indikasi pemberangusan serikat tampak jelas, pelanggaran tersebut hampir tidak pernah diikuti dengan tindakan hukum yang nyata. Manajemen media massa bebas melanggar aturan tanpa takut dihukum. Ketiadaan pengawasan ini menciptakan budaya impunitas di kalangan manajemen, membuat mereka merasa tak tersentuh oleh hukum.
Tidak berjalannya pelindungan hukum terhadap serikat pekerja ini turut melahirkan budaya anti-serikat dalam perusahaan media massa di Indonesia. Di banyak perusahaan media, serikat pekerja masih dianggap tabu. Jurnalis yang berupaya membentuk serikat, bahkan ketika tidak ada konflik industrial, sering dicap sebagai "sok aktivis," yang kemudian dikucilkan.
Budaya semacam ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan pekerja media, dengan ancaman PHK atau penurunan jabatan menjadi risiko yang harus dihadapi mereka yang mencoba menyuarakan pandangannya.
Baca juga:
Inilah mengapa kebanyakan serikat pekerja di industri media baru terbentuk ketika ada kebijakan efisiensi dari manajemen, seperti PHK atau pemotongan gaji. Fenomena berserikat saat nasib telah terkatung-katung adalah sebentuk keberanian yang muncul kala harapan telah hilang. Memang lebih baik keberanian itu datang terlambat dibanding tidak sama sekali, tapi keterlambatan ini punya konsekuensi panjang.
Serikat yang terbentuk secara mendadak ini sering kurang solid sehingga mudah dipecah oleh perusahaan melalui intimidasi atau pendekatan personal terhadap anggota yang vokal. Dalam banyak kasus, upaya konsolidasi yang terlambat sering berujung pada kekalahan di hadapan perusahaan media.
Di balik alasan-alasan ekonomi yang disampaikan oleh manajemen media untuk menolak pembentukan serikat, tersirat kekhawatiran akan hilangnya kontrol atas tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi media yang sepenuhnya berorientasi keuntungan ekonomi, pekerja sering dieksploitasi sebagai alat produksi dalam rantai produksi penyampaian informasi.
Karena itu, pekerja yang memiliki daya tawar dilihat sebagai ancaman terhadap upaya pemilik media untuk mempertahankan kontrol atas distribusi keuntungan ekonomi dan pelaksanaan agenda redaksi.
Baca juga:
Dampak Pemberangusan Serikat Pekerja Media
Pemberangusan serikat pekerja media berdampak lebih luas daripada sekadar urusan hubungan kerja. Jurnalis yang bekerja dalam kondisi penuh tekanan akan kesulitan menjaga independensi dan kredibilitas mereka.
Pemberitaan yang dihasilkan cenderung mengikuti kehendak pemilik media, bukan berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik yang obyektif dan berimbang. Pada akhirnya, publik sebagai konsumen informasi yang dirugikan.
Melihat dampak yang meluas ini, sudah seharusnya keberadaan serikat pekerja yang kuat dipandang sebagai upaya memperkuat demokrasi. Dengan adanya serikat, kesejahteraan jurnalis bisa lebih terjamin, yang memungkinkan mereka bekerja dengan lebih baik dan profesional. Kondisi kerja yang lebih baik akan berdampak langsung pada kualitas jurnalisme, yang pada akhirnya menguntungkan publik.
Namun, sayangnya, harapan untuk perubahan ini masih jauh dari kenyataan. Budaya anti-serikat yang telah mengakar dalam industri media sulit diubah hanya oleh jurnalis. Diperlukan advokasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan terutama Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong pemajuan dan pelindungan hak-hak pekerja di sektor media.
Tanpa tekanan eksternal yang kuat, kondisi jurnalis di Indonesia mungkin akan terus-menerus berada dalam lingkaran masalah yang sama: "diabaikan saat perusahaan untung, dipecat saat krisis".
Dialektika Digital merupakan kolaborasi Tempo bersama KONDISI (Kelompok Kerja Disinformasi di Indonesia). KONDISI beranggotakan para akademikus, praktisi, dan jurnalis yang mendalami dan mengkaji fenomena disinformasi di Indonesia. Dialektika Digital terbit setiap pekan.
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.